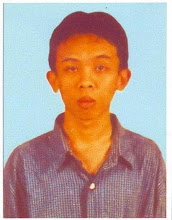Kritik untuk Sistem Pendidikan Indonesia
Menarik sekali membaca tulisan Adi W. Gunawan berjudul Born to be a Genius but Conditioned to be an Idiot dan Sekolah Dirancang Untuk Menghasilkan Orang-orang Gagal. Kedua tulisan ini benar-benar bisa menggambarkan mengapa sistem pendidikan sekolah di Indonesia tidak bisa menghasilkan SDM yang diharapkan. Saya sendiri sering berdiskusi mengenai hal ini bersama teman-teman sejawat, waktu itu saya hanya punya keyakinan bahwa kegagalan sistem pendidikan di Indonesia karena terlalu banyaknya mata pelajaran yang harus dikuasai selama 12 tahun sekolah. Selain itu juga mutu guru yang lebih memilih metoda “menanamkan rasa takut” kepada siswa-siswinya agar mau belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Selebihnya adalah kurangnya praktek di kelas dasar dan menengah mengenai bagaimana berbicara dan mengemukakan pendapat dengan baik dan benar.
Saya ingat betul ketika membahasa mengenai kepahlawanan Pangeran Diponegoro dalam pelajaran sejarah di SMA. Saat itu saya hanya mempermasalahkan dua hal dan ingin sekali berdiskusi mengenai hal itu. Pertama, saya katakan apa alasannya Pangeran Diponegoro itu bisa masuk dalam kategori pahlawan nasional kalau toh motivasi perjuangan yang dia lakukan ternyata hanya gara-gara pembangunan rel kereta api yang melewati tanah makam leluhurnya. Yang kedua, bagaimana nasib proyek pembangunan rel kereta api tersebut setelah perang diponegoro selesai, apakah dilanjutkan atau tidak. Jawaban dari guru sungguh mengecewakan, dan ketika saya debat hasilnya adalah: saya dikeluarkan dari kelas karena katanya saya mengacaukan pelajaran sejarah :(
Atau ketika saya berpendapat dalam “kursus singkat P4″ mengenai pemberontakan G30S/PKI. Yang saya tanyakan dan ingin diskusikan waktu itu adalah masalah kebenaran sejarah. Saya bilang dengan mengutip apa yang dikatakan Napoleon yang kurang lebih bunyinya (persisnya saya sudah lupa), “Sejarah itu hanyalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang menang”. Jawaban yang diberikan –lebih tepat disebut ancama– adalah”, Kamu akan saya buat tidak lulus P4 kalau tetap ngeyel mempermasalahkan hal tersebut!” Semenjak itu pula yang saya lakukan hanyalah mendengar dan menulis pelajaran P4 yang disampaikan … hiks.
Banyak sekali hal-hal yang membuat saya tidak puas dengan sistem pendidikan di Indonesia. Misalnya dengan pelajaran matematika yang ternyata menurut Adi W. Gunawan, dan saya setuju, sangat penting dalam pembangunan konsep diri. Tetapi yang terjadi adalah rasa takut kepada guru matematika yang secara umum terlihat “kejam.” Matematika bukannya dibuat menjadi pelajaran yang menarik tetapi lebih kepada sesuatu yang harus dipelajari dengan pola ditaktor.
Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, baik dari pengalaman pribadi ketika saya mengecap pendidikan maupun setelah saya membaca kedua artikel karya Adi W. Gunawan diatas.
1. Pelajaran yang paling dan sangat penting untuk anak diawal masa sekolahnya sebenarnya hanyalah 3M, yaitu membaca, menulis dan menghitung. Pelajaran lain ditambah ketika 3M sudah dikuasai dengan baik benar.
2. Janganlah terlalu membebani anak sekolah (khususnya SD) dengan mata pelajaran yang sudah banyak itu dengan hasil akhir yang harus bagus semua. Yang paling penting menurut saya adalah matematika dan bahasa ditambah dengan pelajaran moral (tidak harus Pancasila). Karena kita juga tidak mengharapkan orang pintar yang tidak memiliki moral.
3. Penjurusan mulai dilakukan lebih awal, tidak di kelas 2 SMA seperti saat ini, tetapi dimulai sejak SMP. Jadi, ketika seseorang menginjak bangku SMA, dia seharusnya sudah dijuruskan sesuai bakat yang dimiliki. Disinilah peran seorang guru, khususnya guru BP.
Semasa saya SMA sich guru BP kerjanya hanya melerai kalau ada perkelahian, dan saya donkol sekali ketika saya ditertawakan karena ketika ditanya apa cita-cita saya dan saya menjawab ingin jadi presiden
4. Harus ditanamkan bahwa penjurusan dibuat bukan didasari oleh kecerdasan seorang siswa. Hingga kini saya masih merasakan adanya image bahwa yang dijuruskan ke IPA adalah orang-orang pintar dengan nilai rapor yang bagus. Yang agak lemah otaknya di IPS saja. Apakah begitu ? Saya kira dan saya yakin baik IPA dan IPS bukan masalah kecerdasan, tetapi masalah minat dan bakat.
5. Peraturan pendidikan juga harus adil ketika pelajar lulus dari SMA. Jangan sampai, lulusan IPA bisa mengambil jatah kuliah anak-anak lulusan IPS, tetapi lulusan IPS tidak bisa mengambil jatah kuliah lulusan IPA. Nggak fair sama sekali!
6. Sejak mulai SMP, guru-guru harus lebih menanamkan bahwa mata pelajaran itu seharusnya dimengerti, bukan dihapalkan. Tentunya, guru-guru juga harus bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan mengajar seperti jangan membuat soal-soal ulangan yang jawabannya adalah hapalan dsb.
Memang, saya juga mengalami sendiri, bahwa pelajaran 12 tahun itu lebih kepada pelajaran menghapal dibandingkan pelajaran untuk dipahami dan dimengerti.< /i>
7. Hilangkan sistem ranking. Saya cenderung hanya memilih satu orang yang terbaik untuk setiap kelas. Rangking hanyalah membuat orang semakin tidak percaya diri (khusunya bagi mereka yang mendapat rangking-rangking akhir) dan hal ini akan memancing mereka untuk membuat perkumpulan anak-anak pintar dan anak-anak bodoh.
8. Terakhir, cobalah untuk memberikan pendidikan kepada siswa agar berani berbicara, mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. Ini sangat penting untuk kehidupan mereka dimasa yang akan datang.
Sabtu, 28 Februari 2009
Sabtu, 14 Februari 2009
സദന് ഇന്പ് ൨ BESUSU
Visi dan misi SDN Inpres 2 Besusu Palu
Visi : Mewujudkan sekolah dan siswa yang berwawasan IPTEK, berbudi pekerti luhur, kreatif, trampil dan unggul dalam prestasi berdasarkan IMTAQ.
Misi : 1. Melaksanakan pembelajaran tuntas dan bimbingan secara efektif bagi siswa sesuai potensi masing-masing
2. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal
3. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Agama yang dianut dan juga budaya bangsa yang menjadi sumber kearifan dalam bertindak
4. Menciptakan suasana sekolah yang mendukung kehidupan sekolah yang berahklak mulia dan berbudi luhur
5. Peserta didik dapat mempraktekan sikap yang diharapkan oleh pendidik, berbudi pekerti dalam setisp perbuatan
6. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah
7. Menerapkan KBM dan MPMBS dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat
Dasar : Dasar program kerja Kepala Sekolah tahun pelajaran 2008/2009 mengacu pada sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Program kerja dan kalender pendidikan tahun pelajaran 2008/2009, rapat kerja dinas pendidikan kota Palu, program kerja KUPTD Dinas pendidikan Kec. Palu timur, serta hasil rapat kerja guru dan staf pimpinan sekolah
Tujuan : Dalam mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan sangat diperlukan/dibutuhkan adanya Program kerja Kepala sekolah yang diharapkan dapat menjadi acuan sehingga pada akhirnya semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif yang bermuara pada pencapaian hasil maksimal. Pada sisi lain dapat mewujudkan optimalisasi sumber daya sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Inpres 2 Besusu.
Pendekatan :
1. Umum : a. Berorientasi pada tujuan yang berarti bahwa pelaksanaan administrasi sekolah dan hasilnya sangat bermanfaat bagi peserta didik dan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan
b. Berorientasi pada pendayagunaan semua sumber (tenaga dana dan sarana) secara tepat guna dan berhasil guna
c. Berorientasi pada mekanisme pengelolaan administrasi sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian kegiatan sekolah yang dilakukan secara sistematis dan terpadu.
2. Khusus : Pendekatan khusus mengembangkan sikap transparansi/keterbukaan guna memperoleh kepercayaan masyarakat, orang tua siswa, warga sekolah dan praktisi pendidikan. Pelaksanaan administrasi sekolah merujuk pada Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang bertujuan untuk :
a. Memandirikan atau memberdayakan sekolah
b. Mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif kepada semua warga sekolah (Kepala sekolah, guru, karyawan / Penjaga sekolah dan siswa), orang tua siswa dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap mutu sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.
Bidang kegiatan yang direncanakan
A. Umum : Mengadakan rapat dengan dewan guru/Pegawai sekolah untuk
membahas :
1. Penyusunan Program Kerja sekolah
2. Menganalisis kalender Pendidikan
3. Penetapan Visi dan misi sekolah
4. Konsepsi dasar pemutuan pendidikan
5. Pembagian tugas Guru dan penjaga sekolah
6. Mengikuti rapat dinas sekolah
7. Konsultasi dengan pengawas TK/SD dan atasan tingkat kecamatan/kota
8. Koordinasi dengan komite sekolah dan wali murid
B. Kurikulum :
1. Penelaahan Kurikulum
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
3. Penilaian Kurikulum
4. Pengembangan Kurikulum muatan local
C. Program pengajaran :
1. Penelaahan program pengajaran
2. Rencana program pengajaran
3. Penyusunan program Pembelajaran
4. Pelaksanaan Pembelajaran
5. Pengendalian program pengajaran
6. Penilaian Program pengajaran
7. Pelaksanaan supervise pengajaran/kelas
8. Penyusunan kisi-kisi dan soal-soal semester I.II
9. Pelaksanaan evaluasi semester I dan II
10. Pencatatan nilai akhir semester I dan II serta pengisian laporan pendidikan
11. Pelaksanaan hasil analisis evaluasi semester I dan II
12. Pelaksanaan Program perbaikan dan pengayaan setiap kelas/semua mata pelajaran
13. Kenaikan kelas/pembagian raport semester I dan II
14. Penyusunan naskah UAS/UASBN
15. Pelaksanaan UASBN
16. Pencatatan nilai UASBN/UAS dan penentuan kelulusan
17. Pengisian dan penyerahan Ijazah/STL
18. Pelaporan pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa
D. Kesiswaan:
1. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru
2. Penerimaan siswa baru
3. Kegiatan penyesuaian diri siswa baru
4. Bea siswa
5. Mutasi siswa
6. Penata pelaksanaan kesiswaan
7. Pembina kesiswaan
E. Kepegawaian :
1. Perencanaan kebutuhan pengadaan guru dan pegawai tata usaha
2. Pengusulan KGB dan kenaikan pangkat/tingkat guru dan pegawai tata usaha
3. Pembinaan dan pengembangan karier, profesi dan kesejahteraan
4. Ketatalaksanaan tenaga kependidikan
5. Memelihara dan meningkatkan hubungan kekeluargaan
6. Penilaian DP3
F. Sarana / Prasarana :
1. Merencanakan identifikasi kebutuhan
2. Usul pengadaan sarana sesuai kebutuhan
3. memelihara barang yang bergerak dan yang tidak bergerak
4. usul rehabilitasi gedung/ruang kelas
5. Mengusulkan bangunan perpustakaan sekolah
6. Mengatur perpustakaan sekolah dan fasilitas alat peraga
7. Memelihara kebersihan sekolah (7K)
8. Layanan usaha kesehatan sekolah (UKS)
G. Keuangan :
1. Penyusunan RAPBS
2. Kegiatan perncanaan
3. Sumber keuangan, penganggaran dan pengalokasian
4. Pemanfaatan, Pembukuan, Pertanggung jawaban dana
5. Menerima dan menyalurkan gaji guru dan pegawai
6. Pemeriksaan dan pengawasan
H. Humas dan peran serta masyarakat :
1. Mengidentifikasi potensi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program pendidikan
2. Mengadakan rapat, Pengurus komite dan orang tua siswa
3. Mengadakan rapat berkala dengan orang tua siswa kelas I dan kelas VI
4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan pendidikan disekolah
5. Pendataan anak diusia sekolah (wajar) melalui kerjasama dengan lurah, komite dan masyarakat
I. Intra kurikuler :
1. Mengikuti kegiatan KKKS
2. Mendorong dan memfasilitasi guru dalam mengikuti KKG
3. Mengikut sertakan guru dalam kegiatan pelatihan/penataran
4. mendorong guru untuk mengikuti penyeteraan dari DII ke S1
J. Ekstra kurikuler :
1. Pramuka / PMR
2. Pembinaan Olahraga
3. Pembinaan Kesenian
4. Pelaksanaan wawasan wiyata mandala
K. Pelaporan :
1. Laporan bulanan, Kuesioner, Insidentil dan laporan tahunan
2. Laporan pelaksanaan semester I dan II
3. Laporan awal calon peserta UASBN/UAS
4. Laporan akhir pelaksanaan UASBN/UAS
5. Laporan hasil kelulusan pelaksanaan UASBN/UAS
Visi : Mewujudkan sekolah dan siswa yang berwawasan IPTEK, berbudi pekerti luhur, kreatif, trampil dan unggul dalam prestasi berdasarkan IMTAQ.
Misi : 1. Melaksanakan pembelajaran tuntas dan bimbingan secara efektif bagi siswa sesuai potensi masing-masing
2. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal
3. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Agama yang dianut dan juga budaya bangsa yang menjadi sumber kearifan dalam bertindak
4. Menciptakan suasana sekolah yang mendukung kehidupan sekolah yang berahklak mulia dan berbudi luhur
5. Peserta didik dapat mempraktekan sikap yang diharapkan oleh pendidik, berbudi pekerti dalam setisp perbuatan
6. Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah
7. Menerapkan KBM dan MPMBS dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan masyarakat
Dasar : Dasar program kerja Kepala Sekolah tahun pelajaran 2008/2009 mengacu pada sistim Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Program kerja dan kalender pendidikan tahun pelajaran 2008/2009, rapat kerja dinas pendidikan kota Palu, program kerja KUPTD Dinas pendidikan Kec. Palu timur, serta hasil rapat kerja guru dan staf pimpinan sekolah
Tujuan : Dalam mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan sangat diperlukan/dibutuhkan adanya Program kerja Kepala sekolah yang diharapkan dapat menjadi acuan sehingga pada akhirnya semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif yang bermuara pada pencapaian hasil maksimal. Pada sisi lain dapat mewujudkan optimalisasi sumber daya sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Inpres 2 Besusu.
Pendekatan :
1. Umum : a. Berorientasi pada tujuan yang berarti bahwa pelaksanaan administrasi sekolah dan hasilnya sangat bermanfaat bagi peserta didik dan guru dalam pencapaian tujuan pendidikan
b. Berorientasi pada pendayagunaan semua sumber (tenaga dana dan sarana) secara tepat guna dan berhasil guna
c. Berorientasi pada mekanisme pengelolaan administrasi sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian kegiatan sekolah yang dilakukan secara sistematis dan terpadu.
2. Khusus : Pendekatan khusus mengembangkan sikap transparansi/keterbukaan guna memperoleh kepercayaan masyarakat, orang tua siswa, warga sekolah dan praktisi pendidikan. Pelaksanaan administrasi sekolah merujuk pada Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang bertujuan untuk :
a. Memandirikan atau memberdayakan sekolah
b. Mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif kepada semua warga sekolah (Kepala sekolah, guru, karyawan / Penjaga sekolah dan siswa), orang tua siswa dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap mutu sekolah kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.
Bidang kegiatan yang direncanakan
A. Umum : Mengadakan rapat dengan dewan guru/Pegawai sekolah untuk
membahas :
1. Penyusunan Program Kerja sekolah
2. Menganalisis kalender Pendidikan
3. Penetapan Visi dan misi sekolah
4. Konsepsi dasar pemutuan pendidikan
5. Pembagian tugas Guru dan penjaga sekolah
6. Mengikuti rapat dinas sekolah
7. Konsultasi dengan pengawas TK/SD dan atasan tingkat kecamatan/kota
8. Koordinasi dengan komite sekolah dan wali murid
B. Kurikulum :
1. Penelaahan Kurikulum
2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
3. Penilaian Kurikulum
4. Pengembangan Kurikulum muatan local
C. Program pengajaran :
1. Penelaahan program pengajaran
2. Rencana program pengajaran
3. Penyusunan program Pembelajaran
4. Pelaksanaan Pembelajaran
5. Pengendalian program pengajaran
6. Penilaian Program pengajaran
7. Pelaksanaan supervise pengajaran/kelas
8. Penyusunan kisi-kisi dan soal-soal semester I.II
9. Pelaksanaan evaluasi semester I dan II
10. Pencatatan nilai akhir semester I dan II serta pengisian laporan pendidikan
11. Pelaksanaan hasil analisis evaluasi semester I dan II
12. Pelaksanaan Program perbaikan dan pengayaan setiap kelas/semua mata pelajaran
13. Kenaikan kelas/pembagian raport semester I dan II
14. Penyusunan naskah UAS/UASBN
15. Pelaksanaan UASBN
16. Pencatatan nilai UASBN/UAS dan penentuan kelulusan
17. Pengisian dan penyerahan Ijazah/STL
18. Pelaporan pencapaian target kurikulum dan daya serap siswa
D. Kesiswaan:
1. Pembentukan panitia penerimaan siswa baru
2. Penerimaan siswa baru
3. Kegiatan penyesuaian diri siswa baru
4. Bea siswa
5. Mutasi siswa
6. Penata pelaksanaan kesiswaan
7. Pembina kesiswaan
E. Kepegawaian :
1. Perencanaan kebutuhan pengadaan guru dan pegawai tata usaha
2. Pengusulan KGB dan kenaikan pangkat/tingkat guru dan pegawai tata usaha
3. Pembinaan dan pengembangan karier, profesi dan kesejahteraan
4. Ketatalaksanaan tenaga kependidikan
5. Memelihara dan meningkatkan hubungan kekeluargaan
6. Penilaian DP3
F. Sarana / Prasarana :
1. Merencanakan identifikasi kebutuhan
2. Usul pengadaan sarana sesuai kebutuhan
3. memelihara barang yang bergerak dan yang tidak bergerak
4. usul rehabilitasi gedung/ruang kelas
5. Mengusulkan bangunan perpustakaan sekolah
6. Mengatur perpustakaan sekolah dan fasilitas alat peraga
7. Memelihara kebersihan sekolah (7K)
8. Layanan usaha kesehatan sekolah (UKS)
G. Keuangan :
1. Penyusunan RAPBS
2. Kegiatan perncanaan
3. Sumber keuangan, penganggaran dan pengalokasian
4. Pemanfaatan, Pembukuan, Pertanggung jawaban dana
5. Menerima dan menyalurkan gaji guru dan pegawai
6. Pemeriksaan dan pengawasan
H. Humas dan peran serta masyarakat :
1. Mengidentifikasi potensi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan program pendidikan
2. Mengadakan rapat, Pengurus komite dan orang tua siswa
3. Mengadakan rapat berkala dengan orang tua siswa kelas I dan kelas VI
4. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan pendidikan disekolah
5. Pendataan anak diusia sekolah (wajar) melalui kerjasama dengan lurah, komite dan masyarakat
I. Intra kurikuler :
1. Mengikuti kegiatan KKKS
2. Mendorong dan memfasilitasi guru dalam mengikuti KKG
3. Mengikut sertakan guru dalam kegiatan pelatihan/penataran
4. mendorong guru untuk mengikuti penyeteraan dari DII ke S1
J. Ekstra kurikuler :
1. Pramuka / PMR
2. Pembinaan Olahraga
3. Pembinaan Kesenian
4. Pelaksanaan wawasan wiyata mandala
K. Pelaporan :
1. Laporan bulanan, Kuesioner, Insidentil dan laporan tahunan
2. Laporan pelaksanaan semester I dan II
3. Laporan awal calon peserta UASBN/UAS
4. Laporan akhir pelaksanaan UASBN/UAS
5. Laporan hasil kelulusan pelaksanaan UASBN/UAS
Jumat, 13 Februari 2009
Yaku tokaili nisanimu tesana mangge?
BAB I
PENDAHULUAN
Luas Wilayah Dati I Sulawesi Tengah, 63.689.25 km2 atau 6.368,925 Ha.
Sulawesi Tengah pada umumnya di pengaruhi oleh due musim secara tetap yaitu musim Barat yang keying dan musim Timur yang membawa banyak uap air. Musirn .Barat yang keying itu berlaku dari bulan Oktober sampai dengan April yang di tandai dengan kurangnya turun hujan, sedangkan musim Timur yang banyak membawa uap air, yakni pada bulan April sampai dengan Oktober yang ditandai dengan banyaknya turun hujan. Curah hujan di Sulawesi Tengah setahunnya bervariasi antara 800-3000 mm. Kecuali Lembah Palu yang amat kurang mendapat curah hujan, maka variasinya bergerak antara 400-1000 mm saja setahun.
Penduduk yang baru berjumlah satu setengah juta jiwa yang mendiami wilayah ah propinsi yang amat luas itu, dapat dikatakan tidak mudah dapat dengan cepat mengembangkan diri mengelola potensi alam yang besar itu. Namun demikian, keadaan yang dapat dicapai oleh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kehidupan kebudayaannya sejak berabad yang lalu, dapat di katakan tidak' terlampau terisolasi dari perkembangan unum kebudayaan yang terdapat di daerah lain di kepulauan Nusantara ini. Tentu terdapat berbagai faktor yang turut mengambil bahagian dalam perpbentukan kebudayaan penduduk Sulawesi Tengah seperti yang dijumpai sekarang.
Faktor-faktor tersebut antara lain :
1.Gerak perpindahan (migrasi) penduduk pada masa prasejarah yang masuk secara bertahap ke Sulawesi Tengah.
2.Persebaran agama Islam dan Kristen di kalangan penduduk Sulawesi Tengah .
3.Pengaruh dan peranan pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
Beberapa sarjana dalam laporan penelitian mereka telah mencoba melakukan rekonstruksi asal mula persebaran penduduk, serta pertumbuhan kebudayaan yang mereka miliki. Para penulis masa lampau yang amat terkenal seperti Albert C. Kruijt, N. Adriani dan R. W. Kaudren 1).
Rekonstruksi itu didasarkan pada hasil penelitian dan perbandingan dari benda-benda peninggalan praSejarah, bahasa dan mite, serta lagenda penduduk.yang tersebar diberbagai tempat pemukiman yang luas tersebar di wilayah ah ini. Menurut Albert C. Kruijt, daerah yang didiami penduduk Toraja-Sulawesi Tengah itu pada mulanya, lebih dahulu didiami oleh suatu kelompok penduduk yang belum jelas diketahui indan titasnya. Akan tetapi Kleiweg de Zwaan, masih dapat menemukan sisa-sisa dari penduduk Loinang yang berlokasi di Jazirah Timur Sulawesi Tengah.
Dari sini penduduk pembuat tembikar itu menuju ke arah .Utara, ke Daerah Poso Sulawesi Tengah, terus ke daerah Barat, yakni ke daerah Pegunungan Lore, hingga ke daerah aliran Sungai Koro. Dari sana arahnya, kemudian membelok kembali ke Selatan dan berhenti di suatu tempat yang bernama Waebunta, suatu tempat di daerah Galumpang yang kini termasuk wilayah ah Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan.
Migran Pottenbekkers ini menurut Kruyt ada juga yang datangnya dari arah laut (Selatan Makassar ), memasuki daerah Palu dan menyebar ke Lembah Palu. Penduduk pendatang baru itu, membawa anasir kebudayaan baru ke dalam kehidupan penduduk pribumi Lembah Palu, dalam lapangan sosial ekonomi dan relegi, antara lain sebagai berikut :
1.Dalam lapangan ekonomi diperkenalkan teknik pertanian berpengairan.
2.Dalam lapangan relegi disumbangkan satu sistem yang mengenal struktur dewa-dewa yang bertingkattingkat. Disamping itu juga diperkenalkan upacaraupacara keagarnaan yang rumit.
3.Dalam lapangan kehidupan sosial diperkenalkan jumlah peraturan baru, termasuk innovasi dari suatu lapisan sosial baru, yakni lapisan bangsawan, yang berada di atas lapisan sosial yang telah ada lebih dahulu berlaku dalam masyarakat, yaitu lapisan budak dan merdeka.
Eksistensi lapisan sosial bangsawan, sebagai lapisan baru ini terikat pada mite/legenda Sacaerigading dan Manuru Lasaeo. Unsur-unsur kebudayaan baru yang datang bersama orangorang pendatang baru itu, menurut Kruyt diperkirakan berasal dari unsur-unsur kebudayaan Hindu 'Jawa, yang berasal dari Pulau Jawa. Tentang mite/legenda Sawerigading yang terdapat dalam epos Galigo sebagai tokoh orang Bugis di Sulawesi Selatan, diduga persebarannya sebagai tokoh legendaris di Sulawesi Tengah meliputi daerah yang amat luas dari pantai Barat di Selat Makassar, sampai ke Luwuk Banggai di Teluk Tolo.
Selain terjadi migrasi yang berasal dari luar Sulawesi, sepanjang kehidupan penduduk Sulawesi Tengah, terjadi pula beberapa migrasi lokal. Kaudern membahas mengenai migrasi yang berlangsung di Sulawesi Tengah dalam bukunya menyatakan bahwa perpindahan penduduk di daerah ini terjadi karena berbagai sebab, seperti bencana alam, epidemi penyakit dan adat berperang di antara desa-desa. 2) Perang-perang yang amat sering terjadi itu, bertalian erat dengan adat pen,gayauan mereka. Suasana peperangan itu mengakibatkan penduduk desa acapkali mengungsi lebih jauh ke daerah pedalaman yang sukar dijangkau oleh musuhnya. Sebagai akibat lebih jauh dari adat peperangan ini, timbullah lembaga yang berasal dari tawanan perang, pada beberapa kolompok kaum yang besar di Sulawesi Tengah. Juga punahnya sesuatu kaum tertentu, adalah sebagai, akibat adat peperangan itu, seperti yang diambil oleh kepunahan kelompok kaum To Pajapi.
Pemukiman penduduk sebagian besar terpusat disepanjang pantai (71,21%); tersebar dipedalaman (17,15%), termasuk penduduk yang hidup terpencil dipegunungan, berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa, dan selebihnya di daerah kepulauan, (11,64%).
Menurut biasanya, seperti umumnya yang dikemukakan dalam laporan penelitian mutahir 4) SulawesiTengah itu didiami oleh banyak jenis kelompok Etnik (Suku Bangsa), dan terbesar di empat buah Kabupaten, dalam gambar kasarnya sebagai berikut.
Kelompok Etnik (1). Kaili (2). Tomini, (3). Kulawi, umumnya berdian di Kabupaten Donggala. Kelompok-kelompok Etnik (4). Pamona, (5). Lore, (6). Mori, (7). Bungku, umumnya berdiam di Kabupaten Poso. Kelompok-kelompok Etnik (8). Saluan, (9). Balantak, (10). Banggai,umumnya bermukim di Kabupaten Luwuk Banggai. Kelompok-kelompok Etnik (11). Toli-Toli, dan (12). Buol, umumnya bermukim di Kabupaten Buol ToliToli. Dua belas buah kelompok Etnik inilah yang umumnya menjadi pedoman pembagian kelompok Etnik (suku-bangsa) di Sulawesi Tengah.
Cara pengelompokan Etnik tersebut biasanya menurut pengolompokan "bahasa", atau nama tempat pemukiman", mengikuti apa yang sudah dipublikasikan para penelitian sebelumnya.
Di antara kedua belas kelompok Etnik yang manjadi penduduk (asli) Sulawesi Tengah, maka kelompok Etnik Kaili-lah yang terbesar jumlahnya,yaitu kira-kira 45 % dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tengah.
Kelompok kaum atau etnik yang diidentifikasi k rnenurut bahasa yang dipakainya, biasanya digolongk ke dalam narna rumpun bahasa, seperti orang Mela karena berbahasa Melayu, Orang Bugis karena berbaha Bugis; orang Sunda karena berbahasa Sunda dan sebaga nya. Karena pemakaian bahasa itu amat luas terset oleh penutur yang berbeda beda asal tempat tinggalny maka disebutlah misalnya : Orang Melayu Riau; ora Bugis Rappang; orang Sunda Bogor, dan sebagainya. Juga biasa digunakan simbol atau kata tertentu dal suatu bahasa umum yang luas tempat tinggal penuturn tak dapat dibatasi oleh nama tempat saja, maka dipil simbol atau kata khusus dalam dialek bahasa (serumpu itu seperti digunakan oleh Adriani dan Kruijt men identifikasi kan dialek-dialek dalam kalangan apa ya disebutnya Toraja, dengan menggunakan kata sangka seperti Tae, Rai, Ledo, Da'a dan lain-lain yang semu nya berarti "Tidak". Dengan kaitan itu, dibedakann Toraja Tae dari Toraja Data dan'sebagainya.
Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut ci kebudayaan tertentu, seperti To-Panambe, orang ya bermata pencaharian hidup dengan menggunakan al penangkap ikan yang disebut "Panambe": To-Ri-je'n orang (kaum) yang seluruh kehidupannya terletak air. Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut temp kediamannya seperti To-Palu, To (ri) Palu, ialah ora atau kaum yang bermukim di Palu, atau yang beras dari negeri Palu.
BAB II
TO-KAILI (ORANG KAILI)
Wilayah ah propinsi/Dati I Sulawesi Tengah, seperti yang disebut pada permulaan tulisan ini, terdiri atas empat buah daerah Kabupaten/Dati II, didiami oleh kelompok-kelompok etnik, secara umum, menurut daerahdaerah Kabupaten itu di kelompokkan sebagai berikut:
1.To-Kaili, dengan sejumlah sub-etnik antara lain, To-Palu, To-Sigi, To-Dolo To-Biromaru, To-Kulawi, To-Parigi dan lain-lain.
2.To-Pamona dengan sejumlah sub-etnik seperti ToMori, To-Bungku dan lain-lain.
3.To-Banggai dengan sekelompok sub etnik yang berdekatan seperti To-Saluan, To-Balantak dan lain-lain.
4. To-Buol Toli-Toli, dengan sejumlah kelompok kaum yang kecil-kecil.
Diantara kelompok -Kelompok etnik itu yang akat menjadi pokok bahasan tulisan ini ialah kelompok etnil To-Kaili. Kelompok etnik To-Kaili inilah yang terbesai jumlahnya, dan persebarannya dalam seluruh wilayah al propinsi yang amat luas. To-Kaili pada dewasa inmenempati jumlah terbesar yang mendiami daerah kabupaten/ Dati II Donggala, dan sebahagian lainnya bermukir di beberapa wilayah ah kecamatan dalam daerah kabupatei lainnya. Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai ToKai, karena adanya persamaan dalam bahasa dan ada; istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumbei asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua. Fra dalam kalangan semua To-Kaili, digunakan secara umum, Disamping itu terdapat banyak dialek bahasa Kaili van,, juga menjadi identifikasi (sering kali tajam) dari. sut kultur atau sub etnik To-Kaili yang berdiam pada wilayah ah-wilayah ah yang sering kali masih amat terisolasi.
1.To-Palu (To-ri-Palu)
2.To-Biromaru
3.To-Dolo (To-ri-Dolo)
4.To-Sigi (To-ri-Sigi)
5.To-Pakuli, To-Banggai, To-Baluase,To-Sibalaya, To Sidondo
6.To-Lindu
7.To-Banggakoro
8.To-Tamunglcolowi dan To-Baku.
9. To-Kulawi
10.To-Tawaeli (to-payapi)
11..To-Susu, To-Balinggi, To-Dolago
12.To-Petimbe
13.T0-Rarang gonau
14.To-Parigii
Dalam kalangan sub etnik tersebut acap kali terjadi penggolongan yang lebih kecil lagi, dengan ciriciri kliusus, yang kelihatnnya lebih dekat kepada kelompok kekerabatan, yang menunjukkan sifat satuan geneologisnya.
Untuk menemukan pengikat solidaritas dalam kelompok etnik To-Kaili, dicoba diternulcan segala sesuatu yang berbau mitologi, atau cerita-cerita tokoh legendaris atau cerita-cerita rakyat (folk-tale) dalam kalangan To-Kaili dan sub etnik yang terhisap di dalamnya.
To-Kaili yang mendiami Lembah Palu memilki cerita rakyat (folk-tale) yang menjadi pengikat rasa kesatuan To-Kaili tentang asal-usul mereka 4). Tana Kaili yang te-rletak di Lembah Palu (sekarang), menurut ceritera rakyat itu, pada •zaman dahulu kala Lembah Palu ini, masih lautan, di sebut Laut Kai1i atau Teluk Kaili. Nenek moyang To-Kaili pada zainan dahulu itu mendiami lereng-lereng gunung sekeliling Laut Kaili. Konon, di sebelah Timur Laut Kaili itu, terdapat sebatang pohon besar, turnbuh kokoh, tegak dengan kemegahan menjulang tinggi, sebagai tanda pengenal daratan bagi pelaut yang memasuki teluk Kaili. Pohon itu dinamakan Pohon Kaili. Pohon itu tumbuh dipantai dan terletak antara negeri Kalinjo dengan negeri Sigipulu.
Pada suatu hari Laut Kaili mendapat kunjungan sebuah perahu layar yang amat besar, dibawah pimpinan seorang pelaut luar negeri yang namanya sudah arnat tersohor dikawasan ini. Pelaut itu bernama SAGJExIGADING 5). Dikatakan Sawerigading itu, singgah di Teluk Kaili dalam perjalannya kembali dari Tana Cina, menemui dan mengawini tunangannya yang bernama We Cudai. Tempat yang disinggahi pertama oleh perahu Sawerigading, ialah negeri Ganti, ibu negeri Kerajaan Banawa (sekarang Donggala). Antara raja Banawa dengan Sawerigading terjalinlah tali persahabatan yang dilcolcohkan dengan perjanjian ikatan persatuan dQngan kerajan Bugis-Bone, di Sulawesi-Selatan 6). Dalam menyusuri teluk lebih dalam ke arah Selatam sampailah Sawerigading dengan perahunya ke pantai negeri Sigipulu, dalam wilayah ah kerajaan Sigi. Perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan Uwe Mebere, yang sekarang berna~-na Ranoromba. Kerajaan Sigi dipimpin oleh seorang Raja Wanita yang bernama Ngginayo atau Ngili Nayo 7). Raja perempuan ini, belum kawin dan berparas amat cantik. Setibanya di Sigi Sawerigading bertemu langsung dengan raja Ngilinayo yang amat cantik itu. Pada pandengan pertama Sawerigading jatuh cinta. lapun mengajukan pinangan untuk menjadikannya pei-maisuri. Raja Ngilinayo bersedia rnenerirna pinangan Sawerigading dengan syarat ayarn aduannya yang bergelar Calabai 3). dapat dikalahkan oleh ayam aduan Sawerigading yang bergelar Bakka Cimpolon,g (Bg), yaitu ayam berbulu kelabu ke hijauan, dan kepalanya berjambul. Syarat itupun disetujui oleh Sawerigading, dan disepakati, upacara adu ayam itu akan dilangsungkan sekembal Sawerigading dari perjalanan ke pantai Barat, sambi di persi.apkan arena (Wala-wala) adu ayam.
Di pantai Barat perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan negeri Bangga 9). Raja Bangga seorang pe rempuan bernama Wumbulangi di gelar Magau Bangga, yan diceritralcan sebagai To-Manuru 10) Sawerigadingpu menemui baginda dan mengikat perjanjian persahabatan dalam daftar silsilah raja-raja Bangga, Wumbulang adalah Ma~au pertama kerajaan Bangga.
Setibanya di Sigi, Arena untuk penyabungan ayan di atas sebuah gelanggang (wala-wala) sudah dipersiapkan. Ayarn sabungan Sawerigading Bakka Cimpolonp yang akan bertarung melawan Calabai ayam Ngilinayo, semuanya siap di pertarunglean. Pada malam harinya telah diumumkan kepada segenap Iapisan masyarakat, tentank pertarungan yang akan berlangsung ke-esokan paginya. Akan tetapi sesuat.u yang luar biasa telah terjadi pada malarn sebelum pertarungan itu berlangsung, yang menjadi sabab dibatalkannya pertarungan itu.
Anjing Sawerigading yang digelar La-Bolong (SiHitam) turun dari perahu, berjalan jalan di darat Sigi. La-Bolong berjalan ke arah Selatan. Tanpa disadarinya, ia terperangkap kedalam satu Iobang besar, ternpat kediaman seekor belut (Lindu), yang amat besar. Karena merasa terganggu oleh kedatangan anjing labolong yang tiba-tiba itu, maka belut/lindu itupun menjadi marah, dan menyerang La Bolong, maka terjadilah pertarungan yang amat sengit antara keduanya. Pertarungan itu demikian dahsyatnya, sehingga seolah-olah terjadi gempa yang menggetarkan bumi. Penduduk pun menjadi, ketakutan. La-Bolong berhasil menyergap belut/lindu itu, keluar lobangnya. Lobang besar bekas tempat tinggal belut/lindu itu, setelah kosong dan runtuh, lalu menjadi danau, yang hinga kini disebut Danau Lindu.
Anjing Sawerigading La-Bolong melarikan belut itu kearah Utara dalam keadaan meronta-ronta, dan menjadikan lubang berupa saluran yang dialiri oleh air laut yang deras, air yang mengalir dengan deras itu, bagaikan air bah yang tumpah, menyebabkan keringnya air Kaili. Maka terbentuklah Lembah Palu dan terjelmalah Tana--Kaili.
Peristiwa alam yang amat dahsyat ini, membatalkan pertarungan kedua ayam yang telah dipersiapkan dengan cerrnat. Raja Ngilinayo dan Sawerigading sama-sama berikrar untuk hidup sebagai saudara kandung yang saling menghormati i untuk bekerja sama membimbing orang Kaili yang mendiarni Lembah Palu, bekas Teluk Kaili, yang telah menjadi daratan.
Air yang mengalir deras ke laut lepas Selat Makassar menghanyutkan perahu Sawerigading, yang akhirnya terdampar di Sombe. Ceritera rakyat rnenyebut, bahwa gunung yang menyerupai perahu di Sombe itu, adalah bekas perahu Sawerigading yang sekarang di Bulusakaya, yang berarti gunung yang berbentuk perahu. Alat-alat perlengkapan perahu lainnya, antara lain layar, terdampar di pantai sebelah Timur. Tempat itu kini bernama Bulumasomba, artinya gunung yang menyerupai layar.
Sebuah versi lain, mengenai ceritera persaudaraan antara Raja Ngilinayo dengan Sawerigading, menyebutkan bahwa pada menjelang akan diadakannya pertarungan ayam, di adakanlah pesta atau keramaian yang dikunjungi oleh sebahagian besar penduduk kerajaan Sigi. Ferangkat alat kesenian, bunyi-bunyian berupa gong, tambur dan seruling, didaratkan dari perahu Sawerigading, untuk meramaikan pesta kerajaan itu. Gong, tambur, dan genderang dipalu bertalu-talu, memeriahkan pesta itu, mengundang kera:iaian yang gegap gempita. Urang sakitpun yang tadinya terbaring lemah di pembaringan masing-masing, setelah mendan gar bunyi-bunyian itu. Merekapun menghadiri pesta keramaian itu. Penyembuhan dari penyakit, berkat mendan garkan bunyi-bunyian yang mengiringi nyanyian (t'embang), yang diperagakan dengan tari-tarian, dipercaya sebagai obat mujarab. Pengobatan dengan cara itu, disebut Balia, dari dua kata bali + ia artinya lawan ia. Maksudnya setan atau roh jahat yang membawa penyakit harus dilawan.
Puncak acara keramaian malarn itu, ialah peresmian atau pengukuhan sumpah setia persaudaraan antara raja Sigi Ngilinayo dengan Sawerigading. Segenap perangkat alat bunyi-bunyian, diserahkan oleh Sawerigading kepada saudaranya, yaitu Raja Sigi Ngilinayo. Seusai pesta Kerajaan itu, kembalilah Sawerigading dengan anak buahnya ke perahu. Setelah mereka tiba di perahu, mereka dikejutkan oleh adanya getaran bumi yang dahsyat disertai deru air yang bagaikan tautan keras. Dikatan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kareria pergelutan antara Labolong dengan belut/lindu, seperti diceriterakan didepari. Perahu Sawerigadirlg terlepas dari tambatannya, dan hanyut mengikuti arus air ke laut.lepas, Selat Makassar. Berkat lcetangkasar: awak perahu Sawerigading, menyelematkan perahun,da dari malapetaka. Mereka melepaskan diri dari Teluk Kaili yang sudah menjadi daratan, dan selamatlah Saweriading meneruskan perjalanannya kembali ke Tana-Bone Sulawesi-Selatan).
Sawerigading adalah tokoh legendaris dalam ceritera rakyat Tana Kaili. Tokoh itu dihubungkan dengan kedudukan Kerajaan Bone, sebagai kerajaan Bugis di Sulawesi-Selatan yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kai1i. Dapat diperkirakan bahwa hubungan-hubungan yang akrab dengan kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kaili, berlangsung dalam abad ke-17. Adapun tokoh lagendaris Sawerigading di Sulawesi Selatan tersebut dalaiu Epos La-Galigo, dipandang sebagai peletak dasar dan cikal bakal raja-raja Bugis, khususnya di Kerajaan Lucau, yang terletalc pada bahagiaii Utara Selat Bone. Zaman Sawerigading dalam Epos La-Galigo, diperkirakan berlaiigsung dalam abad IX dan X (M). Kedua keadaan itu dalam cerita rakyat Tana Kaili, yaitu tokoh iegendaris Sawerigading dan hubungan persahabatan dengan kerajaan Bone, dipadukan saja sebagai pe-ristiwa istimewa dalam suatu cerita rakyat. Hal seperti itu, adalah biasa dan menjadi karastrestik umum dari suatu cerita rakyat (Folk-Tale), untuk memperoleh semacam pengukuhan legitimasi bagi tokoh-tokoh yang tersangkut dalam peristiwa luar biasa 12). Mungkin sekalli dapat dibuktikan kebenaran ilmi.aluiya, melalui penelitian (arkeologi atau paleoantropologi), bahwa sekitar abad IX-X (M), Lembah Palu masih merupakan lautam sampai negeri Gangga dekat Danau Lindu. Setelah Laut Kaili menjadi daratan, yang membentuk Tana-Kai di Lembah Palu, maka terjadilah hubungan dangan kerajaan Bone dan Gowa yang menguasai perairan Selat Makassar. Ketika itu Kompeni Belanda (VOC) juga sudah mulai melakukan kegiatan intervensi terhadap kerajaan kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Peristiwa-peristiwa penting itu justeru terjadi dalam abad ke XVII. Sekitar abad itu , kerajaan Bone mengunggu kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan di baw pimpinan Aruppalakka, To-Erung malamppee' Gemme' n Ketika itu Kerajaan Bone melakukan hubungan baik m lalui daratan, maupun lautan ke bahagian Timur d Barat Nusantara, termasuk Sulawesi Tengah dan Utar Tana Kaili dan kerajaan Banawa amat banyak di sebabkan dalam Lontara Bugis-Makassar tentang hubungannya , politik dan persaudaraannya dengan negeri-negeri Bugis yang menguasai pelayaran Selat Makassar.
Pada dewasa ini, persebaran pemukiman To-Kaili propinsi Sulawesi Tengah, meliputi sebahagian terbes Kabupaten/Dati II Donggala, dan beberapa wilayah Kecamatan dalam Kabupaten/ Dati II Poso, Banggai d Buol Toli-Toli. Kelompok etnik Tiriombo, Tomini d Moutong yang mendiami pesisir sebelah Timur di Tel Tomini, tadinya masih dapat dipertajam identifikasinya yang berbeda dari kelompok etnik To-Kaili. Teta kini, dilihat dari perkembangan persebaran penerima unsur-unsur kebudayaan yang sama,: maka perbedaa perbedan itu menjadi sangat tipis. Malahan percampur rnelalui jalan kawin-mawin yang amat banyak, teruta dalam kalangan pemuka adat dan masyarakat Kaili dan g To-Tinombo, To-Tomini dan To-Moutong, perbedaan yang pernah mempertajam identifikasi etnik masing-masi kini sudah mencair.
Cacah jiwa orang Kaili yang tersebar luas dal Propinsi Sulawesi Tengah, diperkirakan 45 % dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah, yaitu kira-kira 4 sampai 5 ratus ribu jiwa. To-Kaili pada umumnya atau terbanyak bermukim di sepanjang pantai, baik di pesisir Barat, maupun dipesisir Timur. Oleh karena itu, maka cara hidup clan kebudayaan Kaili yang dominan, kelihatan lebih dekat kesamaannya kepada kebudayaan Bugis-Makassar (Sulawesi-Selatan), dan kebudayaan Melayu (Sumatera dan Malaka ).
Selain dari pada kelompok etnik Kaili, Pamona, Buol Toli-Toli, Banggai dan lain-lain, seperti telah disebut pada bahagiarr depan, masih terdapat lagi keiompok-kelompok etnik dalam jumlah warganya yang tidak , terlalu banyak, tetapi mereka dipandang' sebagai penduduk asli Sulawesi Tengah. Mereka itu kini disebut suku-suku terasirlg, seperti : Lauje, Tajio, Pendau, To-Lare,. Rarang Gonau, Loon , Sea-sea, Daya dan mungkin masih ada lagi lainnya yang belum di kenal. Kelompok-kelompok etnik itu yang jumlah warganya relatif kecil, mendiami lereng gunung secara terpencar-penca-r dalam hutan-hutan. Mereka rnenggunakan bahasa atau dialek tersendiri dalam kehidupan yang terisolasi itu. Secara umum dapat ditandai keadaan fisik mereka yang berbeda dalam dua golongan. Pada umumnya To-Lare (Orang 'gunung) yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Barat Lembah Palu, disebut juga Tolare-bulumpanau, memiliki warna kulit yang agak cerah. Sebaliknya To-Tare yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Timur Lembah Palu disebut juga To-Lare-Bulungpadake, memillki warna kulit gelap.
Kelompok- Kelompok Sub-etnik Kaili seperti yang disebut pada bahagian depan masing--masing rnemiliki kekhususan baik mengenai ceritera tentang asal usul, maupun dialek serta pernyataan kulturalnya, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :
1.Penduduk asli Lembah Palu. Di Lembah Palu dan sepanjang pantai teluk Palu bermukim To-Kaili, sebagai satu kelompok etnik di kawasan ini 14). Penduduk Lembah Palu, terdiri atas beberapa kelompok sub-etnik atau kelompok kaum, dengan dialekdialek bahasa masing-masing.
Pemukiman awal ke-empat kelompok kaum ini, mehurut petunjuk yang diketemukan sekarang, adalah sebagai berikut:
To-ri Palu, bermukim pada bagian Utara lembah, sepanjang dua sisi muara Sungai Palu.
To-Biromaru dan To-ri Sigi, bermukim di bagian Selatan To-ri Palu, pada sebelah kanan daerah aliran sungai Palu, dengan kekecualian bagian kecil sebelah Utara Wunu, di sana berdiam To-ri Dolo, bermukim di sebelah Selatan To-ri Palu, pada bagian ki-ri daerah aliran Sungai Palu. Di lereng-lereng gunung bagian Utara Lembah Palu juga sudah berdiam sejak dahulu kala penduduk yang disebut To-Lare (Orang gunung). Disamping To-Lare terdapat juga To-Petimpe, yang berdiam di lerenglereng gunung sebelah Utara lembah, terutama dalam wilayah ah Palolo. To-Petimpe secara etnik tidak banyak hubungannya dengan penduduk asli Lembah Palu. Menurut berbagai keterangan To-Petimpe itu, keturunan To-Balinggi dari Tana-Boa di Teluk Tomini, atau mungkin juga dari To-Pebato, satu kaur yang berdiam di muara sungai Puna.
Pada bagian yang agak jauh ke Selatan Lembah Palu, sekitar Gumbasa, Miu, Salcuri pada daerah aliran Sungai Palu, terdapat dua kelompok kaum yaitu To-Pakuli sekitar Gumbasa dan Miu, dan To-Sakuri sekitar Miu. Disana terletak negeri Bangga yang penduduknya berbahasa sama dengan To-Pakuli.
2.To-ri Palu dan To- Biromaru. Penduduk Lembah Palu, berasal dari pegunungan sekitar Lembah Palu itu juga. Ketika bermukim di Lerabah Palu, sejak awalaya-pun, mereka telah berkelompok l:e dalam tiga buah kaum, yaitu : To-ri Sigi, To-ri Dolo dan To--ri Palu.
Berbagai cerita rakyat yang samar-sarna diingat melaiui ceritera atau tutur o-ang tua-tua, bahwa ketiga kaum irri, acapkali saling memerangi antara satu sama lainnya. Karena begitul;ah mereka dalam bermukim di Lernbah Paiu, masing -masing memilih tempat yang secara alamiah terlindung dari upaya serangan-serangan terbuka dari pihak lawarrnya. Malahan ada kecenderungan mempertahanl sosialisasi mereka satu sama lainnya.
To-ri Palu yang rnendiami wilayah Palu, kabarnya berasal dari pegunungan sebelaii Timur. Di Tempat asal mereka, dipegunungan itu, terdapat satu tempat yang bernama Buluwatumpalu, disana bertumbuh banyak tanarnan barnbu yang dipergunakan dalam kehidupan. Untuk mengingat asal nama negeri Buluwaturnpalu yang berarti bambu kecil, maka tempat yang mereka pilih untuk bermukim, yaitu di muara sungai besar yang sekarang bernarna Sungai Palu, disebutnya dari kata itu, yaitu mPalu (kecil). Di mana letak tempat yang disebut Buluwatumpalu itu, diperkirakan di salah satu tempat di atas bukit Paneki sekarang, yang disebut Raranggonau.
Adapun To-Biromaru, diduga keras berasal dari leluhur yang sama dengan To-ri Palu, yang sama-sama menggunakan dialek Kaili-Ledo. Pemelcaran menjadi kaum sendiri itu, terjadi kemudian setelah pemisahan tempat pemukiman.
To-Biromaru mendiarRi tempat yang lebih kedalam di daerah lereng dalam lembah yang subur. Pemisahan menjadi dua kelompok kaum itu terjadi sebelum abad ke-XVII 17).
3.To-ri Sigi, To-ri Dolo.
Menurut catatan Valentijn (1724), To-ri Sigi dan To-ri Dolo diperkirakan sudah bermukim di Lembah Palu sejak ak'nir abad XVII atau pada permulaan abad XVIII. Kedua kelompok kaum ini, menggunakan dialek bahasa Kaili yang sama, yaitu dialek Ija. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berasal da,ri leluhur yang sama. Akan tetapi sejarah kehidupan mereka sejak awal, selalu diwarnai oleh permusuhan dan peperangan antara keduanya.
Dari mana asal kedua kelompok kaum ini pada mulanya sebelum bermuhim di Lembah Palu, terdapat beberapa keterangan. Salah satu cerita yang hampir sarna dengan keterangan Hissink, diterlukan dikalangan penduduk Sigi, sebagai berikut. Sebelum To-ri Sigi bermukini di Lernbah Palu, yaitu di Bora, Watunonju, Oloboju dan Sigi, leluhur merelca berrnukim di sele,lah utara Danau Lindu di lereng-lereng gunung, di terapat-tenlpat pemukiman yang disebut Leu, Silonga, Wowolau, Ue-hialaei dan Sigipulu.
Mengenai To-ri Dolo, menurut beberapa cerita rakyat, dikatakan berasal dari daerah pegunungan yang lebih ke Utara lagi letaknya dalam tempattempat pemukiman yang bernama Dolo, Maru dan Pompewajo. Dimana tempat-tempat itu terletak di lerenglereng gunung sekarang, tidak diperoleh petunjuk yang jelas dari penduduk. Tetapi nama-nama itu, masih ada mengingatnya. Kemungkinan besar, bekasbekas pemukiman To-ri Sigi terletak sekitar negeri Palolo sekarang, tempat-tempat pemukiman awal ToDolo, justru terletak sekitar negeri sekarang.
4.To-Pakuli; To-Pakuli; To-Bangga;To-Baluase; ToSibalaya; To-Sidondo adalah kelompok-lcelompok kaum dalam komunitas yang kecil-kecil. Mereka bermukim di sebelah Selatan wilayah ah pemukiman To-ri Sigi. Mereka menggunakan dialelc bahasa Kaili yang disebut Ado atau Edo. Dialek Ado amat dekat kepada dialek Ija yang dipergunakan oleh To-ri Sigi diperkirakan sebelum mereka bermukim di Lembah Palu, mereka berdiam di lereng-lereng pegunungan sebelah Timur dan Tenggara Lembah Palu.
5.To-Tawaili (To-Yayapi). Dalam iembah sebelah utara Napu hiduplah pada zaman dahulu sekelompok kaum yang menamakan diri To-Tawaeli atau To-Payapi. Karena berbagai gangguan dari kaum di sekitarnya lalu berpindah melewati sebelah Utara Danau Lindu, melintasi nege-ri Sigi dan akhirnya sampai ke Budong-Budong, di sebelah Selatan Donggala di pantai Selat Makassar. Sebagiaii lainnya menetap di Sausu, Dolago dan Parigi.
Pada dewasa ini, To-Tawaeli yang bermukim di wilayah ah Kecamatan Tawaeli yang terletak di sebelah Utara Kota Palu, dalam cerita rakyat yang sudah samar-samar dalam ingatan para penuturnya mengatakan bahwa To-Tawaeli berasal dari bagian Selatan pantai Selat Makassar.
6.To-Lindu, bermukim sekitar Danau Lindu. Mereka percaya dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lembah Palu. Para pemimpin adat Lindu atau keturunan mereka yang ada sekarang, selalu menyatakann diri berasal dari Sigi di Lembah Palu. Keterangan seperti juga dijumpai pada umumnya dalam kalangan penduduk lereng-lereng pegunungan sebelah Selatan di lembah Palu, bahwa nenek moyang mereka berasal dari Sigi.
7.To-Banggakoro. yang mendiami daerah pegunungan jauh di sebelah barat Kulawi dapat dikatakan secara kebudayaan lebih banyak bersentuhan dengan kebudayaan Mamuju di pantai Barat dan kebudayaan Lembah Palu di sebelah Utara. Asal mula penduduk terdahulu To-Banggakoro tak dapat ditemukan dalam ceritacerita rakyat. Akan tetapi besar sekali persamaan kelompok kaum ini (To-Banggakoro) dengan penduduk Bangga yang berasal dari bagian Selatan Lembah Palu.
8.To-Tamungkolowi; To-Tabaku, berdiam di atas pegunungan sebelah Barat negeri Kulawi. Tidak ditemukan legenda ataupun ceritera-ceritera rakyat yang memperkatakan tentang asal usul mereka. Akan tetapi berbagai ungkapan dan benda-benda kebudayaan sub-etnik'ini, seperti sebutan Sou-eo, dan pakaian atau alat-alat perhiasan wanita dan tata rambutnya,sama dengan yang pada umumnya terdapat di Lembah Palu. Dari pengamatan-pengamatan yang lebih dekat dan lama dapat dikatakan bahwa To-Tamungkolowi dan To-Tabaku, juga pada awalnya berasal da-ri bahagian Selatan Lembah Palu.
9.To-Kulawi, yang berdiam di sebelah Selatan Danau Lindu, menurut legenda,mereka berasal dari Bora dan Sigi di Lembah Palu. Menurut ceritera rakyat, bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang bangsawan dari Bora bersarna pengikutnya berburu ke hutan-hutan dan gunung Momi di daerah Kulawi yang masih lengang. Para pemburu berteduh dibawah pohon yang amat rimbun.dan lebat daunnya. Mereka namakan pohon itu, pohon Kulawi.Jenis pohon itu sekarang tidak ditemukan lagi.
10.To-Sausu; To-Balinggi; To-Dolago, diantara Sungai Tambarana dengan Parigi di Pantai Timur SulawesiTengah, terdapatlah negeri-negeri Sausu, Tana -Boa dan Dolago. Disitulah kelompok-kelompok kaum yang menyebutkan diri To-Balinggi dan To-Sausu berdiam. Menurut ceritera rakyat, baik To-Sausu maupun ToBalinggi berasal dari keturunan yang sama yang disebut To-Lopontato yang bermukim di lereng-lereng gunung. Kaum ini amat erat hubungan kebudayaanya dengan To-Parigi. Adapun To-Dolago menurut ceritera rakyat itu, juga adalah dari suatu keturunan dengan kedua kaum lainya, yaitu To-Sausu dan To-Dolago. Tetapi kemudian hidup memisahkan diri karena lingkungan alam, tetapi tetap merasa mempunyai hubungan kekeluargaa<< dengan To-Parigi, juga dengan To-Sigi.
11.To-Parigi. Negeri Parigi terletalc di sebelah Utara Sausu di Teluk Tomini. Pada umtlimnya penduduk negeri Parigi yang disebut To-Parigi percaya bahwa nenek rr,oyang rnereka, berasal dari Lembah Palu. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat Parigi selanjutnya, banyak juga terjadi kontak dengan kelompok etnik Panona dari Wilayah ah Poso, sehingga beberapa pengamat menduga, bahwa orang Parigi dapat digolongkan ke dalam kelompok etnik Pamona-Poso.18).
Dapat diduga ballwa oi-ar,g Kaili yang sekarang me diami Lembah Palu, berasal dari arah Tenggara Utara Barat Daya, yaitu dari daerah sebelah Uta Danau Poso. Ada yang bergerak kearah Baiat dan ke a-r pantai Teluk Tomini, dan ke aril Selatan dan Tim Lembah Palu hingga pantai Seiat Makassar.
BAB III
SEKELUMIT SEJARAH KEBUDAYAAN KAILI
Tempat awal pemukiman sesuatu kaum yang pada hakekatnya terpisah-pisah, malahan terisolasi dari tempat pemukiman kaum lainnya, biasa disebut Ngapa. Da-ri Ngapa itulah dimulai peradaban sesuatu kaum, yang lambat laun berturnbuh jumlah warganya dan memekari:an tempat-tempat pemukiman baru itu. Tempat-tempat pemukiman baru disekitar Ngapa itu, selaku perluasan pemukiman kaum perluasan kaum seasal biasanya disebut Boya atau Soki.
Tempat penukiman lain yang terbentuk oleh adanya lapangan pekerjaan tertentu seperti komunitas (persekutuan) tani atau nelayan dinamakan Kinta. apabila pada suatu waktu perkembangan Ngapa menjadi sudah cukup luasnya ole'n dukungan sejumlah Boya, Kinta dan Soki, maka terbentuklah satu wilayah a territorial dengan susunan kekuasaan yang ditaati- oleh penduduk. Terbentuklah apa yang dinamakan secara umum kerajaan lokal, yang dapat disebut "Kagaukang" atau "Kagau".
Menurut berbagai sumber, 1) sebelum terjadinya struktur kerajaan yang disusun dalam perangkat kekuasaan pejabat-pejabat secara hierarchis, sesuatu wilayah ah pemukiman kaum yaitu Ngapa atau sejenisnya dikuasai atau dipimpin oleh orang yang disebut '1'0Malanggai. Ia adalah pemimpin yang dipandang perkasa, seorang jantan yang mengatasi jantan-jantan lainnya. la-pun dapat disebut "penakluk" atas kaum yang bermukim disekitarnya. Dasar kepemimpinannya adalah keberanian, kepeloporan, untuk mengungguli orang-orang atau kaum yang dipimpinnya.
BAB IV
MODAL PERSONALITY ORANG KAILI
Konsep MODAL PERSONALITY, atau kalau hendak diterjemahkan secara sederhana, dapat disebut PERASAAN KKPKIBADIAN. Penguraian tentang modal-personality, pertama-tama akan menghadapi secara serius persoalan metodologis, untuk penerapannya. Kita akan menghadapi suatu masyarakat dengan segala persoalannya yang amat rumit. Wilayah ah masyarakat itu yang seringkali amat luas, aneka ragam pranata dan lembaga sosial; aneka macam lingkungan alam tisik darn kebudayaan; aneka macam iklim yang dibawa oleh aneka macam keadaan lingkungan, seperti gunung, lembah dan dataran yang membentang luas, semua itu secara metodologis harus diperhitungkan dalam penelitian atau pengamatan yang diperlukan, untuk melukis kan PERASAAN KEPRIBADIAN itu. Oleh karena itu, suatu perkiraan umum yang dipandang representatit atau secara wajar mewakili segenap keadaan yang sesungguhnya amat diperlukan. Tentu saja sangat di perlukan adanya sampling secara statistik dari berbagai daerah kesatuan hidup, atau kelompok sosial, jenis-jenis lapangan pekerjaan, tingkat usaha dan lain-lain, untuk mendapatkan gambaran yang sungguh-sungguh dapat memuaskan, sebagai gambaran umum tentang perasaan kepribadian sesuatu kaum, seperti yang akan dilukiskan disini, yaitu YEKASAAN KEPRIBADIAN ORANG KAILI.
Dalam pengertian umum, tulisan ini hendak mencota melukiskan ciri-ciri kepribadian To-Kaili, melalui perasaan kepribadian yang ditampilkan dalam berbagai tata kelakuan dalam kehidupan yang membudaya atau bernilai budaya. la secara aktual dianut atau dihargai sebagai perilaku sosial dan secara umum dilakukan dalam kehidupan. Deilgan kata lain, apa yang dilakukan atau diperbuat oleh orang Kaili, sehingga ia merasa diri sebagai To-Kaili.
Sesuatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan yang bermakna ke-Kaili-an, karena seseorang (Kaili) yang melakukannya merasa diri orang Kaili, ('To-Kaili). To-Kaili lainnya melihat ia melakukari perbuatan itu, segera mengetahui bahwa ia adalah To-Kaili. Maka antara yang melakukan dengan yang mengamati kelakuan itu tumbuh tali perhubungan yang alafniah sebagai hubungan keakraban (familiar). Karena apa yang diamati itu seolah-olah adalah dirinya sendiri. Ia akrab dengan perilaku atau tingkah laku seperti yang dilakukan dalam kebudayaan Kaili.
Patokan-patokan umum yang dapat dipergunakan dalam menjaring perasaan-perasaan kepribadian itu, adalah biasanya perbuatan-perbuatan atau perilaku yang amat lekat pada kehidupan emosional atau yang menyentuh perasaan-perasaan terdalam, seperti pada perasaan hidup :
1.Kekerabatan dan kenasyarakatan,
2.Keagamaan dan kepercayaan,
3.Bahasa, kesusasteraan dan kesenian pada umumnya.
Pertemuan-pertemuan, berupa pesta-pesta dalam keluaga, membuka kesempatan bagi para remaja untuk saling bertemu dan berkenalan, melalui perkenalan di pesta-pesta itu, terjalinlah hubungan-hubungan yang akan mengantarkan ke(-'Iua remaja yang saling mencintai itu, untuk memasuki tingkat hubunban formal menuju perkawinan/pernikahan.
UPACARA PEMINANGAN : Upacara-upacara pernikahan, lebih banyak memperlihatkan segi-segi formal yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Hal-hal yang formal itu dilakukan untuk saling memberikan kesan tentang adanya kesungguhan kedua belah pihak untuk membangun pertalian keluarga besar.
Rangkaian upacara menjelang hari pernikahan, merupakan formalitas yang kelihatannya amat cermat dijalankan. Orang menamakannya upacara adat, untuk menjaga harmoni dalam kehidupan. Menurut ceritera, adapun NOTATE DALA (upacara manbuka jalan) dilakukan, untuk menjaga agar tidak terjadi penolakan pinangan, atau gadis itu telah ada yang meminangnya lebih dahulu. Kalau terjadi yang demikian, dahulu kala dipandang rnembawa aib bagi keluarga laki-laki.
Dalam upacara peminangan, berbagai benda yang bermakna simbolik diantarkan oleh pihak laki-laki yang diberikan oleh pihak pererrrpuan, antara lain sebagai berikut: SP.MPULOIGI (perbiasan emas perak buat perernpuan). SABALE KAMAGI (buah kalung emas).
Berbagai upacara adat dalam pelaksanaan acara perkawinan seperti tersebut di atas dilakukan dengan sedapat mungkin menampilkan idan titas keluarga yang menjadi penyelenggranya. Upacara itu menunjukkan kedudukan keluarga itu dalan masyarakat, sesuai nilai dan norma yang berlaku. Pada upacara itu ditampilkan ke
PENDAHULUAN
Luas Wilayah Dati I Sulawesi Tengah, 63.689.25 km2 atau 6.368,925 Ha.
Sulawesi Tengah pada umumnya di pengaruhi oleh due musim secara tetap yaitu musim Barat yang keying dan musim Timur yang membawa banyak uap air. Musirn .Barat yang keying itu berlaku dari bulan Oktober sampai dengan April yang di tandai dengan kurangnya turun hujan, sedangkan musim Timur yang banyak membawa uap air, yakni pada bulan April sampai dengan Oktober yang ditandai dengan banyaknya turun hujan. Curah hujan di Sulawesi Tengah setahunnya bervariasi antara 800-3000 mm. Kecuali Lembah Palu yang amat kurang mendapat curah hujan, maka variasinya bergerak antara 400-1000 mm saja setahun.
Penduduk yang baru berjumlah satu setengah juta jiwa yang mendiami wilayah ah propinsi yang amat luas itu, dapat dikatakan tidak mudah dapat dengan cepat mengembangkan diri mengelola potensi alam yang besar itu. Namun demikian, keadaan yang dapat dicapai oleh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kehidupan kebudayaannya sejak berabad yang lalu, dapat di katakan tidak' terlampau terisolasi dari perkembangan unum kebudayaan yang terdapat di daerah lain di kepulauan Nusantara ini. Tentu terdapat berbagai faktor yang turut mengambil bahagian dalam perpbentukan kebudayaan penduduk Sulawesi Tengah seperti yang dijumpai sekarang.
Faktor-faktor tersebut antara lain :
1.Gerak perpindahan (migrasi) penduduk pada masa prasejarah yang masuk secara bertahap ke Sulawesi Tengah.
2.Persebaran agama Islam dan Kristen di kalangan penduduk Sulawesi Tengah .
3.Pengaruh dan peranan pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
Beberapa sarjana dalam laporan penelitian mereka telah mencoba melakukan rekonstruksi asal mula persebaran penduduk, serta pertumbuhan kebudayaan yang mereka miliki. Para penulis masa lampau yang amat terkenal seperti Albert C. Kruijt, N. Adriani dan R. W. Kaudren 1).
Rekonstruksi itu didasarkan pada hasil penelitian dan perbandingan dari benda-benda peninggalan praSejarah, bahasa dan mite, serta lagenda penduduk.yang tersebar diberbagai tempat pemukiman yang luas tersebar di wilayah ah ini. Menurut Albert C. Kruijt, daerah yang didiami penduduk Toraja-Sulawesi Tengah itu pada mulanya, lebih dahulu didiami oleh suatu kelompok penduduk yang belum jelas diketahui indan titasnya. Akan tetapi Kleiweg de Zwaan, masih dapat menemukan sisa-sisa dari penduduk Loinang yang berlokasi di Jazirah Timur Sulawesi Tengah.
Dari sini penduduk pembuat tembikar itu menuju ke arah .Utara, ke Daerah Poso Sulawesi Tengah, terus ke daerah Barat, yakni ke daerah Pegunungan Lore, hingga ke daerah aliran Sungai Koro. Dari sana arahnya, kemudian membelok kembali ke Selatan dan berhenti di suatu tempat yang bernama Waebunta, suatu tempat di daerah Galumpang yang kini termasuk wilayah ah Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan.
Migran Pottenbekkers ini menurut Kruyt ada juga yang datangnya dari arah laut (Selatan Makassar ), memasuki daerah Palu dan menyebar ke Lembah Palu. Penduduk pendatang baru itu, membawa anasir kebudayaan baru ke dalam kehidupan penduduk pribumi Lembah Palu, dalam lapangan sosial ekonomi dan relegi, antara lain sebagai berikut :
1.Dalam lapangan ekonomi diperkenalkan teknik pertanian berpengairan.
2.Dalam lapangan relegi disumbangkan satu sistem yang mengenal struktur dewa-dewa yang bertingkattingkat. Disamping itu juga diperkenalkan upacaraupacara keagarnaan yang rumit.
3.Dalam lapangan kehidupan sosial diperkenalkan jumlah peraturan baru, termasuk innovasi dari suatu lapisan sosial baru, yakni lapisan bangsawan, yang berada di atas lapisan sosial yang telah ada lebih dahulu berlaku dalam masyarakat, yaitu lapisan budak dan merdeka.
Eksistensi lapisan sosial bangsawan, sebagai lapisan baru ini terikat pada mite/legenda Sacaerigading dan Manuru Lasaeo. Unsur-unsur kebudayaan baru yang datang bersama orangorang pendatang baru itu, menurut Kruyt diperkirakan berasal dari unsur-unsur kebudayaan Hindu 'Jawa, yang berasal dari Pulau Jawa. Tentang mite/legenda Sawerigading yang terdapat dalam epos Galigo sebagai tokoh orang Bugis di Sulawesi Selatan, diduga persebarannya sebagai tokoh legendaris di Sulawesi Tengah meliputi daerah yang amat luas dari pantai Barat di Selat Makassar, sampai ke Luwuk Banggai di Teluk Tolo.
Selain terjadi migrasi yang berasal dari luar Sulawesi, sepanjang kehidupan penduduk Sulawesi Tengah, terjadi pula beberapa migrasi lokal. Kaudern membahas mengenai migrasi yang berlangsung di Sulawesi Tengah dalam bukunya menyatakan bahwa perpindahan penduduk di daerah ini terjadi karena berbagai sebab, seperti bencana alam, epidemi penyakit dan adat berperang di antara desa-desa. 2) Perang-perang yang amat sering terjadi itu, bertalian erat dengan adat pen,gayauan mereka. Suasana peperangan itu mengakibatkan penduduk desa acapkali mengungsi lebih jauh ke daerah pedalaman yang sukar dijangkau oleh musuhnya. Sebagai akibat lebih jauh dari adat peperangan ini, timbullah lembaga yang berasal dari tawanan perang, pada beberapa kolompok kaum yang besar di Sulawesi Tengah. Juga punahnya sesuatu kaum tertentu, adalah sebagai, akibat adat peperangan itu, seperti yang diambil oleh kepunahan kelompok kaum To Pajapi.
Pemukiman penduduk sebagian besar terpusat disepanjang pantai (71,21%); tersebar dipedalaman (17,15%), termasuk penduduk yang hidup terpencil dipegunungan, berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa, dan selebihnya di daerah kepulauan, (11,64%).
Menurut biasanya, seperti umumnya yang dikemukakan dalam laporan penelitian mutahir 4) SulawesiTengah itu didiami oleh banyak jenis kelompok Etnik (Suku Bangsa), dan terbesar di empat buah Kabupaten, dalam gambar kasarnya sebagai berikut.
Kelompok Etnik (1). Kaili (2). Tomini, (3). Kulawi, umumnya berdian di Kabupaten Donggala. Kelompok-kelompok Etnik (4). Pamona, (5). Lore, (6). Mori, (7). Bungku, umumnya berdiam di Kabupaten Poso. Kelompok-kelompok Etnik (8). Saluan, (9). Balantak, (10). Banggai,umumnya bermukim di Kabupaten Luwuk Banggai. Kelompok-kelompok Etnik (11). Toli-Toli, dan (12). Buol, umumnya bermukim di Kabupaten Buol ToliToli. Dua belas buah kelompok Etnik inilah yang umumnya menjadi pedoman pembagian kelompok Etnik (suku-bangsa) di Sulawesi Tengah.
Cara pengelompokan Etnik tersebut biasanya menurut pengolompokan "bahasa", atau nama tempat pemukiman", mengikuti apa yang sudah dipublikasikan para penelitian sebelumnya.
Di antara kedua belas kelompok Etnik yang manjadi penduduk (asli) Sulawesi Tengah, maka kelompok Etnik Kaili-lah yang terbesar jumlahnya,yaitu kira-kira 45 % dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tengah.
Kelompok kaum atau etnik yang diidentifikasi k rnenurut bahasa yang dipakainya, biasanya digolongk ke dalam narna rumpun bahasa, seperti orang Mela karena berbahasa Melayu, Orang Bugis karena berbaha Bugis; orang Sunda karena berbahasa Sunda dan sebaga nya. Karena pemakaian bahasa itu amat luas terset oleh penutur yang berbeda beda asal tempat tinggalny maka disebutlah misalnya : Orang Melayu Riau; ora Bugis Rappang; orang Sunda Bogor, dan sebagainya. Juga biasa digunakan simbol atau kata tertentu dal suatu bahasa umum yang luas tempat tinggal penuturn tak dapat dibatasi oleh nama tempat saja, maka dipil simbol atau kata khusus dalam dialek bahasa (serumpu itu seperti digunakan oleh Adriani dan Kruijt men identifikasi kan dialek-dialek dalam kalangan apa ya disebutnya Toraja, dengan menggunakan kata sangka seperti Tae, Rai, Ledo, Da'a dan lain-lain yang semu nya berarti "Tidak". Dengan kaitan itu, dibedakann Toraja Tae dari Toraja Data dan'sebagainya.
Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut ci kebudayaan tertentu, seperti To-Panambe, orang ya bermata pencaharian hidup dengan menggunakan al penangkap ikan yang disebut "Panambe": To-Ri-je'n orang (kaum) yang seluruh kehidupannya terletak air. Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut temp kediamannya seperti To-Palu, To (ri) Palu, ialah ora atau kaum yang bermukim di Palu, atau yang beras dari negeri Palu.
BAB II
TO-KAILI (ORANG KAILI)
Wilayah ah propinsi/Dati I Sulawesi Tengah, seperti yang disebut pada permulaan tulisan ini, terdiri atas empat buah daerah Kabupaten/Dati II, didiami oleh kelompok-kelompok etnik, secara umum, menurut daerahdaerah Kabupaten itu di kelompokkan sebagai berikut:
1.To-Kaili, dengan sejumlah sub-etnik antara lain, To-Palu, To-Sigi, To-Dolo To-Biromaru, To-Kulawi, To-Parigi dan lain-lain.
2.To-Pamona dengan sejumlah sub-etnik seperti ToMori, To-Bungku dan lain-lain.
3.To-Banggai dengan sekelompok sub etnik yang berdekatan seperti To-Saluan, To-Balantak dan lain-lain.
4. To-Buol Toli-Toli, dengan sejumlah kelompok kaum yang kecil-kecil.
Diantara kelompok -Kelompok etnik itu yang akat menjadi pokok bahasan tulisan ini ialah kelompok etnil To-Kaili. Kelompok etnik To-Kaili inilah yang terbesai jumlahnya, dan persebarannya dalam seluruh wilayah al propinsi yang amat luas. To-Kaili pada dewasa inmenempati jumlah terbesar yang mendiami daerah kabupaten/ Dati II Donggala, dan sebahagian lainnya bermukir di beberapa wilayah ah kecamatan dalam daerah kabupatei lainnya. Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai ToKai, karena adanya persamaan dalam bahasa dan ada; istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumbei asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua. Fra dalam kalangan semua To-Kaili, digunakan secara umum, Disamping itu terdapat banyak dialek bahasa Kaili van,, juga menjadi identifikasi (sering kali tajam) dari. sut kultur atau sub etnik To-Kaili yang berdiam pada wilayah ah-wilayah ah yang sering kali masih amat terisolasi.
1.To-Palu (To-ri-Palu)
2.To-Biromaru
3.To-Dolo (To-ri-Dolo)
4.To-Sigi (To-ri-Sigi)
5.To-Pakuli, To-Banggai, To-Baluase,To-Sibalaya, To Sidondo
6.To-Lindu
7.To-Banggakoro
8.To-Tamunglcolowi dan To-Baku.
9. To-Kulawi
10.To-Tawaeli (to-payapi)
11..To-Susu, To-Balinggi, To-Dolago
12.To-Petimbe
13.T0-Rarang gonau
14.To-Parigii
Dalam kalangan sub etnik tersebut acap kali terjadi penggolongan yang lebih kecil lagi, dengan ciriciri kliusus, yang kelihatnnya lebih dekat kepada kelompok kekerabatan, yang menunjukkan sifat satuan geneologisnya.
Untuk menemukan pengikat solidaritas dalam kelompok etnik To-Kaili, dicoba diternulcan segala sesuatu yang berbau mitologi, atau cerita-cerita tokoh legendaris atau cerita-cerita rakyat (folk-tale) dalam kalangan To-Kaili dan sub etnik yang terhisap di dalamnya.
To-Kaili yang mendiami Lembah Palu memilki cerita rakyat (folk-tale) yang menjadi pengikat rasa kesatuan To-Kaili tentang asal-usul mereka 4). Tana Kaili yang te-rletak di Lembah Palu (sekarang), menurut ceritera rakyat itu, pada •zaman dahulu kala Lembah Palu ini, masih lautan, di sebut Laut Kai1i atau Teluk Kaili. Nenek moyang To-Kaili pada zainan dahulu itu mendiami lereng-lereng gunung sekeliling Laut Kaili. Konon, di sebelah Timur Laut Kaili itu, terdapat sebatang pohon besar, turnbuh kokoh, tegak dengan kemegahan menjulang tinggi, sebagai tanda pengenal daratan bagi pelaut yang memasuki teluk Kaili. Pohon itu dinamakan Pohon Kaili. Pohon itu tumbuh dipantai dan terletak antara negeri Kalinjo dengan negeri Sigipulu.
Pada suatu hari Laut Kaili mendapat kunjungan sebuah perahu layar yang amat besar, dibawah pimpinan seorang pelaut luar negeri yang namanya sudah arnat tersohor dikawasan ini. Pelaut itu bernama SAGJExIGADING 5). Dikatakan Sawerigading itu, singgah di Teluk Kaili dalam perjalannya kembali dari Tana Cina, menemui dan mengawini tunangannya yang bernama We Cudai. Tempat yang disinggahi pertama oleh perahu Sawerigading, ialah negeri Ganti, ibu negeri Kerajaan Banawa (sekarang Donggala). Antara raja Banawa dengan Sawerigading terjalinlah tali persahabatan yang dilcolcohkan dengan perjanjian ikatan persatuan dQngan kerajan Bugis-Bone, di Sulawesi-Selatan 6). Dalam menyusuri teluk lebih dalam ke arah Selatam sampailah Sawerigading dengan perahunya ke pantai negeri Sigipulu, dalam wilayah ah kerajaan Sigi. Perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan Uwe Mebere, yang sekarang berna~-na Ranoromba. Kerajaan Sigi dipimpin oleh seorang Raja Wanita yang bernama Ngginayo atau Ngili Nayo 7). Raja perempuan ini, belum kawin dan berparas amat cantik. Setibanya di Sigi Sawerigading bertemu langsung dengan raja Ngilinayo yang amat cantik itu. Pada pandengan pertama Sawerigading jatuh cinta. lapun mengajukan pinangan untuk menjadikannya pei-maisuri. Raja Ngilinayo bersedia rnenerirna pinangan Sawerigading dengan syarat ayarn aduannya yang bergelar Calabai 3). dapat dikalahkan oleh ayam aduan Sawerigading yang bergelar Bakka Cimpolon,g (Bg), yaitu ayam berbulu kelabu ke hijauan, dan kepalanya berjambul. Syarat itupun disetujui oleh Sawerigading, dan disepakati, upacara adu ayam itu akan dilangsungkan sekembal Sawerigading dari perjalanan ke pantai Barat, sambi di persi.apkan arena (Wala-wala) adu ayam.
Di pantai Barat perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan negeri Bangga 9). Raja Bangga seorang pe rempuan bernama Wumbulangi di gelar Magau Bangga, yan diceritralcan sebagai To-Manuru 10) Sawerigadingpu menemui baginda dan mengikat perjanjian persahabatan dalam daftar silsilah raja-raja Bangga, Wumbulang adalah Ma~au pertama kerajaan Bangga.
Setibanya di Sigi, Arena untuk penyabungan ayan di atas sebuah gelanggang (wala-wala) sudah dipersiapkan. Ayarn sabungan Sawerigading Bakka Cimpolonp yang akan bertarung melawan Calabai ayam Ngilinayo, semuanya siap di pertarunglean. Pada malam harinya telah diumumkan kepada segenap Iapisan masyarakat, tentank pertarungan yang akan berlangsung ke-esokan paginya. Akan tetapi sesuat.u yang luar biasa telah terjadi pada malarn sebelum pertarungan itu berlangsung, yang menjadi sabab dibatalkannya pertarungan itu.
Anjing Sawerigading yang digelar La-Bolong (SiHitam) turun dari perahu, berjalan jalan di darat Sigi. La-Bolong berjalan ke arah Selatan. Tanpa disadarinya, ia terperangkap kedalam satu Iobang besar, ternpat kediaman seekor belut (Lindu), yang amat besar. Karena merasa terganggu oleh kedatangan anjing labolong yang tiba-tiba itu, maka belut/lindu itupun menjadi marah, dan menyerang La Bolong, maka terjadilah pertarungan yang amat sengit antara keduanya. Pertarungan itu demikian dahsyatnya, sehingga seolah-olah terjadi gempa yang menggetarkan bumi. Penduduk pun menjadi, ketakutan. La-Bolong berhasil menyergap belut/lindu itu, keluar lobangnya. Lobang besar bekas tempat tinggal belut/lindu itu, setelah kosong dan runtuh, lalu menjadi danau, yang hinga kini disebut Danau Lindu.
Anjing Sawerigading La-Bolong melarikan belut itu kearah Utara dalam keadaan meronta-ronta, dan menjadikan lubang berupa saluran yang dialiri oleh air laut yang deras, air yang mengalir dengan deras itu, bagaikan air bah yang tumpah, menyebabkan keringnya air Kaili. Maka terbentuklah Lembah Palu dan terjelmalah Tana--Kaili.
Peristiwa alam yang amat dahsyat ini, membatalkan pertarungan kedua ayam yang telah dipersiapkan dengan cerrnat. Raja Ngilinayo dan Sawerigading sama-sama berikrar untuk hidup sebagai saudara kandung yang saling menghormati i untuk bekerja sama membimbing orang Kaili yang mendiarni Lembah Palu, bekas Teluk Kaili, yang telah menjadi daratan.
Air yang mengalir deras ke laut lepas Selat Makassar menghanyutkan perahu Sawerigading, yang akhirnya terdampar di Sombe. Ceritera rakyat rnenyebut, bahwa gunung yang menyerupai perahu di Sombe itu, adalah bekas perahu Sawerigading yang sekarang di Bulusakaya, yang berarti gunung yang berbentuk perahu. Alat-alat perlengkapan perahu lainnya, antara lain layar, terdampar di pantai sebelah Timur. Tempat itu kini bernama Bulumasomba, artinya gunung yang menyerupai layar.
Sebuah versi lain, mengenai ceritera persaudaraan antara Raja Ngilinayo dengan Sawerigading, menyebutkan bahwa pada menjelang akan diadakannya pertarungan ayam, di adakanlah pesta atau keramaian yang dikunjungi oleh sebahagian besar penduduk kerajaan Sigi. Ferangkat alat kesenian, bunyi-bunyian berupa gong, tambur dan seruling, didaratkan dari perahu Sawerigading, untuk meramaikan pesta kerajaan itu. Gong, tambur, dan genderang dipalu bertalu-talu, memeriahkan pesta itu, mengundang kera:iaian yang gegap gempita. Urang sakitpun yang tadinya terbaring lemah di pembaringan masing-masing, setelah mendan gar bunyi-bunyian itu. Merekapun menghadiri pesta keramaian itu. Penyembuhan dari penyakit, berkat mendan garkan bunyi-bunyian yang mengiringi nyanyian (t'embang), yang diperagakan dengan tari-tarian, dipercaya sebagai obat mujarab. Pengobatan dengan cara itu, disebut Balia, dari dua kata bali + ia artinya lawan ia. Maksudnya setan atau roh jahat yang membawa penyakit harus dilawan.
Puncak acara keramaian malarn itu, ialah peresmian atau pengukuhan sumpah setia persaudaraan antara raja Sigi Ngilinayo dengan Sawerigading. Segenap perangkat alat bunyi-bunyian, diserahkan oleh Sawerigading kepada saudaranya, yaitu Raja Sigi Ngilinayo. Seusai pesta Kerajaan itu, kembalilah Sawerigading dengan anak buahnya ke perahu. Setelah mereka tiba di perahu, mereka dikejutkan oleh adanya getaran bumi yang dahsyat disertai deru air yang bagaikan tautan keras. Dikatan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kareria pergelutan antara Labolong dengan belut/lindu, seperti diceriterakan didepari. Perahu Sawerigadirlg terlepas dari tambatannya, dan hanyut mengikuti arus air ke laut.lepas, Selat Makassar. Berkat lcetangkasar: awak perahu Sawerigading, menyelematkan perahun,da dari malapetaka. Mereka melepaskan diri dari Teluk Kaili yang sudah menjadi daratan, dan selamatlah Saweriading meneruskan perjalanannya kembali ke Tana-Bone Sulawesi-Selatan).
Sawerigading adalah tokoh legendaris dalam ceritera rakyat Tana Kaili. Tokoh itu dihubungkan dengan kedudukan Kerajaan Bone, sebagai kerajaan Bugis di Sulawesi-Selatan yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kai1i. Dapat diperkirakan bahwa hubungan-hubungan yang akrab dengan kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kaili, berlangsung dalam abad ke-17. Adapun tokoh lagendaris Sawerigading di Sulawesi Selatan tersebut dalaiu Epos La-Galigo, dipandang sebagai peletak dasar dan cikal bakal raja-raja Bugis, khususnya di Kerajaan Lucau, yang terletalc pada bahagiaii Utara Selat Bone. Zaman Sawerigading dalam Epos La-Galigo, diperkirakan berlaiigsung dalam abad IX dan X (M). Kedua keadaan itu dalam cerita rakyat Tana Kaili, yaitu tokoh iegendaris Sawerigading dan hubungan persahabatan dengan kerajaan Bone, dipadukan saja sebagai pe-ristiwa istimewa dalam suatu cerita rakyat. Hal seperti itu, adalah biasa dan menjadi karastrestik umum dari suatu cerita rakyat (Folk-Tale), untuk memperoleh semacam pengukuhan legitimasi bagi tokoh-tokoh yang tersangkut dalam peristiwa luar biasa 12). Mungkin sekalli dapat dibuktikan kebenaran ilmi.aluiya, melalui penelitian (arkeologi atau paleoantropologi), bahwa sekitar abad IX-X (M), Lembah Palu masih merupakan lautam sampai negeri Gangga dekat Danau Lindu. Setelah Laut Kaili menjadi daratan, yang membentuk Tana-Kai di Lembah Palu, maka terjadilah hubungan dangan kerajaan Bone dan Gowa yang menguasai perairan Selat Makassar. Ketika itu Kompeni Belanda (VOC) juga sudah mulai melakukan kegiatan intervensi terhadap kerajaan kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Peristiwa-peristiwa penting itu justeru terjadi dalam abad ke XVII. Sekitar abad itu , kerajaan Bone mengunggu kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan di baw pimpinan Aruppalakka, To-Erung malamppee' Gemme' n Ketika itu Kerajaan Bone melakukan hubungan baik m lalui daratan, maupun lautan ke bahagian Timur d Barat Nusantara, termasuk Sulawesi Tengah dan Utar Tana Kaili dan kerajaan Banawa amat banyak di sebabkan dalam Lontara Bugis-Makassar tentang hubungannya , politik dan persaudaraannya dengan negeri-negeri Bugis yang menguasai pelayaran Selat Makassar.
Pada dewasa ini, persebaran pemukiman To-Kaili propinsi Sulawesi Tengah, meliputi sebahagian terbes Kabupaten/Dati II Donggala, dan beberapa wilayah Kecamatan dalam Kabupaten/ Dati II Poso, Banggai d Buol Toli-Toli. Kelompok etnik Tiriombo, Tomini d Moutong yang mendiami pesisir sebelah Timur di Tel Tomini, tadinya masih dapat dipertajam identifikasinya yang berbeda dari kelompok etnik To-Kaili. Teta kini, dilihat dari perkembangan persebaran penerima unsur-unsur kebudayaan yang sama,: maka perbedaa perbedan itu menjadi sangat tipis. Malahan percampur rnelalui jalan kawin-mawin yang amat banyak, teruta dalam kalangan pemuka adat dan masyarakat Kaili dan g To-Tinombo, To-Tomini dan To-Moutong, perbedaan yang pernah mempertajam identifikasi etnik masing-masi kini sudah mencair.
Cacah jiwa orang Kaili yang tersebar luas dal Propinsi Sulawesi Tengah, diperkirakan 45 % dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah, yaitu kira-kira 4 sampai 5 ratus ribu jiwa. To-Kaili pada umumnya atau terbanyak bermukim di sepanjang pantai, baik di pesisir Barat, maupun dipesisir Timur. Oleh karena itu, maka cara hidup clan kebudayaan Kaili yang dominan, kelihatan lebih dekat kesamaannya kepada kebudayaan Bugis-Makassar (Sulawesi-Selatan), dan kebudayaan Melayu (Sumatera dan Malaka ).
Selain dari pada kelompok etnik Kaili, Pamona, Buol Toli-Toli, Banggai dan lain-lain, seperti telah disebut pada bahagiarr depan, masih terdapat lagi keiompok-kelompok etnik dalam jumlah warganya yang tidak , terlalu banyak, tetapi mereka dipandang' sebagai penduduk asli Sulawesi Tengah. Mereka itu kini disebut suku-suku terasirlg, seperti : Lauje, Tajio, Pendau, To-Lare,. Rarang Gonau, Loon , Sea-sea, Daya dan mungkin masih ada lagi lainnya yang belum di kenal. Kelompok-kelompok etnik itu yang jumlah warganya relatif kecil, mendiami lereng gunung secara terpencar-penca-r dalam hutan-hutan. Mereka rnenggunakan bahasa atau dialek tersendiri dalam kehidupan yang terisolasi itu. Secara umum dapat ditandai keadaan fisik mereka yang berbeda dalam dua golongan. Pada umumnya To-Lare (Orang 'gunung) yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Barat Lembah Palu, disebut juga Tolare-bulumpanau, memiliki warna kulit yang agak cerah. Sebaliknya To-Tare yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Timur Lembah Palu disebut juga To-Lare-Bulungpadake, memillki warna kulit gelap.
Kelompok- Kelompok Sub-etnik Kaili seperti yang disebut pada bahagian depan masing--masing rnemiliki kekhususan baik mengenai ceritera tentang asal usul, maupun dialek serta pernyataan kulturalnya, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :
1.Penduduk asli Lembah Palu. Di Lembah Palu dan sepanjang pantai teluk Palu bermukim To-Kaili, sebagai satu kelompok etnik di kawasan ini 14). Penduduk Lembah Palu, terdiri atas beberapa kelompok sub-etnik atau kelompok kaum, dengan dialekdialek bahasa masing-masing.
Pemukiman awal ke-empat kelompok kaum ini, mehurut petunjuk yang diketemukan sekarang, adalah sebagai berikut:
To-ri Palu, bermukim pada bagian Utara lembah, sepanjang dua sisi muara Sungai Palu.
To-Biromaru dan To-ri Sigi, bermukim di bagian Selatan To-ri Palu, pada sebelah kanan daerah aliran sungai Palu, dengan kekecualian bagian kecil sebelah Utara Wunu, di sana berdiam To-ri Dolo, bermukim di sebelah Selatan To-ri Palu, pada bagian ki-ri daerah aliran Sungai Palu. Di lereng-lereng gunung bagian Utara Lembah Palu juga sudah berdiam sejak dahulu kala penduduk yang disebut To-Lare (Orang gunung). Disamping To-Lare terdapat juga To-Petimpe, yang berdiam di lerenglereng gunung sebelah Utara lembah, terutama dalam wilayah ah Palolo. To-Petimpe secara etnik tidak banyak hubungannya dengan penduduk asli Lembah Palu. Menurut berbagai keterangan To-Petimpe itu, keturunan To-Balinggi dari Tana-Boa di Teluk Tomini, atau mungkin juga dari To-Pebato, satu kaur yang berdiam di muara sungai Puna.
Pada bagian yang agak jauh ke Selatan Lembah Palu, sekitar Gumbasa, Miu, Salcuri pada daerah aliran Sungai Palu, terdapat dua kelompok kaum yaitu To-Pakuli sekitar Gumbasa dan Miu, dan To-Sakuri sekitar Miu. Disana terletak negeri Bangga yang penduduknya berbahasa sama dengan To-Pakuli.
2.To-ri Palu dan To- Biromaru. Penduduk Lembah Palu, berasal dari pegunungan sekitar Lembah Palu itu juga. Ketika bermukim di Lerabah Palu, sejak awalaya-pun, mereka telah berkelompok l:e dalam tiga buah kaum, yaitu : To-ri Sigi, To-ri Dolo dan To--ri Palu.
Berbagai cerita rakyat yang samar-sarna diingat melaiui ceritera atau tutur o-ang tua-tua, bahwa ketiga kaum irri, acapkali saling memerangi antara satu sama lainnya. Karena begitul;ah mereka dalam bermukim di Lernbah Paiu, masing -masing memilih tempat yang secara alamiah terlindung dari upaya serangan-serangan terbuka dari pihak lawarrnya. Malahan ada kecenderungan mempertahanl sosialisasi mereka satu sama lainnya.
To-ri Palu yang rnendiami wilayah Palu, kabarnya berasal dari pegunungan sebelaii Timur. Di Tempat asal mereka, dipegunungan itu, terdapat satu tempat yang bernama Buluwatumpalu, disana bertumbuh banyak tanarnan barnbu yang dipergunakan dalam kehidupan. Untuk mengingat asal nama negeri Buluwaturnpalu yang berarti bambu kecil, maka tempat yang mereka pilih untuk bermukim, yaitu di muara sungai besar yang sekarang bernarna Sungai Palu, disebutnya dari kata itu, yaitu mPalu (kecil). Di mana letak tempat yang disebut Buluwatumpalu itu, diperkirakan di salah satu tempat di atas bukit Paneki sekarang, yang disebut Raranggonau.
Adapun To-Biromaru, diduga keras berasal dari leluhur yang sama dengan To-ri Palu, yang sama-sama menggunakan dialek Kaili-Ledo. Pemelcaran menjadi kaum sendiri itu, terjadi kemudian setelah pemisahan tempat pemukiman.
To-Biromaru mendiarRi tempat yang lebih kedalam di daerah lereng dalam lembah yang subur. Pemisahan menjadi dua kelompok kaum itu terjadi sebelum abad ke-XVII 17).
3.To-ri Sigi, To-ri Dolo.
Menurut catatan Valentijn (1724), To-ri Sigi dan To-ri Dolo diperkirakan sudah bermukim di Lembah Palu sejak ak'nir abad XVII atau pada permulaan abad XVIII. Kedua kelompok kaum ini, menggunakan dialek bahasa Kaili yang sama, yaitu dialek Ija. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berasal da,ri leluhur yang sama. Akan tetapi sejarah kehidupan mereka sejak awal, selalu diwarnai oleh permusuhan dan peperangan antara keduanya.
Dari mana asal kedua kelompok kaum ini pada mulanya sebelum bermuhim di Lembah Palu, terdapat beberapa keterangan. Salah satu cerita yang hampir sarna dengan keterangan Hissink, diterlukan dikalangan penduduk Sigi, sebagai berikut. Sebelum To-ri Sigi bermukini di Lernbah Palu, yaitu di Bora, Watunonju, Oloboju dan Sigi, leluhur merelca berrnukim di sele,lah utara Danau Lindu di lereng-lereng gunung, di terapat-tenlpat pemukiman yang disebut Leu, Silonga, Wowolau, Ue-hialaei dan Sigipulu.
Mengenai To-ri Dolo, menurut beberapa cerita rakyat, dikatakan berasal dari daerah pegunungan yang lebih ke Utara lagi letaknya dalam tempattempat pemukiman yang bernama Dolo, Maru dan Pompewajo. Dimana tempat-tempat itu terletak di lerenglereng gunung sekarang, tidak diperoleh petunjuk yang jelas dari penduduk. Tetapi nama-nama itu, masih ada mengingatnya. Kemungkinan besar, bekasbekas pemukiman To-ri Sigi terletak sekitar negeri Palolo sekarang, tempat-tempat pemukiman awal ToDolo, justru terletak sekitar negeri sekarang.
4.To-Pakuli; To-Pakuli; To-Bangga;To-Baluase; ToSibalaya; To-Sidondo adalah kelompok-lcelompok kaum dalam komunitas yang kecil-kecil. Mereka bermukim di sebelah Selatan wilayah ah pemukiman To-ri Sigi. Mereka menggunakan dialelc bahasa Kaili yang disebut Ado atau Edo. Dialek Ado amat dekat kepada dialek Ija yang dipergunakan oleh To-ri Sigi diperkirakan sebelum mereka bermukim di Lembah Palu, mereka berdiam di lereng-lereng pegunungan sebelah Timur dan Tenggara Lembah Palu.
5.To-Tawaili (To-Yayapi). Dalam iembah sebelah utara Napu hiduplah pada zaman dahulu sekelompok kaum yang menamakan diri To-Tawaeli atau To-Payapi. Karena berbagai gangguan dari kaum di sekitarnya lalu berpindah melewati sebelah Utara Danau Lindu, melintasi nege-ri Sigi dan akhirnya sampai ke Budong-Budong, di sebelah Selatan Donggala di pantai Selat Makassar. Sebagiaii lainnya menetap di Sausu, Dolago dan Parigi.
Pada dewasa ini, To-Tawaeli yang bermukim di wilayah ah Kecamatan Tawaeli yang terletak di sebelah Utara Kota Palu, dalam cerita rakyat yang sudah samar-samar dalam ingatan para penuturnya mengatakan bahwa To-Tawaeli berasal dari bagian Selatan pantai Selat Makassar.
6.To-Lindu, bermukim sekitar Danau Lindu. Mereka percaya dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lembah Palu. Para pemimpin adat Lindu atau keturunan mereka yang ada sekarang, selalu menyatakann diri berasal dari Sigi di Lembah Palu. Keterangan seperti juga dijumpai pada umumnya dalam kalangan penduduk lereng-lereng pegunungan sebelah Selatan di lembah Palu, bahwa nenek moyang mereka berasal dari Sigi.
7.To-Banggakoro. yang mendiami daerah pegunungan jauh di sebelah barat Kulawi dapat dikatakan secara kebudayaan lebih banyak bersentuhan dengan kebudayaan Mamuju di pantai Barat dan kebudayaan Lembah Palu di sebelah Utara. Asal mula penduduk terdahulu To-Banggakoro tak dapat ditemukan dalam ceritacerita rakyat. Akan tetapi besar sekali persamaan kelompok kaum ini (To-Banggakoro) dengan penduduk Bangga yang berasal dari bagian Selatan Lembah Palu.
8.To-Tamungkolowi; To-Tabaku, berdiam di atas pegunungan sebelah Barat negeri Kulawi. Tidak ditemukan legenda ataupun ceritera-ceritera rakyat yang memperkatakan tentang asal usul mereka. Akan tetapi berbagai ungkapan dan benda-benda kebudayaan sub-etnik'ini, seperti sebutan Sou-eo, dan pakaian atau alat-alat perhiasan wanita dan tata rambutnya,sama dengan yang pada umumnya terdapat di Lembah Palu. Dari pengamatan-pengamatan yang lebih dekat dan lama dapat dikatakan bahwa To-Tamungkolowi dan To-Tabaku, juga pada awalnya berasal da-ri bahagian Selatan Lembah Palu.
9.To-Kulawi, yang berdiam di sebelah Selatan Danau Lindu, menurut legenda,mereka berasal dari Bora dan Sigi di Lembah Palu. Menurut ceritera rakyat, bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang bangsawan dari Bora bersarna pengikutnya berburu ke hutan-hutan dan gunung Momi di daerah Kulawi yang masih lengang. Para pemburu berteduh dibawah pohon yang amat rimbun.dan lebat daunnya. Mereka namakan pohon itu, pohon Kulawi.Jenis pohon itu sekarang tidak ditemukan lagi.
10.To-Sausu; To-Balinggi; To-Dolago, diantara Sungai Tambarana dengan Parigi di Pantai Timur SulawesiTengah, terdapatlah negeri-negeri Sausu, Tana -Boa dan Dolago. Disitulah kelompok-kelompok kaum yang menyebutkan diri To-Balinggi dan To-Sausu berdiam. Menurut ceritera rakyat, baik To-Sausu maupun ToBalinggi berasal dari keturunan yang sama yang disebut To-Lopontato yang bermukim di lereng-lereng gunung. Kaum ini amat erat hubungan kebudayaanya dengan To-Parigi. Adapun To-Dolago menurut ceritera rakyat itu, juga adalah dari suatu keturunan dengan kedua kaum lainya, yaitu To-Sausu dan To-Dolago. Tetapi kemudian hidup memisahkan diri karena lingkungan alam, tetapi tetap merasa mempunyai hubungan kekeluargaa<< dengan To-Parigi, juga dengan To-Sigi.
11.To-Parigi. Negeri Parigi terletalc di sebelah Utara Sausu di Teluk Tomini. Pada umtlimnya penduduk negeri Parigi yang disebut To-Parigi percaya bahwa nenek rr,oyang rnereka, berasal dari Lembah Palu. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat Parigi selanjutnya, banyak juga terjadi kontak dengan kelompok etnik Panona dari Wilayah ah Poso, sehingga beberapa pengamat menduga, bahwa orang Parigi dapat digolongkan ke dalam kelompok etnik Pamona-Poso.18).
Dapat diduga ballwa oi-ar,g Kaili yang sekarang me diami Lembah Palu, berasal dari arah Tenggara Utara Barat Daya, yaitu dari daerah sebelah Uta Danau Poso. Ada yang bergerak kearah Baiat dan ke a-r pantai Teluk Tomini, dan ke aril Selatan dan Tim Lembah Palu hingga pantai Seiat Makassar.
BAB III
SEKELUMIT SEJARAH KEBUDAYAAN KAILI
Tempat awal pemukiman sesuatu kaum yang pada hakekatnya terpisah-pisah, malahan terisolasi dari tempat pemukiman kaum lainnya, biasa disebut Ngapa. Da-ri Ngapa itulah dimulai peradaban sesuatu kaum, yang lambat laun berturnbuh jumlah warganya dan memekari:an tempat-tempat pemukiman baru itu. Tempat-tempat pemukiman baru disekitar Ngapa itu, selaku perluasan pemukiman kaum perluasan kaum seasal biasanya disebut Boya atau Soki.
Tempat penukiman lain yang terbentuk oleh adanya lapangan pekerjaan tertentu seperti komunitas (persekutuan) tani atau nelayan dinamakan Kinta. apabila pada suatu waktu perkembangan Ngapa menjadi sudah cukup luasnya ole'n dukungan sejumlah Boya, Kinta dan Soki, maka terbentuklah satu wilayah a territorial dengan susunan kekuasaan yang ditaati- oleh penduduk. Terbentuklah apa yang dinamakan secara umum kerajaan lokal, yang dapat disebut "Kagaukang" atau "Kagau".
Menurut berbagai sumber, 1) sebelum terjadinya struktur kerajaan yang disusun dalam perangkat kekuasaan pejabat-pejabat secara hierarchis, sesuatu wilayah ah pemukiman kaum yaitu Ngapa atau sejenisnya dikuasai atau dipimpin oleh orang yang disebut '1'0Malanggai. Ia adalah pemimpin yang dipandang perkasa, seorang jantan yang mengatasi jantan-jantan lainnya. la-pun dapat disebut "penakluk" atas kaum yang bermukim disekitarnya. Dasar kepemimpinannya adalah keberanian, kepeloporan, untuk mengungguli orang-orang atau kaum yang dipimpinnya.
BAB IV
MODAL PERSONALITY ORANG KAILI
Konsep MODAL PERSONALITY, atau kalau hendak diterjemahkan secara sederhana, dapat disebut PERASAAN KKPKIBADIAN. Penguraian tentang modal-personality, pertama-tama akan menghadapi secara serius persoalan metodologis, untuk penerapannya. Kita akan menghadapi suatu masyarakat dengan segala persoalannya yang amat rumit. Wilayah ah masyarakat itu yang seringkali amat luas, aneka ragam pranata dan lembaga sosial; aneka macam lingkungan alam tisik darn kebudayaan; aneka macam iklim yang dibawa oleh aneka macam keadaan lingkungan, seperti gunung, lembah dan dataran yang membentang luas, semua itu secara metodologis harus diperhitungkan dalam penelitian atau pengamatan yang diperlukan, untuk melukis kan PERASAAN KEPRIBADIAN itu. Oleh karena itu, suatu perkiraan umum yang dipandang representatit atau secara wajar mewakili segenap keadaan yang sesungguhnya amat diperlukan. Tentu saja sangat di perlukan adanya sampling secara statistik dari berbagai daerah kesatuan hidup, atau kelompok sosial, jenis-jenis lapangan pekerjaan, tingkat usaha dan lain-lain, untuk mendapatkan gambaran yang sungguh-sungguh dapat memuaskan, sebagai gambaran umum tentang perasaan kepribadian sesuatu kaum, seperti yang akan dilukiskan disini, yaitu YEKASAAN KEPRIBADIAN ORANG KAILI.
Dalam pengertian umum, tulisan ini hendak mencota melukiskan ciri-ciri kepribadian To-Kaili, melalui perasaan kepribadian yang ditampilkan dalam berbagai tata kelakuan dalam kehidupan yang membudaya atau bernilai budaya. la secara aktual dianut atau dihargai sebagai perilaku sosial dan secara umum dilakukan dalam kehidupan. Deilgan kata lain, apa yang dilakukan atau diperbuat oleh orang Kaili, sehingga ia merasa diri sebagai To-Kaili.
Sesuatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan yang bermakna ke-Kaili-an, karena seseorang (Kaili) yang melakukannya merasa diri orang Kaili, ('To-Kaili). To-Kaili lainnya melihat ia melakukari perbuatan itu, segera mengetahui bahwa ia adalah To-Kaili. Maka antara yang melakukan dengan yang mengamati kelakuan itu tumbuh tali perhubungan yang alafniah sebagai hubungan keakraban (familiar). Karena apa yang diamati itu seolah-olah adalah dirinya sendiri. Ia akrab dengan perilaku atau tingkah laku seperti yang dilakukan dalam kebudayaan Kaili.
Patokan-patokan umum yang dapat dipergunakan dalam menjaring perasaan-perasaan kepribadian itu, adalah biasanya perbuatan-perbuatan atau perilaku yang amat lekat pada kehidupan emosional atau yang menyentuh perasaan-perasaan terdalam, seperti pada perasaan hidup :
1.Kekerabatan dan kenasyarakatan,
2.Keagamaan dan kepercayaan,
3.Bahasa, kesusasteraan dan kesenian pada umumnya.
Pertemuan-pertemuan, berupa pesta-pesta dalam keluaga, membuka kesempatan bagi para remaja untuk saling bertemu dan berkenalan, melalui perkenalan di pesta-pesta itu, terjalinlah hubungan-hubungan yang akan mengantarkan ke(-'Iua remaja yang saling mencintai itu, untuk memasuki tingkat hubunban formal menuju perkawinan/pernikahan.
UPACARA PEMINANGAN : Upacara-upacara pernikahan, lebih banyak memperlihatkan segi-segi formal yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Hal-hal yang formal itu dilakukan untuk saling memberikan kesan tentang adanya kesungguhan kedua belah pihak untuk membangun pertalian keluarga besar.
Rangkaian upacara menjelang hari pernikahan, merupakan formalitas yang kelihatannya amat cermat dijalankan. Orang menamakannya upacara adat, untuk menjaga harmoni dalam kehidupan. Menurut ceritera, adapun NOTATE DALA (upacara manbuka jalan) dilakukan, untuk menjaga agar tidak terjadi penolakan pinangan, atau gadis itu telah ada yang meminangnya lebih dahulu. Kalau terjadi yang demikian, dahulu kala dipandang rnembawa aib bagi keluarga laki-laki.
Dalam upacara peminangan, berbagai benda yang bermakna simbolik diantarkan oleh pihak laki-laki yang diberikan oleh pihak pererrrpuan, antara lain sebagai berikut: SP.MPULOIGI (perbiasan emas perak buat perernpuan). SABALE KAMAGI (buah kalung emas).
Berbagai upacara adat dalam pelaksanaan acara perkawinan seperti tersebut di atas dilakukan dengan sedapat mungkin menampilkan idan titas keluarga yang menjadi penyelenggranya. Upacara itu menunjukkan kedudukan keluarga itu dalan masyarakat, sesuai nilai dan norma yang berlaku. Pada upacara itu ditampilkan ke
Yaku tokaili nisanimu tesana mangge?
BAB I
PENDAHULUAN
Luas Wilayah Dati I Sulawesi Tengah, 63.689.25 km2 atau 6.368,925 Ha.
Sulawesi Tengah pada umumnya di pengaruhi oleh due musim secara tetap yaitu musim Barat yang keying dan musim Timur yang membawa banyak uap air. Musirn .Barat yang keying itu berlaku dari bulan Oktober sampai dengan April yang di tandai dengan kurangnya turun hujan, sedangkan musim Timur yang banyak membawa uap air, yakni pada bulan April sampai dengan Oktober yang ditandai dengan banyaknya turun hujan. Curah hujan di Sulawesi Tengah setahunnya bervariasi antara 800-3000 mm. Kecuali Lembah Palu yang amat kurang mendapat curah hujan, maka variasinya bergerak antara 400-1000 mm saja setahun.
Penduduk yang baru berjumlah satu setengah juta jiwa yang mendiami wilayah ah propinsi yang amat luas itu, dapat dikatakan tidak mudah dapat dengan cepat mengembangkan diri mengelola potensi alam yang besar itu. Namun demikian, keadaan yang dapat dicapai oleh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kehidupan kebudayaannya sejak berabad yang lalu, dapat di katakan tidak' terlampau terisolasi dari perkembangan unum kebudayaan yang terdapat di daerah lain di kepulauan Nusantara ini. Tentu terdapat berbagai faktor yang turut mengambil bahagian dalam perpbentukan kebudayaan penduduk Sulawesi Tengah seperti yang dijumpai sekarang.
Faktor-faktor tersebut antara lain :
1.Gerak perpindahan (migrasi) penduduk pada masa prasejarah yang masuk secara bertahap ke Sulawesi Tengah.
2.Persebaran agama Islam dan Kristen di kalangan penduduk Sulawesi Tengah .
3.Pengaruh dan peranan pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
Beberapa sarjana dalam laporan penelitian mereka telah mencoba melakukan rekonstruksi asal mula persebaran penduduk, serta pertumbuhan kebudayaan yang mereka miliki. Para penulis masa lampau yang amat terkenal seperti Albert C. Kruijt, N. Adriani dan R. W. Kaudren 1).
Rekonstruksi itu didasarkan pada hasil penelitian dan perbandingan dari benda-benda peninggalan praSejarah, bahasa dan mite, serta lagenda penduduk.yang tersebar diberbagai tempat pemukiman yang luas tersebar di wilayah ah ini. Menurut Albert C. Kruijt, daerah yang didiami penduduk Toraja-Sulawesi Tengah itu pada mulanya, lebih dahulu didiami oleh suatu kelompok penduduk yang belum jelas diketahui indan titasnya. Akan tetapi Kleiweg de Zwaan, masih dapat menemukan sisa-sisa dari penduduk Loinang yang berlokasi di Jazirah Timur Sulawesi Tengah.
Dari sini penduduk pembuat tembikar itu menuju ke arah .Utara, ke Daerah Poso Sulawesi Tengah, terus ke daerah Barat, yakni ke daerah Pegunungan Lore, hingga ke daerah aliran Sungai Koro. Dari sana arahnya, kemudian membelok kembali ke Selatan dan berhenti di suatu tempat yang bernama Waebunta, suatu tempat di daerah Galumpang yang kini termasuk wilayah ah Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan.
Migran Pottenbekkers ini menurut Kruyt ada juga yang datangnya dari arah laut (Selatan Makassar ), memasuki daerah Palu dan menyebar ke Lembah Palu. Penduduk pendatang baru itu, membawa anasir kebudayaan baru ke dalam kehidupan penduduk pribumi Lembah Palu, dalam lapangan sosial ekonomi dan relegi, antara lain sebagai berikut :
1.Dalam lapangan ekonomi diperkenalkan teknik pertanian berpengairan.
2.Dalam lapangan relegi disumbangkan satu sistem yang mengenal struktur dewa-dewa yang bertingkattingkat. Disamping itu juga diperkenalkan upacaraupacara keagarnaan yang rumit.
3.Dalam lapangan kehidupan sosial diperkenalkan jumlah peraturan baru, termasuk innovasi dari suatu lapisan sosial baru, yakni lapisan bangsawan, yang berada di atas lapisan sosial yang telah ada lebih dahulu berlaku dalam masyarakat, yaitu lapisan budak dan merdeka.
Eksistensi lapisan sosial bangsawan, sebagai lapisan baru ini terikat pada mite/legenda Sacaerigading dan Manuru Lasaeo. Unsur-unsur kebudayaan baru yang datang bersama orangorang pendatang baru itu, menurut Kruyt diperkirakan berasal dari unsur-unsur kebudayaan Hindu 'Jawa, yang berasal dari Pulau Jawa. Tentang mite/legenda Sawerigading yang terdapat dalam epos Galigo sebagai tokoh orang Bugis di Sulawesi Selatan, diduga persebarannya sebagai tokoh legendaris di Sulawesi Tengah meliputi daerah yang amat luas dari pantai Barat di Selat Makassar, sampai ke Luwuk Banggai di Teluk Tolo.
Selain terjadi migrasi yang berasal dari luar Sulawesi, sepanjang kehidupan penduduk Sulawesi Tengah, terjadi pula beberapa migrasi lokal. Kaudern membahas mengenai migrasi yang berlangsung di Sulawesi Tengah dalam bukunya menyatakan bahwa perpindahan penduduk di daerah ini terjadi karena berbagai sebab, seperti bencana alam, epidemi penyakit dan adat berperang di antara desa-desa. 2) Perang-perang yang amat sering terjadi itu, bertalian erat dengan adat pen,gayauan mereka. Suasana peperangan itu mengakibatkan penduduk desa acapkali mengungsi lebih jauh ke daerah pedalaman yang sukar dijangkau oleh musuhnya. Sebagai akibat lebih jauh dari adat peperangan ini, timbullah lembaga yang berasal dari tawanan perang, pada beberapa kolompok kaum yang besar di Sulawesi Tengah. Juga punahnya sesuatu kaum tertentu, adalah sebagai, akibat adat peperangan itu, seperti yang diambil oleh kepunahan kelompok kaum To Pajapi.
Pemukiman penduduk sebagian besar terpusat disepanjang pantai (71,21%); tersebar dipedalaman (17,15%), termasuk penduduk yang hidup terpencil dipegunungan, berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa, dan selebihnya di daerah kepulauan, (11,64%).
Menurut biasanya, seperti umumnya yang dikemukakan dalam laporan penelitian mutahir 4) SulawesiTengah itu didiami oleh banyak jenis kelompok Etnik (Suku Bangsa), dan terbesar di empat buah Kabupaten, dalam gambar kasarnya sebagai berikut.
Kelompok Etnik (1). Kaili (2). Tomini, (3). Kulawi, umumnya berdian di Kabupaten Donggala. Kelompok-kelompok Etnik (4). Pamona, (5). Lore, (6). Mori, (7). Bungku, umumnya berdiam di Kabupaten Poso. Kelompok-kelompok Etnik (8). Saluan, (9). Balantak, (10). Banggai,umumnya bermukim di Kabupaten Luwuk Banggai. Kelompok-kelompok Etnik (11). Toli-Toli, dan (12). Buol, umumnya bermukim di Kabupaten Buol ToliToli. Dua belas buah kelompok Etnik inilah yang umumnya menjadi pedoman pembagian kelompok Etnik (suku-bangsa) di Sulawesi Tengah.
Cara pengelompokan Etnik tersebut biasanya menurut pengolompokan "bahasa", atau nama tempat pemukiman", mengikuti apa yang sudah dipublikasikan para penelitian sebelumnya.
Di antara kedua belas kelompok Etnik yang manjadi penduduk (asli) Sulawesi Tengah, maka kelompok Etnik Kaili-lah yang terbesar jumlahnya,yaitu kira-kira 45 % dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tengah.
Kelompok kaum atau etnik yang diidentifikasi k rnenurut bahasa yang dipakainya, biasanya digolongk ke dalam narna rumpun bahasa, seperti orang Mela karena berbahasa Melayu, Orang Bugis karena berbaha Bugis; orang Sunda karena berbahasa Sunda dan sebaga nya. Karena pemakaian bahasa itu amat luas terset oleh penutur yang berbeda beda asal tempat tinggalny maka disebutlah misalnya : Orang Melayu Riau; ora Bugis Rappang; orang Sunda Bogor, dan sebagainya. Juga biasa digunakan simbol atau kata tertentu dal suatu bahasa umum yang luas tempat tinggal penuturn tak dapat dibatasi oleh nama tempat saja, maka dipil simbol atau kata khusus dalam dialek bahasa (serumpu itu seperti digunakan oleh Adriani dan Kruijt men identifikasi kan dialek-dialek dalam kalangan apa ya disebutnya Toraja, dengan menggunakan kata sangka seperti Tae, Rai, Ledo, Da'a dan lain-lain yang semu nya berarti "Tidak". Dengan kaitan itu, dibedakann Toraja Tae dari Toraja Data dan'sebagainya.
Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut ci kebudayaan tertentu, seperti To-Panambe, orang ya bermata pencaharian hidup dengan menggunakan al penangkap ikan yang disebut "Panambe": To-Ri-je'n orang (kaum) yang seluruh kehidupannya terletak air. Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut temp kediamannya seperti To-Palu, To (ri) Palu, ialah ora atau kaum yang bermukim di Palu, atau yang beras dari negeri Palu.
BAB II
TO-KAILI (ORANG KAILI)
Wilayah ah propinsi/Dati I Sulawesi Tengah, seperti yang disebut pada permulaan tulisan ini, terdiri atas empat buah daerah Kabupaten/Dati II, didiami oleh kelompok-kelompok etnik, secara umum, menurut daerahdaerah Kabupaten itu di kelompokkan sebagai berikut:
1.To-Kaili, dengan sejumlah sub-etnik antara lain, To-Palu, To-Sigi, To-Dolo To-Biromaru, To-Kulawi, To-Parigi dan lain-lain.
2.To-Pamona dengan sejumlah sub-etnik seperti ToMori, To-Bungku dan lain-lain.
3.To-Banggai dengan sekelompok sub etnik yang berdekatan seperti To-Saluan, To-Balantak dan lain-lain.
4. To-Buol Toli-Toli, dengan sejumlah kelompok kaum yang kecil-kecil.
Diantara kelompok -Kelompok etnik itu yang akat menjadi pokok bahasan tulisan ini ialah kelompok etnil To-Kaili. Kelompok etnik To-Kaili inilah yang terbesai jumlahnya, dan persebarannya dalam seluruh wilayah al propinsi yang amat luas. To-Kaili pada dewasa inmenempati jumlah terbesar yang mendiami daerah kabupaten/ Dati II Donggala, dan sebahagian lainnya bermukir di beberapa wilayah ah kecamatan dalam daerah kabupatei lainnya. Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai ToKai, karena adanya persamaan dalam bahasa dan ada; istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumbei asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua. Fra dalam kalangan semua To-Kaili, digunakan secara umum, Disamping itu terdapat banyak dialek bahasa Kaili van,, juga menjadi identifikasi (sering kali tajam) dari. sut kultur atau sub etnik To-Kaili yang berdiam pada wilayah ah-wilayah ah yang sering kali masih amat terisolasi.
1.To-Palu (To-ri-Palu)
2.To-Biromaru
3.To-Dolo (To-ri-Dolo)
4.To-Sigi (To-ri-Sigi)
5.To-Pakuli, To-Banggai, To-Baluase,To-Sibalaya, To Sidondo
6.To-Lindu
7.To-Banggakoro
8.To-Tamunglcolowi dan To-Baku.
9. To-Kulawi
10.To-Tawaeli (to-payapi)
11..To-Susu, To-Balinggi, To-Dolago
12.To-Petimbe
13.T0-Rarang gonau
14.To-Parigii
Dalam kalangan sub etnik tersebut acap kali terjadi penggolongan yang lebih kecil lagi, dengan ciriciri kliusus, yang kelihatnnya lebih dekat kepada kelompok kekerabatan, yang menunjukkan sifat satuan geneologisnya.
Untuk menemukan pengikat solidaritas dalam kelompok etnik To-Kaili, dicoba diternulcan segala sesuatu yang berbau mitologi, atau cerita-cerita tokoh legendaris atau cerita-cerita rakyat (folk-tale) dalam kalangan To-Kaili dan sub etnik yang terhisap di dalamnya.
To-Kaili yang mendiami Lembah Palu memilki cerita rakyat (folk-tale) yang menjadi pengikat rasa kesatuan To-Kaili tentang asal-usul mereka 4). Tana Kaili yang te-rletak di Lembah Palu (sekarang), menurut ceritera rakyat itu, pada •zaman dahulu kala Lembah Palu ini, masih lautan, di sebut Laut Kai1i atau Teluk Kaili. Nenek moyang To-Kaili pada zainan dahulu itu mendiami lereng-lereng gunung sekeliling Laut Kaili. Konon, di sebelah Timur Laut Kaili itu, terdapat sebatang pohon besar, turnbuh kokoh, tegak dengan kemegahan menjulang tinggi, sebagai tanda pengenal daratan bagi pelaut yang memasuki teluk Kaili. Pohon itu dinamakan Pohon Kaili. Pohon itu tumbuh dipantai dan terletak antara negeri Kalinjo dengan negeri Sigipulu.
Pada suatu hari Laut Kaili mendapat kunjungan sebuah perahu layar yang amat besar, dibawah pimpinan seorang pelaut luar negeri yang namanya sudah arnat tersohor dikawasan ini. Pelaut itu bernama SAGJExIGADING 5). Dikatakan Sawerigading itu, singgah di Teluk Kaili dalam perjalannya kembali dari Tana Cina, menemui dan mengawini tunangannya yang bernama We Cudai. Tempat yang disinggahi pertama oleh perahu Sawerigading, ialah negeri Ganti, ibu negeri Kerajaan Banawa (sekarang Donggala). Antara raja Banawa dengan Sawerigading terjalinlah tali persahabatan yang dilcolcohkan dengan perjanjian ikatan persatuan dQngan kerajan Bugis-Bone, di Sulawesi-Selatan 6). Dalam menyusuri teluk lebih dalam ke arah Selatam sampailah Sawerigading dengan perahunya ke pantai negeri Sigipulu, dalam wilayah ah kerajaan Sigi. Perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan Uwe Mebere, yang sekarang berna~-na Ranoromba. Kerajaan Sigi dipimpin oleh seorang Raja Wanita yang bernama Ngginayo atau Ngili Nayo 7). Raja perempuan ini, belum kawin dan berparas amat cantik. Setibanya di Sigi Sawerigading bertemu langsung dengan raja Ngilinayo yang amat cantik itu. Pada pandengan pertama Sawerigading jatuh cinta. lapun mengajukan pinangan untuk menjadikannya pei-maisuri. Raja Ngilinayo bersedia rnenerirna pinangan Sawerigading dengan syarat ayarn aduannya yang bergelar Calabai 3). dapat dikalahkan oleh ayam aduan Sawerigading yang bergelar Bakka Cimpolon,g (Bg), yaitu ayam berbulu kelabu ke hijauan, dan kepalanya berjambul. Syarat itupun disetujui oleh Sawerigading, dan disepakati, upacara adu ayam itu akan dilangsungkan sekembal Sawerigading dari perjalanan ke pantai Barat, sambi di persi.apkan arena (Wala-wala) adu ayam.
Di pantai Barat perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan negeri Bangga 9). Raja Bangga seorang pe rempuan bernama Wumbulangi di gelar Magau Bangga, yan diceritralcan sebagai To-Manuru 10) Sawerigadingpu menemui baginda dan mengikat perjanjian persahabatan dalam daftar silsilah raja-raja Bangga, Wumbulang adalah Ma~au pertama kerajaan Bangga.
Setibanya di Sigi, Arena untuk penyabungan ayan di atas sebuah gelanggang (wala-wala) sudah dipersiapkan. Ayarn sabungan Sawerigading Bakka Cimpolonp yang akan bertarung melawan Calabai ayam Ngilinayo, semuanya siap di pertarunglean. Pada malam harinya telah diumumkan kepada segenap Iapisan masyarakat, tentank pertarungan yang akan berlangsung ke-esokan paginya. Akan tetapi sesuat.u yang luar biasa telah terjadi pada malarn sebelum pertarungan itu berlangsung, yang menjadi sabab dibatalkannya pertarungan itu.
Anjing Sawerigading yang digelar La-Bolong (SiHitam) turun dari perahu, berjalan jalan di darat Sigi. La-Bolong berjalan ke arah Selatan. Tanpa disadarinya, ia terperangkap kedalam satu Iobang besar, ternpat kediaman seekor belut (Lindu), yang amat besar. Karena merasa terganggu oleh kedatangan anjing labolong yang tiba-tiba itu, maka belut/lindu itupun menjadi marah, dan menyerang La Bolong, maka terjadilah pertarungan yang amat sengit antara keduanya. Pertarungan itu demikian dahsyatnya, sehingga seolah-olah terjadi gempa yang menggetarkan bumi. Penduduk pun menjadi, ketakutan. La-Bolong berhasil menyergap belut/lindu itu, keluar lobangnya. Lobang besar bekas tempat tinggal belut/lindu itu, setelah kosong dan runtuh, lalu menjadi danau, yang hinga kini disebut Danau Lindu.
Anjing Sawerigading La-Bolong melarikan belut itu kearah Utara dalam keadaan meronta-ronta, dan menjadikan lubang berupa saluran yang dialiri oleh air laut yang deras, air yang mengalir dengan deras itu, bagaikan air bah yang tumpah, menyebabkan keringnya air Kaili. Maka terbentuklah Lembah Palu dan terjelmalah Tana--Kaili.
Peristiwa alam yang amat dahsyat ini, membatalkan pertarungan kedua ayam yang telah dipersiapkan dengan cerrnat. Raja Ngilinayo dan Sawerigading sama-sama berikrar untuk hidup sebagai saudara kandung yang saling menghormati i untuk bekerja sama membimbing orang Kaili yang mendiarni Lembah Palu, bekas Teluk Kaili, yang telah menjadi daratan.
Air yang mengalir deras ke laut lepas Selat Makassar menghanyutkan perahu Sawerigading, yang akhirnya terdampar di Sombe. Ceritera rakyat rnenyebut, bahwa gunung yang menyerupai perahu di Sombe itu, adalah bekas perahu Sawerigading yang sekarang di Bulusakaya, yang berarti gunung yang berbentuk perahu. Alat-alat perlengkapan perahu lainnya, antara lain layar, terdampar di pantai sebelah Timur. Tempat itu kini bernama Bulumasomba, artinya gunung yang menyerupai layar.
Sebuah versi lain, mengenai ceritera persaudaraan antara Raja Ngilinayo dengan Sawerigading, menyebutkan bahwa pada menjelang akan diadakannya pertarungan ayam, di adakanlah pesta atau keramaian yang dikunjungi oleh sebahagian besar penduduk kerajaan Sigi. Ferangkat alat kesenian, bunyi-bunyian berupa gong, tambur dan seruling, didaratkan dari perahu Sawerigading, untuk meramaikan pesta kerajaan itu. Gong, tambur, dan genderang dipalu bertalu-talu, memeriahkan pesta itu, mengundang kera:iaian yang gegap gempita. Urang sakitpun yang tadinya terbaring lemah di pembaringan masing-masing, setelah mendan gar bunyi-bunyian itu. Merekapun menghadiri pesta keramaian itu. Penyembuhan dari penyakit, berkat mendan garkan bunyi-bunyian yang mengiringi nyanyian (t'embang), yang diperagakan dengan tari-tarian, dipercaya sebagai obat mujarab. Pengobatan dengan cara itu, disebut Balia, dari dua kata bali + ia artinya lawan ia. Maksudnya setan atau roh jahat yang membawa penyakit harus dilawan.
Puncak acara keramaian malarn itu, ialah peresmian atau pengukuhan sumpah setia persaudaraan antara raja Sigi Ngilinayo dengan Sawerigading. Segenap perangkat alat bunyi-bunyian, diserahkan oleh Sawerigading kepada saudaranya, yaitu Raja Sigi Ngilinayo. Seusai pesta Kerajaan itu, kembalilah Sawerigading dengan anak buahnya ke perahu. Setelah mereka tiba di perahu, mereka dikejutkan oleh adanya getaran bumi yang dahsyat disertai deru air yang bagaikan tautan keras. Dikatan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kareria pergelutan antara Labolong dengan belut/lindu, seperti diceriterakan didepari. Perahu Sawerigadirlg terlepas dari tambatannya, dan hanyut mengikuti arus air ke laut.lepas, Selat Makassar. Berkat lcetangkasar: awak perahu Sawerigading, menyelematkan perahun,da dari malapetaka. Mereka melepaskan diri dari Teluk Kaili yang sudah menjadi daratan, dan selamatlah Saweriading meneruskan perjalanannya kembali ke Tana-Bone Sulawesi-Selatan).
Sawerigading adalah tokoh legendaris dalam ceritera rakyat Tana Kaili. Tokoh itu dihubungkan dengan kedudukan Kerajaan Bone, sebagai kerajaan Bugis di Sulawesi-Selatan yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kai1i. Dapat diperkirakan bahwa hubungan-hubungan yang akrab dengan kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kaili, berlangsung dalam abad ke-17. Adapun tokoh lagendaris Sawerigading di Sulawesi Selatan tersebut dalaiu Epos La-Galigo, dipandang sebagai peletak dasar dan cikal bakal raja-raja Bugis, khususnya di Kerajaan Lucau, yang terletalc pada bahagiaii Utara Selat Bone. Zaman Sawerigading dalam Epos La-Galigo, diperkirakan berlaiigsung dalam abad IX dan X (M). Kedua keadaan itu dalam cerita rakyat Tana Kaili, yaitu tokoh iegendaris Sawerigading dan hubungan persahabatan dengan kerajaan Bone, dipadukan saja sebagai pe-ristiwa istimewa dalam suatu cerita rakyat. Hal seperti itu, adalah biasa dan menjadi karastrestik umum dari suatu cerita rakyat (Folk-Tale), untuk memperoleh semacam pengukuhan legitimasi bagi tokoh-tokoh yang tersangkut dalam peristiwa luar biasa 12). Mungkin sekalli dapat dibuktikan kebenaran ilmi.aluiya, melalui penelitian (arkeologi atau paleoantropologi), bahwa sekitar abad IX-X (M), Lembah Palu masih merupakan lautam sampai negeri Gangga dekat Danau Lindu. Setelah Laut Kaili menjadi daratan, yang membentuk Tana-Kai di Lembah Palu, maka terjadilah hubungan dangan kerajaan Bone dan Gowa yang menguasai perairan Selat Makassar. Ketika itu Kompeni Belanda (VOC) juga sudah mulai melakukan kegiatan intervensi terhadap kerajaan kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Peristiwa-peristiwa penting itu justeru terjadi dalam abad ke XVII. Sekitar abad itu , kerajaan Bone mengunggu kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan di baw pimpinan Aruppalakka, To-Erung malamppee' Gemme' n Ketika itu Kerajaan Bone melakukan hubungan baik m lalui daratan, maupun lautan ke bahagian Timur d Barat Nusantara, termasuk Sulawesi Tengah dan Utar Tana Kaili dan kerajaan Banawa amat banyak di sebabkan dalam Lontara Bugis-Makassar tentang hubungannya , politik dan persaudaraannya dengan negeri-negeri Bugis yang menguasai pelayaran Selat Makassar.
Pada dewasa ini, persebaran pemukiman To-Kaili propinsi Sulawesi Tengah, meliputi sebahagian terbes Kabupaten/Dati II Donggala, dan beberapa wilayah Kecamatan dalam Kabupaten/ Dati II Poso, Banggai d Buol Toli-Toli. Kelompok etnik Tiriombo, Tomini d Moutong yang mendiami pesisir sebelah Timur di Tel Tomini, tadinya masih dapat dipertajam identifikasinya yang berbeda dari kelompok etnik To-Kaili. Teta kini, dilihat dari perkembangan persebaran penerima unsur-unsur kebudayaan yang sama,: maka perbedaa perbedan itu menjadi sangat tipis. Malahan percampur rnelalui jalan kawin-mawin yang amat banyak, teruta dalam kalangan pemuka adat dan masyarakat Kaili dan g To-Tinombo, To-Tomini dan To-Moutong, perbedaan yang pernah mempertajam identifikasi etnik masing-masi kini sudah mencair.
Cacah jiwa orang Kaili yang tersebar luas dal Propinsi Sulawesi Tengah, diperkirakan 45 % dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah, yaitu kira-kira 4 sampai 5 ratus ribu jiwa. To-Kaili pada umumnya atau terbanyak bermukim di sepanjang pantai, baik di pesisir Barat, maupun dipesisir Timur. Oleh karena itu, maka cara hidup clan kebudayaan Kaili yang dominan, kelihatan lebih dekat kesamaannya kepada kebudayaan Bugis-Makassar (Sulawesi-Selatan), dan kebudayaan Melayu (Sumatera dan Malaka ).
Selain dari pada kelompok etnik Kaili, Pamona, Buol Toli-Toli, Banggai dan lain-lain, seperti telah disebut pada bahagiarr depan, masih terdapat lagi keiompok-kelompok etnik dalam jumlah warganya yang tidak , terlalu banyak, tetapi mereka dipandang' sebagai penduduk asli Sulawesi Tengah. Mereka itu kini disebut suku-suku terasirlg, seperti : Lauje, Tajio, Pendau, To-Lare,. Rarang Gonau, Loon , Sea-sea, Daya dan mungkin masih ada lagi lainnya yang belum di kenal. Kelompok-kelompok etnik itu yang jumlah warganya relatif kecil, mendiami lereng gunung secara terpencar-penca-r dalam hutan-hutan. Mereka rnenggunakan bahasa atau dialek tersendiri dalam kehidupan yang terisolasi itu. Secara umum dapat ditandai keadaan fisik mereka yang berbeda dalam dua golongan. Pada umumnya To-Lare (Orang 'gunung) yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Barat Lembah Palu, disebut juga Tolare-bulumpanau, memiliki warna kulit yang agak cerah. Sebaliknya To-Tare yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Timur Lembah Palu disebut juga To-Lare-Bulungpadake, memillki warna kulit gelap.
Kelompok- Kelompok Sub-etnik Kaili seperti yang disebut pada bahagian depan masing--masing rnemiliki kekhususan baik mengenai ceritera tentang asal usul, maupun dialek serta pernyataan kulturalnya, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :
1.Penduduk asli Lembah Palu. Di Lembah Palu dan sepanjang pantai teluk Palu bermukim To-Kaili, sebagai satu kelompok etnik di kawasan ini 14). Penduduk Lembah Palu, terdiri atas beberapa kelompok sub-etnik atau kelompok kaum, dengan dialekdialek bahasa masing-masing.
Pemukiman awal ke-empat kelompok kaum ini, mehurut petunjuk yang diketemukan sekarang, adalah sebagai berikut:
To-ri Palu, bermukim pada bagian Utara lembah, sepanjang dua sisi muara Sungai Palu.
To-Biromaru dan To-ri Sigi, bermukim di bagian Selatan To-ri Palu, pada sebelah kanan daerah aliran sungai Palu, dengan kekecualian bagian kecil sebelah Utara Wunu, di sana berdiam To-ri Dolo, bermukim di sebelah Selatan To-ri Palu, pada bagian ki-ri daerah aliran Sungai Palu. Di lereng-lereng gunung bagian Utara Lembah Palu juga sudah berdiam sejak dahulu kala penduduk yang disebut To-Lare (Orang gunung). Disamping To-Lare terdapat juga To-Petimpe, yang berdiam di lerenglereng gunung sebelah Utara lembah, terutama dalam wilayah ah Palolo. To-Petimpe secara etnik tidak banyak hubungannya dengan penduduk asli Lembah Palu. Menurut berbagai keterangan To-Petimpe itu, keturunan To-Balinggi dari Tana-Boa di Teluk Tomini, atau mungkin juga dari To-Pebato, satu kaur yang berdiam di muara sungai Puna.
Pada bagian yang agak jauh ke Selatan Lembah Palu, sekitar Gumbasa, Miu, Salcuri pada daerah aliran Sungai Palu, terdapat dua kelompok kaum yaitu To-Pakuli sekitar Gumbasa dan Miu, dan To-Sakuri sekitar Miu. Disana terletak negeri Bangga yang penduduknya berbahasa sama dengan To-Pakuli.
2.To-ri Palu dan To- Biromaru. Penduduk Lembah Palu, berasal dari pegunungan sekitar Lembah Palu itu juga. Ketika bermukim di Lerabah Palu, sejak awalaya-pun, mereka telah berkelompok l:e dalam tiga buah kaum, yaitu : To-ri Sigi, To-ri Dolo dan To--ri Palu.
Berbagai cerita rakyat yang samar-sarna diingat melaiui ceritera atau tutur o-ang tua-tua, bahwa ketiga kaum irri, acapkali saling memerangi antara satu sama lainnya. Karena begitul;ah mereka dalam bermukim di Lernbah Paiu, masing -masing memilih tempat yang secara alamiah terlindung dari upaya serangan-serangan terbuka dari pihak lawarrnya. Malahan ada kecenderungan mempertahanl sosialisasi mereka satu sama lainnya.
To-ri Palu yang rnendiami wilayah Palu, kabarnya berasal dari pegunungan sebelaii Timur. Di Tempat asal mereka, dipegunungan itu, terdapat satu tempat yang bernama Buluwatumpalu, disana bertumbuh banyak tanarnan barnbu yang dipergunakan dalam kehidupan. Untuk mengingat asal nama negeri Buluwaturnpalu yang berarti bambu kecil, maka tempat yang mereka pilih untuk bermukim, yaitu di muara sungai besar yang sekarang bernarna Sungai Palu, disebutnya dari kata itu, yaitu mPalu (kecil). Di mana letak tempat yang disebut Buluwatumpalu itu, diperkirakan di salah satu tempat di atas bukit Paneki sekarang, yang disebut Raranggonau.
Adapun To-Biromaru, diduga keras berasal dari leluhur yang sama dengan To-ri Palu, yang sama-sama menggunakan dialek Kaili-Ledo. Pemelcaran menjadi kaum sendiri itu, terjadi kemudian setelah pemisahan tempat pemukiman.
To-Biromaru mendiarRi tempat yang lebih kedalam di daerah lereng dalam lembah yang subur. Pemisahan menjadi dua kelompok kaum itu terjadi sebelum abad ke-XVII 17).
3.To-ri Sigi, To-ri Dolo.
Menurut catatan Valentijn (1724), To-ri Sigi dan To-ri Dolo diperkirakan sudah bermukim di Lembah Palu sejak ak'nir abad XVII atau pada permulaan abad XVIII. Kedua kelompok kaum ini, menggunakan dialek bahasa Kaili yang sama, yaitu dialek Ija. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berasal da,ri leluhur yang sama. Akan tetapi sejarah kehidupan mereka sejak awal, selalu diwarnai oleh permusuhan dan peperangan antara keduanya.
Dari mana asal kedua kelompok kaum ini pada mulanya sebelum bermuhim di Lembah Palu, terdapat beberapa keterangan. Salah satu cerita yang hampir sarna dengan keterangan Hissink, diterlukan dikalangan penduduk Sigi, sebagai berikut. Sebelum To-ri Sigi bermukini di Lernbah Palu, yaitu di Bora, Watunonju, Oloboju dan Sigi, leluhur merelca berrnukim di sele,lah utara Danau Lindu di lereng-lereng gunung, di terapat-tenlpat pemukiman yang disebut Leu, Silonga, Wowolau, Ue-hialaei dan Sigipulu.
Mengenai To-ri Dolo, menurut beberapa cerita rakyat, dikatakan berasal dari daerah pegunungan yang lebih ke Utara lagi letaknya dalam tempattempat pemukiman yang bernama Dolo, Maru dan Pompewajo. Dimana tempat-tempat itu terletak di lerenglereng gunung sekarang, tidak diperoleh petunjuk yang jelas dari penduduk. Tetapi nama-nama itu, masih ada mengingatnya. Kemungkinan besar, bekasbekas pemukiman To-ri Sigi terletak sekitar negeri Palolo sekarang, tempat-tempat pemukiman awal ToDolo, justru terletak sekitar negeri sekarang.
4.To-Pakuli; To-Pakuli; To-Bangga;To-Baluase; ToSibalaya; To-Sidondo adalah kelompok-lcelompok kaum dalam komunitas yang kecil-kecil. Mereka bermukim di sebelah Selatan wilayah ah pemukiman To-ri Sigi. Mereka menggunakan dialelc bahasa Kaili yang disebut Ado atau Edo. Dialek Ado amat dekat kepada dialek Ija yang dipergunakan oleh To-ri Sigi diperkirakan sebelum mereka bermukim di Lembah Palu, mereka berdiam di lereng-lereng pegunungan sebelah Timur dan Tenggara Lembah Palu.
5.To-Tawaili (To-Yayapi). Dalam iembah sebelah utara Napu hiduplah pada zaman dahulu sekelompok kaum yang menamakan diri To-Tawaeli atau To-Payapi. Karena berbagai gangguan dari kaum di sekitarnya lalu berpindah melewati sebelah Utara Danau Lindu, melintasi nege-ri Sigi dan akhirnya sampai ke Budong-Budong, di sebelah Selatan Donggala di pantai Selat Makassar. Sebagiaii lainnya menetap di Sausu, Dolago dan Parigi.
Pada dewasa ini, To-Tawaeli yang bermukim di wilayah ah Kecamatan Tawaeli yang terletak di sebelah Utara Kota Palu, dalam cerita rakyat yang sudah samar-samar dalam ingatan para penuturnya mengatakan bahwa To-Tawaeli berasal dari bagian Selatan pantai Selat Makassar.
6.To-Lindu, bermukim sekitar Danau Lindu. Mereka percaya dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lembah Palu. Para pemimpin adat Lindu atau keturunan mereka yang ada sekarang, selalu menyatakann diri berasal dari Sigi di Lembah Palu. Keterangan seperti juga dijumpai pada umumnya dalam kalangan penduduk lereng-lereng pegunungan sebelah Selatan di lembah Palu, bahwa nenek moyang mereka berasal dari Sigi.
7.To-Banggakoro. yang mendiami daerah pegunungan jauh di sebelah barat Kulawi dapat dikatakan secara kebudayaan lebih banyak bersentuhan dengan kebudayaan Mamuju di pantai Barat dan kebudayaan Lembah Palu di sebelah Utara. Asal mula penduduk terdahulu To-Banggakoro tak dapat ditemukan dalam ceritacerita rakyat. Akan tetapi besar sekali persamaan kelompok kaum ini (To-Banggakoro) dengan penduduk Bangga yang berasal dari bagian Selatan Lembah Palu.
8.To-Tamungkolowi; To-Tabaku, berdiam di atas pegunungan sebelah Barat negeri Kulawi. Tidak ditemukan legenda ataupun ceritera-ceritera rakyat yang memperkatakan tentang asal usul mereka. Akan tetapi berbagai ungkapan dan benda-benda kebudayaan sub-etnik'ini, seperti sebutan Sou-eo, dan pakaian atau alat-alat perhiasan wanita dan tata rambutnya,sama dengan yang pada umumnya terdapat di Lembah Palu. Dari pengamatan-pengamatan yang lebih dekat dan lama dapat dikatakan bahwa To-Tamungkolowi dan To-Tabaku, juga pada awalnya berasal da-ri bahagian Selatan Lembah Palu.
9.To-Kulawi, yang berdiam di sebelah Selatan Danau Lindu, menurut legenda,mereka berasal dari Bora dan Sigi di Lembah Palu. Menurut ceritera rakyat, bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang bangsawan dari Bora bersarna pengikutnya berburu ke hutan-hutan dan gunung Momi di daerah Kulawi yang masih lengang. Para pemburu berteduh dibawah pohon yang amat rimbun.dan lebat daunnya. Mereka namakan pohon itu, pohon Kulawi.Jenis pohon itu sekarang tidak ditemukan lagi.
10.To-Sausu; To-Balinggi; To-Dolago, diantara Sungai Tambarana dengan Parigi di Pantai Timur SulawesiTengah, terdapatlah negeri-negeri Sausu, Tana -Boa dan Dolago. Disitulah kelompok-kelompok kaum yang menyebutkan diri To-Balinggi dan To-Sausu berdiam. Menurut ceritera rakyat, baik To-Sausu maupun ToBalinggi berasal dari keturunan yang sama yang disebut To-Lopontato yang bermukim di lereng-lereng gunung. Kaum ini amat erat hubungan kebudayaanya dengan To-Parigi. Adapun To-Dolago menurut ceritera rakyat itu, juga adalah dari suatu keturunan dengan kedua kaum lainya, yaitu To-Sausu dan To-Dolago. Tetapi kemudian hidup memisahkan diri karena lingkungan alam, tetapi tetap merasa mempunyai hubungan kekeluargaa<< dengan To-Parigi, juga dengan To-Sigi.
11.To-Parigi. Negeri Parigi terletalc di sebelah Utara Sausu di Teluk Tomini. Pada umtlimnya penduduk negeri Parigi yang disebut To-Parigi percaya bahwa nenek rr,oyang rnereka, berasal dari Lembah Palu. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat Parigi selanjutnya, banyak juga terjadi kontak dengan kelompok etnik Panona dari Wilayah ah Poso, sehingga beberapa pengamat menduga, bahwa orang Parigi dapat digolongkan ke dalam kelompok etnik Pamona-Poso.18).
Dapat diduga ballwa oi-ar,g Kaili yang sekarang me diami Lembah Palu, berasal dari arah Tenggara Utara Barat Daya, yaitu dari daerah sebelah Uta Danau Poso. Ada yang bergerak kearah Baiat dan ke a-r pantai Teluk Tomini, dan ke aril Selatan dan Tim Lembah Palu hingga pantai Seiat Makassar.
BAB III
SEKELUMIT SEJARAH KEBUDAYAAN KAILI
Tempat awal pemukiman sesuatu kaum yang pada hakekatnya terpisah-pisah, malahan terisolasi dari tempat pemukiman kaum lainnya, biasa disebut Ngapa. Da-ri Ngapa itulah dimulai peradaban sesuatu kaum, yang lambat laun berturnbuh jumlah warganya dan memekari:an tempat-tempat pemukiman baru itu. Tempat-tempat pemukiman baru disekitar Ngapa itu, selaku perluasan pemukiman kaum perluasan kaum seasal biasanya disebut Boya atau Soki.
Tempat penukiman lain yang terbentuk oleh adanya lapangan pekerjaan tertentu seperti komunitas (persekutuan) tani atau nelayan dinamakan Kinta. apabila pada suatu waktu perkembangan Ngapa menjadi sudah cukup luasnya ole'n dukungan sejumlah Boya, Kinta dan Soki, maka terbentuklah satu wilayah a territorial dengan susunan kekuasaan yang ditaati- oleh penduduk. Terbentuklah apa yang dinamakan secara umum kerajaan lokal, yang dapat disebut "Kagaukang" atau "Kagau".
Menurut berbagai sumber, 1) sebelum terjadinya struktur kerajaan yang disusun dalam perangkat kekuasaan pejabat-pejabat secara hierarchis, sesuatu wilayah ah pemukiman kaum yaitu Ngapa atau sejenisnya dikuasai atau dipimpin oleh orang yang disebut '1'0Malanggai. Ia adalah pemimpin yang dipandang perkasa, seorang jantan yang mengatasi jantan-jantan lainnya. la-pun dapat disebut "penakluk" atas kaum yang bermukim disekitarnya. Dasar kepemimpinannya adalah keberanian, kepeloporan, untuk mengungguli orang-orang atau kaum yang dipimpinnya.
BAB IV
MODAL PERSONALITY ORANG KAILI
Konsep MODAL PERSONALITY, atau kalau hendak diterjemahkan secara sederhana, dapat disebut PERASAAN KKPKIBADIAN. Penguraian tentang modal-personality, pertama-tama akan menghadapi secara serius persoalan metodologis, untuk penerapannya. Kita akan menghadapi suatu masyarakat dengan segala persoalannya yang amat rumit. Wilayah ah masyarakat itu yang seringkali amat luas, aneka ragam pranata dan lembaga sosial; aneka macam lingkungan alam tisik darn kebudayaan; aneka macam iklim yang dibawa oleh aneka macam keadaan lingkungan, seperti gunung, lembah dan dataran yang membentang luas, semua itu secara metodologis harus diperhitungkan dalam penelitian atau pengamatan yang diperlukan, untuk melukis kan PERASAAN KEPRIBADIAN itu. Oleh karena itu, suatu perkiraan umum yang dipandang representatit atau secara wajar mewakili segenap keadaan yang sesungguhnya amat diperlukan. Tentu saja sangat di perlukan adanya sampling secara statistik dari berbagai daerah kesatuan hidup, atau kelompok sosial, jenis-jenis lapangan pekerjaan, tingkat usaha dan lain-lain, untuk mendapatkan gambaran yang sungguh-sungguh dapat memuaskan, sebagai gambaran umum tentang perasaan kepribadian sesuatu kaum, seperti yang akan dilukiskan disini, yaitu YEKASAAN KEPRIBADIAN ORANG KAILI.
Dalam pengertian umum, tulisan ini hendak mencota melukiskan ciri-ciri kepribadian To-Kaili, melalui perasaan kepribadian yang ditampilkan dalam berbagai tata kelakuan dalam kehidupan yang membudaya atau bernilai budaya. la secara aktual dianut atau dihargai sebagai perilaku sosial dan secara umum dilakukan dalam kehidupan. Deilgan kata lain, apa yang dilakukan atau diperbuat oleh orang Kaili, sehingga ia merasa diri sebagai To-Kaili.
Sesuatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan yang bermakna ke-Kaili-an, karena seseorang (Kaili) yang melakukannya merasa diri orang Kaili, ('To-Kaili). To-Kaili lainnya melihat ia melakukari perbuatan itu, segera mengetahui bahwa ia adalah To-Kaili. Maka antara yang melakukan dengan yang mengamati kelakuan itu tumbuh tali perhubungan yang alafniah sebagai hubungan keakraban (familiar). Karena apa yang diamati itu seolah-olah adalah dirinya sendiri. Ia akrab dengan perilaku atau tingkah laku seperti yang dilakukan dalam kebudayaan Kaili.
Patokan-patokan umum yang dapat dipergunakan dalam menjaring perasaan-perasaan kepribadian itu, adalah biasanya perbuatan-perbuatan atau perilaku yang amat lekat pada kehidupan emosional atau yang menyentuh perasaan-perasaan terdalam, seperti pada perasaan hidup :
1.Kekerabatan dan kenasyarakatan,
2.Keagamaan dan kepercayaan,
3.Bahasa, kesusasteraan dan kesenian pada umumnya.
Pertemuan-pertemuan, berupa pesta-pesta dalam keluaga, membuka kesempatan bagi para remaja untuk saling bertemu dan berkenalan, melalui perkenalan di pesta-pesta itu, terjalinlah hubungan-hubungan yang akan mengantarkan ke(-'Iua remaja yang saling mencintai itu, untuk memasuki tingkat hubunban formal menuju perkawinan/pernikahan.
UPACARA PEMINANGAN : Upacara-upacara pernikahan, lebih banyak memperlihatkan segi-segi formal yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Hal-hal yang formal itu dilakukan untuk saling memberikan kesan tentang adanya kesungguhan kedua belah pihak untuk membangun pertalian keluarga besar.
Rangkaian upacara menjelang hari pernikahan, merupakan formalitas yang kelihatannya amat cermat dijalankan. Orang menamakannya upacara adat, untuk menjaga harmoni dalam kehidupan. Menurut ceritera, adapun NOTATE DALA (upacara manbuka jalan) dilakukan, untuk menjaga agar tidak terjadi penolakan pinangan, atau gadis itu telah ada yang meminangnya lebih dahulu. Kalau terjadi yang demikian, dahulu kala dipandang rnembawa aib bagi keluarga laki-laki.
Dalam upacara peminangan, berbagai benda yang bermakna simbolik diantarkan oleh pihak laki-laki yang diberikan oleh pihak pererrrpuan, antara lain sebagai berikut: SP.MPULOIGI (perbiasan emas perak buat perernpuan). SABALE KAMAGI (buah kalung emas).
Berbagai upacara adat dalam pelaksanaan acara perkawinan seperti tersebut di atas dilakukan dengan sedapat mungkin menampilkan idan titas keluarga yang menjadi penyelenggranya. Upacara itu menunjukkan kedudukan keluarga itu dalan masyarakat, sesuai nilai dan norma yang berlaku. Pada upacara itu ditampilkan ke
PENDAHULUAN
Luas Wilayah Dati I Sulawesi Tengah, 63.689.25 km2 atau 6.368,925 Ha.
Sulawesi Tengah pada umumnya di pengaruhi oleh due musim secara tetap yaitu musim Barat yang keying dan musim Timur yang membawa banyak uap air. Musirn .Barat yang keying itu berlaku dari bulan Oktober sampai dengan April yang di tandai dengan kurangnya turun hujan, sedangkan musim Timur yang banyak membawa uap air, yakni pada bulan April sampai dengan Oktober yang ditandai dengan banyaknya turun hujan. Curah hujan di Sulawesi Tengah setahunnya bervariasi antara 800-3000 mm. Kecuali Lembah Palu yang amat kurang mendapat curah hujan, maka variasinya bergerak antara 400-1000 mm saja setahun.
Penduduk yang baru berjumlah satu setengah juta jiwa yang mendiami wilayah ah propinsi yang amat luas itu, dapat dikatakan tidak mudah dapat dengan cepat mengembangkan diri mengelola potensi alam yang besar itu. Namun demikian, keadaan yang dapat dicapai oleh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kehidupan kebudayaannya sejak berabad yang lalu, dapat di katakan tidak' terlampau terisolasi dari perkembangan unum kebudayaan yang terdapat di daerah lain di kepulauan Nusantara ini. Tentu terdapat berbagai faktor yang turut mengambil bahagian dalam perpbentukan kebudayaan penduduk Sulawesi Tengah seperti yang dijumpai sekarang.
Faktor-faktor tersebut antara lain :
1.Gerak perpindahan (migrasi) penduduk pada masa prasejarah yang masuk secara bertahap ke Sulawesi Tengah.
2.Persebaran agama Islam dan Kristen di kalangan penduduk Sulawesi Tengah .
3.Pengaruh dan peranan pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
Beberapa sarjana dalam laporan penelitian mereka telah mencoba melakukan rekonstruksi asal mula persebaran penduduk, serta pertumbuhan kebudayaan yang mereka miliki. Para penulis masa lampau yang amat terkenal seperti Albert C. Kruijt, N. Adriani dan R. W. Kaudren 1).
Rekonstruksi itu didasarkan pada hasil penelitian dan perbandingan dari benda-benda peninggalan praSejarah, bahasa dan mite, serta lagenda penduduk.yang tersebar diberbagai tempat pemukiman yang luas tersebar di wilayah ah ini. Menurut Albert C. Kruijt, daerah yang didiami penduduk Toraja-Sulawesi Tengah itu pada mulanya, lebih dahulu didiami oleh suatu kelompok penduduk yang belum jelas diketahui indan titasnya. Akan tetapi Kleiweg de Zwaan, masih dapat menemukan sisa-sisa dari penduduk Loinang yang berlokasi di Jazirah Timur Sulawesi Tengah.
Dari sini penduduk pembuat tembikar itu menuju ke arah .Utara, ke Daerah Poso Sulawesi Tengah, terus ke daerah Barat, yakni ke daerah Pegunungan Lore, hingga ke daerah aliran Sungai Koro. Dari sana arahnya, kemudian membelok kembali ke Selatan dan berhenti di suatu tempat yang bernama Waebunta, suatu tempat di daerah Galumpang yang kini termasuk wilayah ah Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan.
Migran Pottenbekkers ini menurut Kruyt ada juga yang datangnya dari arah laut (Selatan Makassar ), memasuki daerah Palu dan menyebar ke Lembah Palu. Penduduk pendatang baru itu, membawa anasir kebudayaan baru ke dalam kehidupan penduduk pribumi Lembah Palu, dalam lapangan sosial ekonomi dan relegi, antara lain sebagai berikut :
1.Dalam lapangan ekonomi diperkenalkan teknik pertanian berpengairan.
2.Dalam lapangan relegi disumbangkan satu sistem yang mengenal struktur dewa-dewa yang bertingkattingkat. Disamping itu juga diperkenalkan upacaraupacara keagarnaan yang rumit.
3.Dalam lapangan kehidupan sosial diperkenalkan jumlah peraturan baru, termasuk innovasi dari suatu lapisan sosial baru, yakni lapisan bangsawan, yang berada di atas lapisan sosial yang telah ada lebih dahulu berlaku dalam masyarakat, yaitu lapisan budak dan merdeka.
Eksistensi lapisan sosial bangsawan, sebagai lapisan baru ini terikat pada mite/legenda Sacaerigading dan Manuru Lasaeo. Unsur-unsur kebudayaan baru yang datang bersama orangorang pendatang baru itu, menurut Kruyt diperkirakan berasal dari unsur-unsur kebudayaan Hindu 'Jawa, yang berasal dari Pulau Jawa. Tentang mite/legenda Sawerigading yang terdapat dalam epos Galigo sebagai tokoh orang Bugis di Sulawesi Selatan, diduga persebarannya sebagai tokoh legendaris di Sulawesi Tengah meliputi daerah yang amat luas dari pantai Barat di Selat Makassar, sampai ke Luwuk Banggai di Teluk Tolo.
Selain terjadi migrasi yang berasal dari luar Sulawesi, sepanjang kehidupan penduduk Sulawesi Tengah, terjadi pula beberapa migrasi lokal. Kaudern membahas mengenai migrasi yang berlangsung di Sulawesi Tengah dalam bukunya menyatakan bahwa perpindahan penduduk di daerah ini terjadi karena berbagai sebab, seperti bencana alam, epidemi penyakit dan adat berperang di antara desa-desa. 2) Perang-perang yang amat sering terjadi itu, bertalian erat dengan adat pen,gayauan mereka. Suasana peperangan itu mengakibatkan penduduk desa acapkali mengungsi lebih jauh ke daerah pedalaman yang sukar dijangkau oleh musuhnya. Sebagai akibat lebih jauh dari adat peperangan ini, timbullah lembaga yang berasal dari tawanan perang, pada beberapa kolompok kaum yang besar di Sulawesi Tengah. Juga punahnya sesuatu kaum tertentu, adalah sebagai, akibat adat peperangan itu, seperti yang diambil oleh kepunahan kelompok kaum To Pajapi.
Pemukiman penduduk sebagian besar terpusat disepanjang pantai (71,21%); tersebar dipedalaman (17,15%), termasuk penduduk yang hidup terpencil dipegunungan, berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa, dan selebihnya di daerah kepulauan, (11,64%).
Menurut biasanya, seperti umumnya yang dikemukakan dalam laporan penelitian mutahir 4) SulawesiTengah itu didiami oleh banyak jenis kelompok Etnik (Suku Bangsa), dan terbesar di empat buah Kabupaten, dalam gambar kasarnya sebagai berikut.
Kelompok Etnik (1). Kaili (2). Tomini, (3). Kulawi, umumnya berdian di Kabupaten Donggala. Kelompok-kelompok Etnik (4). Pamona, (5). Lore, (6). Mori, (7). Bungku, umumnya berdiam di Kabupaten Poso. Kelompok-kelompok Etnik (8). Saluan, (9). Balantak, (10). Banggai,umumnya bermukim di Kabupaten Luwuk Banggai. Kelompok-kelompok Etnik (11). Toli-Toli, dan (12). Buol, umumnya bermukim di Kabupaten Buol ToliToli. Dua belas buah kelompok Etnik inilah yang umumnya menjadi pedoman pembagian kelompok Etnik (suku-bangsa) di Sulawesi Tengah.
Cara pengelompokan Etnik tersebut biasanya menurut pengolompokan "bahasa", atau nama tempat pemukiman", mengikuti apa yang sudah dipublikasikan para penelitian sebelumnya.
Di antara kedua belas kelompok Etnik yang manjadi penduduk (asli) Sulawesi Tengah, maka kelompok Etnik Kaili-lah yang terbesar jumlahnya,yaitu kira-kira 45 % dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tengah.
Kelompok kaum atau etnik yang diidentifikasi k rnenurut bahasa yang dipakainya, biasanya digolongk ke dalam narna rumpun bahasa, seperti orang Mela karena berbahasa Melayu, Orang Bugis karena berbaha Bugis; orang Sunda karena berbahasa Sunda dan sebaga nya. Karena pemakaian bahasa itu amat luas terset oleh penutur yang berbeda beda asal tempat tinggalny maka disebutlah misalnya : Orang Melayu Riau; ora Bugis Rappang; orang Sunda Bogor, dan sebagainya. Juga biasa digunakan simbol atau kata tertentu dal suatu bahasa umum yang luas tempat tinggal penuturn tak dapat dibatasi oleh nama tempat saja, maka dipil simbol atau kata khusus dalam dialek bahasa (serumpu itu seperti digunakan oleh Adriani dan Kruijt men identifikasi kan dialek-dialek dalam kalangan apa ya disebutnya Toraja, dengan menggunakan kata sangka seperti Tae, Rai, Ledo, Da'a dan lain-lain yang semu nya berarti "Tidak". Dengan kaitan itu, dibedakann Toraja Tae dari Toraja Data dan'sebagainya.
Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut ci kebudayaan tertentu, seperti To-Panambe, orang ya bermata pencaharian hidup dengan menggunakan al penangkap ikan yang disebut "Panambe": To-Ri-je'n orang (kaum) yang seluruh kehidupannya terletak air. Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut temp kediamannya seperti To-Palu, To (ri) Palu, ialah ora atau kaum yang bermukim di Palu, atau yang beras dari negeri Palu.
BAB II
TO-KAILI (ORANG KAILI)
Wilayah ah propinsi/Dati I Sulawesi Tengah, seperti yang disebut pada permulaan tulisan ini, terdiri atas empat buah daerah Kabupaten/Dati II, didiami oleh kelompok-kelompok etnik, secara umum, menurut daerahdaerah Kabupaten itu di kelompokkan sebagai berikut:
1.To-Kaili, dengan sejumlah sub-etnik antara lain, To-Palu, To-Sigi, To-Dolo To-Biromaru, To-Kulawi, To-Parigi dan lain-lain.
2.To-Pamona dengan sejumlah sub-etnik seperti ToMori, To-Bungku dan lain-lain.
3.To-Banggai dengan sekelompok sub etnik yang berdekatan seperti To-Saluan, To-Balantak dan lain-lain.
4. To-Buol Toli-Toli, dengan sejumlah kelompok kaum yang kecil-kecil.
Diantara kelompok -Kelompok etnik itu yang akat menjadi pokok bahasan tulisan ini ialah kelompok etnil To-Kaili. Kelompok etnik To-Kaili inilah yang terbesai jumlahnya, dan persebarannya dalam seluruh wilayah al propinsi yang amat luas. To-Kaili pada dewasa inmenempati jumlah terbesar yang mendiami daerah kabupaten/ Dati II Donggala, dan sebahagian lainnya bermukir di beberapa wilayah ah kecamatan dalam daerah kabupatei lainnya. Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai ToKai, karena adanya persamaan dalam bahasa dan ada; istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumbei asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua. Fra dalam kalangan semua To-Kaili, digunakan secara umum, Disamping itu terdapat banyak dialek bahasa Kaili van,, juga menjadi identifikasi (sering kali tajam) dari. sut kultur atau sub etnik To-Kaili yang berdiam pada wilayah ah-wilayah ah yang sering kali masih amat terisolasi.
1.To-Palu (To-ri-Palu)
2.To-Biromaru
3.To-Dolo (To-ri-Dolo)
4.To-Sigi (To-ri-Sigi)
5.To-Pakuli, To-Banggai, To-Baluase,To-Sibalaya, To Sidondo
6.To-Lindu
7.To-Banggakoro
8.To-Tamunglcolowi dan To-Baku.
9. To-Kulawi
10.To-Tawaeli (to-payapi)
11..To-Susu, To-Balinggi, To-Dolago
12.To-Petimbe
13.T0-Rarang gonau
14.To-Parigii
Dalam kalangan sub etnik tersebut acap kali terjadi penggolongan yang lebih kecil lagi, dengan ciriciri kliusus, yang kelihatnnya lebih dekat kepada kelompok kekerabatan, yang menunjukkan sifat satuan geneologisnya.
Untuk menemukan pengikat solidaritas dalam kelompok etnik To-Kaili, dicoba diternulcan segala sesuatu yang berbau mitologi, atau cerita-cerita tokoh legendaris atau cerita-cerita rakyat (folk-tale) dalam kalangan To-Kaili dan sub etnik yang terhisap di dalamnya.
To-Kaili yang mendiami Lembah Palu memilki cerita rakyat (folk-tale) yang menjadi pengikat rasa kesatuan To-Kaili tentang asal-usul mereka 4). Tana Kaili yang te-rletak di Lembah Palu (sekarang), menurut ceritera rakyat itu, pada •zaman dahulu kala Lembah Palu ini, masih lautan, di sebut Laut Kai1i atau Teluk Kaili. Nenek moyang To-Kaili pada zainan dahulu itu mendiami lereng-lereng gunung sekeliling Laut Kaili. Konon, di sebelah Timur Laut Kaili itu, terdapat sebatang pohon besar, turnbuh kokoh, tegak dengan kemegahan menjulang tinggi, sebagai tanda pengenal daratan bagi pelaut yang memasuki teluk Kaili. Pohon itu dinamakan Pohon Kaili. Pohon itu tumbuh dipantai dan terletak antara negeri Kalinjo dengan negeri Sigipulu.
Pada suatu hari Laut Kaili mendapat kunjungan sebuah perahu layar yang amat besar, dibawah pimpinan seorang pelaut luar negeri yang namanya sudah arnat tersohor dikawasan ini. Pelaut itu bernama SAGJExIGADING 5). Dikatakan Sawerigading itu, singgah di Teluk Kaili dalam perjalannya kembali dari Tana Cina, menemui dan mengawini tunangannya yang bernama We Cudai. Tempat yang disinggahi pertama oleh perahu Sawerigading, ialah negeri Ganti, ibu negeri Kerajaan Banawa (sekarang Donggala). Antara raja Banawa dengan Sawerigading terjalinlah tali persahabatan yang dilcolcohkan dengan perjanjian ikatan persatuan dQngan kerajan Bugis-Bone, di Sulawesi-Selatan 6). Dalam menyusuri teluk lebih dalam ke arah Selatam sampailah Sawerigading dengan perahunya ke pantai negeri Sigipulu, dalam wilayah ah kerajaan Sigi. Perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan Uwe Mebere, yang sekarang berna~-na Ranoromba. Kerajaan Sigi dipimpin oleh seorang Raja Wanita yang bernama Ngginayo atau Ngili Nayo 7). Raja perempuan ini, belum kawin dan berparas amat cantik. Setibanya di Sigi Sawerigading bertemu langsung dengan raja Ngilinayo yang amat cantik itu. Pada pandengan pertama Sawerigading jatuh cinta. lapun mengajukan pinangan untuk menjadikannya pei-maisuri. Raja Ngilinayo bersedia rnenerirna pinangan Sawerigading dengan syarat ayarn aduannya yang bergelar Calabai 3). dapat dikalahkan oleh ayam aduan Sawerigading yang bergelar Bakka Cimpolon,g (Bg), yaitu ayam berbulu kelabu ke hijauan, dan kepalanya berjambul. Syarat itupun disetujui oleh Sawerigading, dan disepakati, upacara adu ayam itu akan dilangsungkan sekembal Sawerigading dari perjalanan ke pantai Barat, sambi di persi.apkan arena (Wala-wala) adu ayam.
Di pantai Barat perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan negeri Bangga 9). Raja Bangga seorang pe rempuan bernama Wumbulangi di gelar Magau Bangga, yan diceritralcan sebagai To-Manuru 10) Sawerigadingpu menemui baginda dan mengikat perjanjian persahabatan dalam daftar silsilah raja-raja Bangga, Wumbulang adalah Ma~au pertama kerajaan Bangga.
Setibanya di Sigi, Arena untuk penyabungan ayan di atas sebuah gelanggang (wala-wala) sudah dipersiapkan. Ayarn sabungan Sawerigading Bakka Cimpolonp yang akan bertarung melawan Calabai ayam Ngilinayo, semuanya siap di pertarunglean. Pada malam harinya telah diumumkan kepada segenap Iapisan masyarakat, tentank pertarungan yang akan berlangsung ke-esokan paginya. Akan tetapi sesuat.u yang luar biasa telah terjadi pada malarn sebelum pertarungan itu berlangsung, yang menjadi sabab dibatalkannya pertarungan itu.
Anjing Sawerigading yang digelar La-Bolong (SiHitam) turun dari perahu, berjalan jalan di darat Sigi. La-Bolong berjalan ke arah Selatan. Tanpa disadarinya, ia terperangkap kedalam satu Iobang besar, ternpat kediaman seekor belut (Lindu), yang amat besar. Karena merasa terganggu oleh kedatangan anjing labolong yang tiba-tiba itu, maka belut/lindu itupun menjadi marah, dan menyerang La Bolong, maka terjadilah pertarungan yang amat sengit antara keduanya. Pertarungan itu demikian dahsyatnya, sehingga seolah-olah terjadi gempa yang menggetarkan bumi. Penduduk pun menjadi, ketakutan. La-Bolong berhasil menyergap belut/lindu itu, keluar lobangnya. Lobang besar bekas tempat tinggal belut/lindu itu, setelah kosong dan runtuh, lalu menjadi danau, yang hinga kini disebut Danau Lindu.
Anjing Sawerigading La-Bolong melarikan belut itu kearah Utara dalam keadaan meronta-ronta, dan menjadikan lubang berupa saluran yang dialiri oleh air laut yang deras, air yang mengalir dengan deras itu, bagaikan air bah yang tumpah, menyebabkan keringnya air Kaili. Maka terbentuklah Lembah Palu dan terjelmalah Tana--Kaili.
Peristiwa alam yang amat dahsyat ini, membatalkan pertarungan kedua ayam yang telah dipersiapkan dengan cerrnat. Raja Ngilinayo dan Sawerigading sama-sama berikrar untuk hidup sebagai saudara kandung yang saling menghormati i untuk bekerja sama membimbing orang Kaili yang mendiarni Lembah Palu, bekas Teluk Kaili, yang telah menjadi daratan.
Air yang mengalir deras ke laut lepas Selat Makassar menghanyutkan perahu Sawerigading, yang akhirnya terdampar di Sombe. Ceritera rakyat rnenyebut, bahwa gunung yang menyerupai perahu di Sombe itu, adalah bekas perahu Sawerigading yang sekarang di Bulusakaya, yang berarti gunung yang berbentuk perahu. Alat-alat perlengkapan perahu lainnya, antara lain layar, terdampar di pantai sebelah Timur. Tempat itu kini bernama Bulumasomba, artinya gunung yang menyerupai layar.
Sebuah versi lain, mengenai ceritera persaudaraan antara Raja Ngilinayo dengan Sawerigading, menyebutkan bahwa pada menjelang akan diadakannya pertarungan ayam, di adakanlah pesta atau keramaian yang dikunjungi oleh sebahagian besar penduduk kerajaan Sigi. Ferangkat alat kesenian, bunyi-bunyian berupa gong, tambur dan seruling, didaratkan dari perahu Sawerigading, untuk meramaikan pesta kerajaan itu. Gong, tambur, dan genderang dipalu bertalu-talu, memeriahkan pesta itu, mengundang kera:iaian yang gegap gempita. Urang sakitpun yang tadinya terbaring lemah di pembaringan masing-masing, setelah mendan gar bunyi-bunyian itu. Merekapun menghadiri pesta keramaian itu. Penyembuhan dari penyakit, berkat mendan garkan bunyi-bunyian yang mengiringi nyanyian (t'embang), yang diperagakan dengan tari-tarian, dipercaya sebagai obat mujarab. Pengobatan dengan cara itu, disebut Balia, dari dua kata bali + ia artinya lawan ia. Maksudnya setan atau roh jahat yang membawa penyakit harus dilawan.
Puncak acara keramaian malarn itu, ialah peresmian atau pengukuhan sumpah setia persaudaraan antara raja Sigi Ngilinayo dengan Sawerigading. Segenap perangkat alat bunyi-bunyian, diserahkan oleh Sawerigading kepada saudaranya, yaitu Raja Sigi Ngilinayo. Seusai pesta Kerajaan itu, kembalilah Sawerigading dengan anak buahnya ke perahu. Setelah mereka tiba di perahu, mereka dikejutkan oleh adanya getaran bumi yang dahsyat disertai deru air yang bagaikan tautan keras. Dikatan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kareria pergelutan antara Labolong dengan belut/lindu, seperti diceriterakan didepari. Perahu Sawerigadirlg terlepas dari tambatannya, dan hanyut mengikuti arus air ke laut.lepas, Selat Makassar. Berkat lcetangkasar: awak perahu Sawerigading, menyelematkan perahun,da dari malapetaka. Mereka melepaskan diri dari Teluk Kaili yang sudah menjadi daratan, dan selamatlah Saweriading meneruskan perjalanannya kembali ke Tana-Bone Sulawesi-Selatan).
Sawerigading adalah tokoh legendaris dalam ceritera rakyat Tana Kaili. Tokoh itu dihubungkan dengan kedudukan Kerajaan Bone, sebagai kerajaan Bugis di Sulawesi-Selatan yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kai1i. Dapat diperkirakan bahwa hubungan-hubungan yang akrab dengan kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kaili, berlangsung dalam abad ke-17. Adapun tokoh lagendaris Sawerigading di Sulawesi Selatan tersebut dalaiu Epos La-Galigo, dipandang sebagai peletak dasar dan cikal bakal raja-raja Bugis, khususnya di Kerajaan Lucau, yang terletalc pada bahagiaii Utara Selat Bone. Zaman Sawerigading dalam Epos La-Galigo, diperkirakan berlaiigsung dalam abad IX dan X (M). Kedua keadaan itu dalam cerita rakyat Tana Kaili, yaitu tokoh iegendaris Sawerigading dan hubungan persahabatan dengan kerajaan Bone, dipadukan saja sebagai pe-ristiwa istimewa dalam suatu cerita rakyat. Hal seperti itu, adalah biasa dan menjadi karastrestik umum dari suatu cerita rakyat (Folk-Tale), untuk memperoleh semacam pengukuhan legitimasi bagi tokoh-tokoh yang tersangkut dalam peristiwa luar biasa 12). Mungkin sekalli dapat dibuktikan kebenaran ilmi.aluiya, melalui penelitian (arkeologi atau paleoantropologi), bahwa sekitar abad IX-X (M), Lembah Palu masih merupakan lautam sampai negeri Gangga dekat Danau Lindu. Setelah Laut Kaili menjadi daratan, yang membentuk Tana-Kai di Lembah Palu, maka terjadilah hubungan dangan kerajaan Bone dan Gowa yang menguasai perairan Selat Makassar. Ketika itu Kompeni Belanda (VOC) juga sudah mulai melakukan kegiatan intervensi terhadap kerajaan kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Peristiwa-peristiwa penting itu justeru terjadi dalam abad ke XVII. Sekitar abad itu , kerajaan Bone mengunggu kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan di baw pimpinan Aruppalakka, To-Erung malamppee' Gemme' n Ketika itu Kerajaan Bone melakukan hubungan baik m lalui daratan, maupun lautan ke bahagian Timur d Barat Nusantara, termasuk Sulawesi Tengah dan Utar Tana Kaili dan kerajaan Banawa amat banyak di sebabkan dalam Lontara Bugis-Makassar tentang hubungannya , politik dan persaudaraannya dengan negeri-negeri Bugis yang menguasai pelayaran Selat Makassar.
Pada dewasa ini, persebaran pemukiman To-Kaili propinsi Sulawesi Tengah, meliputi sebahagian terbes Kabupaten/Dati II Donggala, dan beberapa wilayah Kecamatan dalam Kabupaten/ Dati II Poso, Banggai d Buol Toli-Toli. Kelompok etnik Tiriombo, Tomini d Moutong yang mendiami pesisir sebelah Timur di Tel Tomini, tadinya masih dapat dipertajam identifikasinya yang berbeda dari kelompok etnik To-Kaili. Teta kini, dilihat dari perkembangan persebaran penerima unsur-unsur kebudayaan yang sama,: maka perbedaa perbedan itu menjadi sangat tipis. Malahan percampur rnelalui jalan kawin-mawin yang amat banyak, teruta dalam kalangan pemuka adat dan masyarakat Kaili dan g To-Tinombo, To-Tomini dan To-Moutong, perbedaan yang pernah mempertajam identifikasi etnik masing-masi kini sudah mencair.
Cacah jiwa orang Kaili yang tersebar luas dal Propinsi Sulawesi Tengah, diperkirakan 45 % dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah, yaitu kira-kira 4 sampai 5 ratus ribu jiwa. To-Kaili pada umumnya atau terbanyak bermukim di sepanjang pantai, baik di pesisir Barat, maupun dipesisir Timur. Oleh karena itu, maka cara hidup clan kebudayaan Kaili yang dominan, kelihatan lebih dekat kesamaannya kepada kebudayaan Bugis-Makassar (Sulawesi-Selatan), dan kebudayaan Melayu (Sumatera dan Malaka ).
Selain dari pada kelompok etnik Kaili, Pamona, Buol Toli-Toli, Banggai dan lain-lain, seperti telah disebut pada bahagiarr depan, masih terdapat lagi keiompok-kelompok etnik dalam jumlah warganya yang tidak , terlalu banyak, tetapi mereka dipandang' sebagai penduduk asli Sulawesi Tengah. Mereka itu kini disebut suku-suku terasirlg, seperti : Lauje, Tajio, Pendau, To-Lare,. Rarang Gonau, Loon , Sea-sea, Daya dan mungkin masih ada lagi lainnya yang belum di kenal. Kelompok-kelompok etnik itu yang jumlah warganya relatif kecil, mendiami lereng gunung secara terpencar-penca-r dalam hutan-hutan. Mereka rnenggunakan bahasa atau dialek tersendiri dalam kehidupan yang terisolasi itu. Secara umum dapat ditandai keadaan fisik mereka yang berbeda dalam dua golongan. Pada umumnya To-Lare (Orang 'gunung) yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Barat Lembah Palu, disebut juga Tolare-bulumpanau, memiliki warna kulit yang agak cerah. Sebaliknya To-Tare yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Timur Lembah Palu disebut juga To-Lare-Bulungpadake, memillki warna kulit gelap.
Kelompok- Kelompok Sub-etnik Kaili seperti yang disebut pada bahagian depan masing--masing rnemiliki kekhususan baik mengenai ceritera tentang asal usul, maupun dialek serta pernyataan kulturalnya, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :
1.Penduduk asli Lembah Palu. Di Lembah Palu dan sepanjang pantai teluk Palu bermukim To-Kaili, sebagai satu kelompok etnik di kawasan ini 14). Penduduk Lembah Palu, terdiri atas beberapa kelompok sub-etnik atau kelompok kaum, dengan dialekdialek bahasa masing-masing.
Pemukiman awal ke-empat kelompok kaum ini, mehurut petunjuk yang diketemukan sekarang, adalah sebagai berikut:
To-ri Palu, bermukim pada bagian Utara lembah, sepanjang dua sisi muara Sungai Palu.
To-Biromaru dan To-ri Sigi, bermukim di bagian Selatan To-ri Palu, pada sebelah kanan daerah aliran sungai Palu, dengan kekecualian bagian kecil sebelah Utara Wunu, di sana berdiam To-ri Dolo, bermukim di sebelah Selatan To-ri Palu, pada bagian ki-ri daerah aliran Sungai Palu. Di lereng-lereng gunung bagian Utara Lembah Palu juga sudah berdiam sejak dahulu kala penduduk yang disebut To-Lare (Orang gunung). Disamping To-Lare terdapat juga To-Petimpe, yang berdiam di lerenglereng gunung sebelah Utara lembah, terutama dalam wilayah ah Palolo. To-Petimpe secara etnik tidak banyak hubungannya dengan penduduk asli Lembah Palu. Menurut berbagai keterangan To-Petimpe itu, keturunan To-Balinggi dari Tana-Boa di Teluk Tomini, atau mungkin juga dari To-Pebato, satu kaur yang berdiam di muara sungai Puna.
Pada bagian yang agak jauh ke Selatan Lembah Palu, sekitar Gumbasa, Miu, Salcuri pada daerah aliran Sungai Palu, terdapat dua kelompok kaum yaitu To-Pakuli sekitar Gumbasa dan Miu, dan To-Sakuri sekitar Miu. Disana terletak negeri Bangga yang penduduknya berbahasa sama dengan To-Pakuli.
2.To-ri Palu dan To- Biromaru. Penduduk Lembah Palu, berasal dari pegunungan sekitar Lembah Palu itu juga. Ketika bermukim di Lerabah Palu, sejak awalaya-pun, mereka telah berkelompok l:e dalam tiga buah kaum, yaitu : To-ri Sigi, To-ri Dolo dan To--ri Palu.
Berbagai cerita rakyat yang samar-sarna diingat melaiui ceritera atau tutur o-ang tua-tua, bahwa ketiga kaum irri, acapkali saling memerangi antara satu sama lainnya. Karena begitul;ah mereka dalam bermukim di Lernbah Paiu, masing -masing memilih tempat yang secara alamiah terlindung dari upaya serangan-serangan terbuka dari pihak lawarrnya. Malahan ada kecenderungan mempertahanl sosialisasi mereka satu sama lainnya.
To-ri Palu yang rnendiami wilayah Palu, kabarnya berasal dari pegunungan sebelaii Timur. Di Tempat asal mereka, dipegunungan itu, terdapat satu tempat yang bernama Buluwatumpalu, disana bertumbuh banyak tanarnan barnbu yang dipergunakan dalam kehidupan. Untuk mengingat asal nama negeri Buluwaturnpalu yang berarti bambu kecil, maka tempat yang mereka pilih untuk bermukim, yaitu di muara sungai besar yang sekarang bernarna Sungai Palu, disebutnya dari kata itu, yaitu mPalu (kecil). Di mana letak tempat yang disebut Buluwatumpalu itu, diperkirakan di salah satu tempat di atas bukit Paneki sekarang, yang disebut Raranggonau.
Adapun To-Biromaru, diduga keras berasal dari leluhur yang sama dengan To-ri Palu, yang sama-sama menggunakan dialek Kaili-Ledo. Pemelcaran menjadi kaum sendiri itu, terjadi kemudian setelah pemisahan tempat pemukiman.
To-Biromaru mendiarRi tempat yang lebih kedalam di daerah lereng dalam lembah yang subur. Pemisahan menjadi dua kelompok kaum itu terjadi sebelum abad ke-XVII 17).
3.To-ri Sigi, To-ri Dolo.
Menurut catatan Valentijn (1724), To-ri Sigi dan To-ri Dolo diperkirakan sudah bermukim di Lembah Palu sejak ak'nir abad XVII atau pada permulaan abad XVIII. Kedua kelompok kaum ini, menggunakan dialek bahasa Kaili yang sama, yaitu dialek Ija. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berasal da,ri leluhur yang sama. Akan tetapi sejarah kehidupan mereka sejak awal, selalu diwarnai oleh permusuhan dan peperangan antara keduanya.
Dari mana asal kedua kelompok kaum ini pada mulanya sebelum bermuhim di Lembah Palu, terdapat beberapa keterangan. Salah satu cerita yang hampir sarna dengan keterangan Hissink, diterlukan dikalangan penduduk Sigi, sebagai berikut. Sebelum To-ri Sigi bermukini di Lernbah Palu, yaitu di Bora, Watunonju, Oloboju dan Sigi, leluhur merelca berrnukim di sele,lah utara Danau Lindu di lereng-lereng gunung, di terapat-tenlpat pemukiman yang disebut Leu, Silonga, Wowolau, Ue-hialaei dan Sigipulu.
Mengenai To-ri Dolo, menurut beberapa cerita rakyat, dikatakan berasal dari daerah pegunungan yang lebih ke Utara lagi letaknya dalam tempattempat pemukiman yang bernama Dolo, Maru dan Pompewajo. Dimana tempat-tempat itu terletak di lerenglereng gunung sekarang, tidak diperoleh petunjuk yang jelas dari penduduk. Tetapi nama-nama itu, masih ada mengingatnya. Kemungkinan besar, bekasbekas pemukiman To-ri Sigi terletak sekitar negeri Palolo sekarang, tempat-tempat pemukiman awal ToDolo, justru terletak sekitar negeri sekarang.
4.To-Pakuli; To-Pakuli; To-Bangga;To-Baluase; ToSibalaya; To-Sidondo adalah kelompok-lcelompok kaum dalam komunitas yang kecil-kecil. Mereka bermukim di sebelah Selatan wilayah ah pemukiman To-ri Sigi. Mereka menggunakan dialelc bahasa Kaili yang disebut Ado atau Edo. Dialek Ado amat dekat kepada dialek Ija yang dipergunakan oleh To-ri Sigi diperkirakan sebelum mereka bermukim di Lembah Palu, mereka berdiam di lereng-lereng pegunungan sebelah Timur dan Tenggara Lembah Palu.
5.To-Tawaili (To-Yayapi). Dalam iembah sebelah utara Napu hiduplah pada zaman dahulu sekelompok kaum yang menamakan diri To-Tawaeli atau To-Payapi. Karena berbagai gangguan dari kaum di sekitarnya lalu berpindah melewati sebelah Utara Danau Lindu, melintasi nege-ri Sigi dan akhirnya sampai ke Budong-Budong, di sebelah Selatan Donggala di pantai Selat Makassar. Sebagiaii lainnya menetap di Sausu, Dolago dan Parigi.
Pada dewasa ini, To-Tawaeli yang bermukim di wilayah ah Kecamatan Tawaeli yang terletak di sebelah Utara Kota Palu, dalam cerita rakyat yang sudah samar-samar dalam ingatan para penuturnya mengatakan bahwa To-Tawaeli berasal dari bagian Selatan pantai Selat Makassar.
6.To-Lindu, bermukim sekitar Danau Lindu. Mereka percaya dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lembah Palu. Para pemimpin adat Lindu atau keturunan mereka yang ada sekarang, selalu menyatakann diri berasal dari Sigi di Lembah Palu. Keterangan seperti juga dijumpai pada umumnya dalam kalangan penduduk lereng-lereng pegunungan sebelah Selatan di lembah Palu, bahwa nenek moyang mereka berasal dari Sigi.
7.To-Banggakoro. yang mendiami daerah pegunungan jauh di sebelah barat Kulawi dapat dikatakan secara kebudayaan lebih banyak bersentuhan dengan kebudayaan Mamuju di pantai Barat dan kebudayaan Lembah Palu di sebelah Utara. Asal mula penduduk terdahulu To-Banggakoro tak dapat ditemukan dalam ceritacerita rakyat. Akan tetapi besar sekali persamaan kelompok kaum ini (To-Banggakoro) dengan penduduk Bangga yang berasal dari bagian Selatan Lembah Palu.
8.To-Tamungkolowi; To-Tabaku, berdiam di atas pegunungan sebelah Barat negeri Kulawi. Tidak ditemukan legenda ataupun ceritera-ceritera rakyat yang memperkatakan tentang asal usul mereka. Akan tetapi berbagai ungkapan dan benda-benda kebudayaan sub-etnik'ini, seperti sebutan Sou-eo, dan pakaian atau alat-alat perhiasan wanita dan tata rambutnya,sama dengan yang pada umumnya terdapat di Lembah Palu. Dari pengamatan-pengamatan yang lebih dekat dan lama dapat dikatakan bahwa To-Tamungkolowi dan To-Tabaku, juga pada awalnya berasal da-ri bahagian Selatan Lembah Palu.
9.To-Kulawi, yang berdiam di sebelah Selatan Danau Lindu, menurut legenda,mereka berasal dari Bora dan Sigi di Lembah Palu. Menurut ceritera rakyat, bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang bangsawan dari Bora bersarna pengikutnya berburu ke hutan-hutan dan gunung Momi di daerah Kulawi yang masih lengang. Para pemburu berteduh dibawah pohon yang amat rimbun.dan lebat daunnya. Mereka namakan pohon itu, pohon Kulawi.Jenis pohon itu sekarang tidak ditemukan lagi.
10.To-Sausu; To-Balinggi; To-Dolago, diantara Sungai Tambarana dengan Parigi di Pantai Timur SulawesiTengah, terdapatlah negeri-negeri Sausu, Tana -Boa dan Dolago. Disitulah kelompok-kelompok kaum yang menyebutkan diri To-Balinggi dan To-Sausu berdiam. Menurut ceritera rakyat, baik To-Sausu maupun ToBalinggi berasal dari keturunan yang sama yang disebut To-Lopontato yang bermukim di lereng-lereng gunung. Kaum ini amat erat hubungan kebudayaanya dengan To-Parigi. Adapun To-Dolago menurut ceritera rakyat itu, juga adalah dari suatu keturunan dengan kedua kaum lainya, yaitu To-Sausu dan To-Dolago. Tetapi kemudian hidup memisahkan diri karena lingkungan alam, tetapi tetap merasa mempunyai hubungan kekeluargaa<< dengan To-Parigi, juga dengan To-Sigi.
11.To-Parigi. Negeri Parigi terletalc di sebelah Utara Sausu di Teluk Tomini. Pada umtlimnya penduduk negeri Parigi yang disebut To-Parigi percaya bahwa nenek rr,oyang rnereka, berasal dari Lembah Palu. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat Parigi selanjutnya, banyak juga terjadi kontak dengan kelompok etnik Panona dari Wilayah ah Poso, sehingga beberapa pengamat menduga, bahwa orang Parigi dapat digolongkan ke dalam kelompok etnik Pamona-Poso.18).
Dapat diduga ballwa oi-ar,g Kaili yang sekarang me diami Lembah Palu, berasal dari arah Tenggara Utara Barat Daya, yaitu dari daerah sebelah Uta Danau Poso. Ada yang bergerak kearah Baiat dan ke a-r pantai Teluk Tomini, dan ke aril Selatan dan Tim Lembah Palu hingga pantai Seiat Makassar.
BAB III
SEKELUMIT SEJARAH KEBUDAYAAN KAILI
Tempat awal pemukiman sesuatu kaum yang pada hakekatnya terpisah-pisah, malahan terisolasi dari tempat pemukiman kaum lainnya, biasa disebut Ngapa. Da-ri Ngapa itulah dimulai peradaban sesuatu kaum, yang lambat laun berturnbuh jumlah warganya dan memekari:an tempat-tempat pemukiman baru itu. Tempat-tempat pemukiman baru disekitar Ngapa itu, selaku perluasan pemukiman kaum perluasan kaum seasal biasanya disebut Boya atau Soki.
Tempat penukiman lain yang terbentuk oleh adanya lapangan pekerjaan tertentu seperti komunitas (persekutuan) tani atau nelayan dinamakan Kinta. apabila pada suatu waktu perkembangan Ngapa menjadi sudah cukup luasnya ole'n dukungan sejumlah Boya, Kinta dan Soki, maka terbentuklah satu wilayah a territorial dengan susunan kekuasaan yang ditaati- oleh penduduk. Terbentuklah apa yang dinamakan secara umum kerajaan lokal, yang dapat disebut "Kagaukang" atau "Kagau".
Menurut berbagai sumber, 1) sebelum terjadinya struktur kerajaan yang disusun dalam perangkat kekuasaan pejabat-pejabat secara hierarchis, sesuatu wilayah ah pemukiman kaum yaitu Ngapa atau sejenisnya dikuasai atau dipimpin oleh orang yang disebut '1'0Malanggai. Ia adalah pemimpin yang dipandang perkasa, seorang jantan yang mengatasi jantan-jantan lainnya. la-pun dapat disebut "penakluk" atas kaum yang bermukim disekitarnya. Dasar kepemimpinannya adalah keberanian, kepeloporan, untuk mengungguli orang-orang atau kaum yang dipimpinnya.
BAB IV
MODAL PERSONALITY ORANG KAILI
Konsep MODAL PERSONALITY, atau kalau hendak diterjemahkan secara sederhana, dapat disebut PERASAAN KKPKIBADIAN. Penguraian tentang modal-personality, pertama-tama akan menghadapi secara serius persoalan metodologis, untuk penerapannya. Kita akan menghadapi suatu masyarakat dengan segala persoalannya yang amat rumit. Wilayah ah masyarakat itu yang seringkali amat luas, aneka ragam pranata dan lembaga sosial; aneka macam lingkungan alam tisik darn kebudayaan; aneka macam iklim yang dibawa oleh aneka macam keadaan lingkungan, seperti gunung, lembah dan dataran yang membentang luas, semua itu secara metodologis harus diperhitungkan dalam penelitian atau pengamatan yang diperlukan, untuk melukis kan PERASAAN KEPRIBADIAN itu. Oleh karena itu, suatu perkiraan umum yang dipandang representatit atau secara wajar mewakili segenap keadaan yang sesungguhnya amat diperlukan. Tentu saja sangat di perlukan adanya sampling secara statistik dari berbagai daerah kesatuan hidup, atau kelompok sosial, jenis-jenis lapangan pekerjaan, tingkat usaha dan lain-lain, untuk mendapatkan gambaran yang sungguh-sungguh dapat memuaskan, sebagai gambaran umum tentang perasaan kepribadian sesuatu kaum, seperti yang akan dilukiskan disini, yaitu YEKASAAN KEPRIBADIAN ORANG KAILI.
Dalam pengertian umum, tulisan ini hendak mencota melukiskan ciri-ciri kepribadian To-Kaili, melalui perasaan kepribadian yang ditampilkan dalam berbagai tata kelakuan dalam kehidupan yang membudaya atau bernilai budaya. la secara aktual dianut atau dihargai sebagai perilaku sosial dan secara umum dilakukan dalam kehidupan. Deilgan kata lain, apa yang dilakukan atau diperbuat oleh orang Kaili, sehingga ia merasa diri sebagai To-Kaili.
Sesuatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan yang bermakna ke-Kaili-an, karena seseorang (Kaili) yang melakukannya merasa diri orang Kaili, ('To-Kaili). To-Kaili lainnya melihat ia melakukari perbuatan itu, segera mengetahui bahwa ia adalah To-Kaili. Maka antara yang melakukan dengan yang mengamati kelakuan itu tumbuh tali perhubungan yang alafniah sebagai hubungan keakraban (familiar). Karena apa yang diamati itu seolah-olah adalah dirinya sendiri. Ia akrab dengan perilaku atau tingkah laku seperti yang dilakukan dalam kebudayaan Kaili.
Patokan-patokan umum yang dapat dipergunakan dalam menjaring perasaan-perasaan kepribadian itu, adalah biasanya perbuatan-perbuatan atau perilaku yang amat lekat pada kehidupan emosional atau yang menyentuh perasaan-perasaan terdalam, seperti pada perasaan hidup :
1.Kekerabatan dan kenasyarakatan,
2.Keagamaan dan kepercayaan,
3.Bahasa, kesusasteraan dan kesenian pada umumnya.
Pertemuan-pertemuan, berupa pesta-pesta dalam keluaga, membuka kesempatan bagi para remaja untuk saling bertemu dan berkenalan, melalui perkenalan di pesta-pesta itu, terjalinlah hubungan-hubungan yang akan mengantarkan ke(-'Iua remaja yang saling mencintai itu, untuk memasuki tingkat hubunban formal menuju perkawinan/pernikahan.
UPACARA PEMINANGAN : Upacara-upacara pernikahan, lebih banyak memperlihatkan segi-segi formal yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Hal-hal yang formal itu dilakukan untuk saling memberikan kesan tentang adanya kesungguhan kedua belah pihak untuk membangun pertalian keluarga besar.
Rangkaian upacara menjelang hari pernikahan, merupakan formalitas yang kelihatannya amat cermat dijalankan. Orang menamakannya upacara adat, untuk menjaga harmoni dalam kehidupan. Menurut ceritera, adapun NOTATE DALA (upacara manbuka jalan) dilakukan, untuk menjaga agar tidak terjadi penolakan pinangan, atau gadis itu telah ada yang meminangnya lebih dahulu. Kalau terjadi yang demikian, dahulu kala dipandang rnembawa aib bagi keluarga laki-laki.
Dalam upacara peminangan, berbagai benda yang bermakna simbolik diantarkan oleh pihak laki-laki yang diberikan oleh pihak pererrrpuan, antara lain sebagai berikut: SP.MPULOIGI (perbiasan emas perak buat perernpuan). SABALE KAMAGI (buah kalung emas).
Berbagai upacara adat dalam pelaksanaan acara perkawinan seperti tersebut di atas dilakukan dengan sedapat mungkin menampilkan idan titas keluarga yang menjadi penyelenggranya. Upacara itu menunjukkan kedudukan keluarga itu dalan masyarakat, sesuai nilai dan norma yang berlaku. Pada upacara itu ditampilkan ke
Nama saya Abigael Mitaart, lahir di Pulau Bacan, Maluku Utara, 30 Maret 1949, dari pasangan Efraim Mitaart dan Yohana Diadon. Latar belakang agama keluarga kami adalah Kristen Protestan. Ketika beragama Kristen Protestan, saya sama sekali tidak pernah membayangkan untuk memilih agama Islam sebagai iman kepercayaan saya. Hal ini dapat dilihat dari situasi keluarga kami yang sangat teguh pendiriannya pada keimanan Kristus.
Bagi saya, saat itu tidak mudah untuk hidup rukun berdampingan bersama umat Islam, karena sejak masa kanak-kanak telah ditanamkan oleh keluarga agar menganggap setiap orang Islam sebagai musuh yang wajib diperangi. Bahkan kalau perlu, seorang bayi Kristen diberikan pelajaran bagaimana caranya membuang ludah ke wajah seorang muslim. Hal ini mereka lakukan sebagai perwujudan dari rasa kebencian kepada umat Islam. Disanalah, saya tumbuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang sangat tidak bersahabat dengan warga muslim.
Tentu saya tidak pernah absen pergi ke gereja setiap hari Minggu. Bahkan, saya berperan dalam setiap Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Misalnya, saya selalu diminta tampil di berbagai kelompok paduan suara untuk pelayanan lagu-lagu rohani di gereja. Selain itu, saya kerap mengikuti kegiatan ?Aksi Natal? yang diselenggarakan oleh gereja dalam rangka pelebaran sayap tugas-tugas misionaris (kristenisasi).
TERTARIK PADA ISLAM
Ihwal ketertarikan saya pada agama Islam berawal dari rasa kekecewaan kepada ajaran-ajaran Kristen dan isi Alkitab yang hanya berisikan slogan-slogan. Bahkan, menurut saya, apabila para pendeta menyampaikan khotbah diatas mimbar, mereka lebih terkesan seperti seorang penjual obat murahan. Ibarat kata pepatah, ? tong kosong nyaring bunyinya.?
Sekalipun saya sudah menekuni pasal demi pasal, ayat demi ayat dalam Alkitab, tetapi tetap saja saya sulit memahami maksud yang terkandung mengenai isi Alkitab. Misalnya, tertulis pada Markus 15:34, ?Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku??
Lalu, siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Bukankah ia adalah paribadi (zat) Allah yang menjelma sebagai manusia? Lalu, mengapa ia (Yesus) berseru dengan suara nyaring dan mengatakan, ?Eli, Eli,..lama sabakhtani? ? (Tuhanku,..Tuhanku,.. mengapa Engkau tinggalkan aku?)
Akhirnya saya yakin bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Walaupun sebelumnya iman kepada Yesus Kristus sangat berarti dalam kehidupan saya. Apalagi, ketika itu didukung dengan ayat-ayat dalam Alkitab, seperti tertulis,?Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia (Yesus Kristus). Sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan.? Kisah Para Rasul 4:12
Kemudian dilanjutkan lagi dengan Yohanes 14:6, ?Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui Aku (Yesus).?
Setelah membaca ayat ini, kemudian saya mencoba membanding-bandingkan dengan satu ayat yang tertulis dalam QS. 3:19, ?Sesungguhnya agama (yang diridhai) pada sisi Allah ialah Islam.?
Entah mengapa, saya merasakan pikiran saya beru-bah, mungkin ini suatu keajaiban yang luar biasa terjadi dalam diri saya, karena selesai membaca ayat al-Qur?an tersebut, saya mulai merasa yakin bahwa ayat yang tertulis dalam QS. 3:19 itu bukanlah ?ayat rekayasa? dari Nabi Muhammad, tetapi ayat tersebut sesungguhnya adalah firman Allah yang hidup dan kehadiran agama Islam langsung mendapat ridha dari Allah SWT.
Betapa sulitnya seorang Kristen seperti saya bisa memeluk agama Islam, tetapi saya yakin dengan keputusan untuk masuk agama Islam, karena saya berkesimpulan apabila seorang beragama Kristen kemudian memilih agama Islam, selain karena mendapat hidayah, ia juga termasuk umat pilihan Allah SWT. Alhamdulillah, singkat cerita pada tanggal 22 Desember 1973, disebuah pulau terpencil bernama Pulau Moti di wilayah Makian, Maluku Utara dengan disaksikan warga muslim setempat, saya mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat. Tanpa terasa air mata kemenangan berlinang, sehingga suasana menjadi hening sejenak, keharuan amat terasa saat peristiwa bersejarah dalam hidup saya itu berlangsung. Usai mengucap dua kalimat syahadat, nama saya segera saya ganti menjadi Chadidjah Mitaart Zachawerus.
Keputusan saya untuk memilih Islam harus saya bayar dengan terusirnya saya dari lingkungan rumah, pengusiran ini tidak menggoyahkan iman dan Islam saya, karena saya yakin akan kasih sayang Allah SWT, senantiasa tetap memelihara saya dalam lindungan-Nya.
?Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah tidak menolong kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin berserah diri.? QS. 3:160
Alhamdulillah, pada bulan Juni 1996, saya bersama suami, Sulaiman Zachawerus, menunaikan rukun Islam kelima, pergi haji ke Baitullah.
5 KOMENTAR TERAKHIR
gabriel omar-- tanggal : 2009-02-09
To : Willy
Sebaiknya anda membaca sejarah turunnya alquran baru berkomentar !!!!! mana mungkin kitab alquran diturunkan dari langit secara utuhh? anda saja yang bodoh mau menerima pemikiran seperti itu,heheh ehehe.
Alquran = firman allah
Alkitab = kitab saksi sejarah
Silahkan anda semua pilih mau percaya kitab yang dari allah atau kitab sejarah !!!!
wassalam
yanuar-- tanggal : 2009-02-09
to :willy
lihatlah kedalam alkitab memangnya itu wahyu Tuhan?, kalau dari Tuhan emangnya Yesus Tuhan?, kalau Yesus Tuhan emangnya Tuhan bisa mati? kalau bisa mati kenapa Yesus di sebut Tuhan dan jika Yesus bukan Tuhan berarti alkitab bukan Wahyu dari Tuhan donk???
yang dimaksud Turun langsung dari langit itu begini: Tuhan memgirimksn langsung Tulisan dan kalimat-Nya ke nabi Muhammad terus dari Nabi Muhammad di bacakan lagi Kalimatullah tersebut jadilah Al-Quran, masa begitu saja bingung???
makanya jadi orang yang di anugrahi iman dan akal pakailah keduanya, jangan mengimani alkitab yang sudah jelas2 secara akal salah masih di imani kan aneh jadinya!
willy-- tanggal : 2009-02-07
Salah satu bukti Ke Allahan Kristus adalah dengan begitu banyaknya orang yang terus menerus mencari tahu segala sesuatu tentang Dia,namun sialnya mereka tak pernah puas dan tak pernah mengerti.
Anda boleh mengakui bahwa Al Qur an adalh kitab suci yang langsung dari Allah.
Tapi saya meragukan hal tersebut. Dalam sejarah tidak pernah ada tulisan yang langsung jatuh dari Langit.
Alkitab merupakan suatu saksi sejarah karena didalamnya tertuliskan segala sesuatu yang terjadi pada zaman dulu, zaman Para Nabi-nabi dan bukan diturunkan dari langit. Kebohongan terbesar bila mengatakan tulisan diturunkan dari Langit, itu tidak masuk akal.
Yudas_Eskareot-- tanggal : 18/01/2009
YESUS....?BAGAIMANA MURID YESUS MEMAHAMI PERKATAAN DAN FIRMAN?PAHAMKAH MEREKA MANA PERKATAAN MANA BUKAN MANA FIRMAN MANA BUKAN?
JANGAN-JANGAN PARA MURID JESUS INI MENYAMPAIKAN FIRMAN TUHAN ASAL-ASALAN YANG FIRMAN DICAMPUR ADUKAN DENGAN PERKATAAN CKCKCKCKC BISA BAHAYA ITU!!!
Admin :Om Yudas, tolong gunakan huruf normal aja ya.. jangan kapital semua... Syukron...
gabriel omar-- tanggal : 06/01/2009
TO : rocky -- asal : bogor
Ya, nabi Isa akan menjadi hakim yang adil (menurut versi islam)
Maksudnya, ketika turun ke dunia pada Hari Kiamat nanti, Isa akan memberikan kesaksian kepada manusia tentang apa yang mereka perselisihkan di antara mereka sepeninggalnya. Pada saat itu beliau akan memberikan kesaksian bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam (Qs. Aali 'Imraan 19).
Sedangkan menurut alkitab matius 19 : 28 dia akan menjadi hakim hanya untuk kedua belas suku israel.,,,,,,,,(karena memang dia di utus untuk umat israel, tidak kepada seluruh umat manusia)
Jadi hakim bagi seluruh umat manusia hanya allah !!!!!
Siapa bilang ajaran yesus sudah lengkap coba anda baca baca lagi alkitab ? saya melihat bahwa ajaran yesus itu tidak lengkap, dan injil itu banyak bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya ( yang menunjukan ajaran tersebut sebagian palsu /terdistorsi ) dan nabi Muhamad meluruskannya (melengkapinya) coba anda baca alquran semua tuntunan hidup di dunia ini tertulis secara lengkap,,??..dan untuk mengantisipasi ajaran kristen yang tidak bisa di terapkan, maka orang orang membuat hukum ekonomi, hukum perdata , hukum pidana untuk melengkapi injil yang tidak bisa di terapkan di dalam dunia ini yang memiliki permasalahan kompleks
wassalam
Bagi saya, saat itu tidak mudah untuk hidup rukun berdampingan bersama umat Islam, karena sejak masa kanak-kanak telah ditanamkan oleh keluarga agar menganggap setiap orang Islam sebagai musuh yang wajib diperangi. Bahkan kalau perlu, seorang bayi Kristen diberikan pelajaran bagaimana caranya membuang ludah ke wajah seorang muslim. Hal ini mereka lakukan sebagai perwujudan dari rasa kebencian kepada umat Islam. Disanalah, saya tumbuh dalam lingkungan keluarga Kristen yang sangat tidak bersahabat dengan warga muslim.
Tentu saya tidak pernah absen pergi ke gereja setiap hari Minggu. Bahkan, saya berperan dalam setiap Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR). Misalnya, saya selalu diminta tampil di berbagai kelompok paduan suara untuk pelayanan lagu-lagu rohani di gereja. Selain itu, saya kerap mengikuti kegiatan ?Aksi Natal? yang diselenggarakan oleh gereja dalam rangka pelebaran sayap tugas-tugas misionaris (kristenisasi).
TERTARIK PADA ISLAM
Ihwal ketertarikan saya pada agama Islam berawal dari rasa kekecewaan kepada ajaran-ajaran Kristen dan isi Alkitab yang hanya berisikan slogan-slogan. Bahkan, menurut saya, apabila para pendeta menyampaikan khotbah diatas mimbar, mereka lebih terkesan seperti seorang penjual obat murahan. Ibarat kata pepatah, ? tong kosong nyaring bunyinya.?
Sekalipun saya sudah menekuni pasal demi pasal, ayat demi ayat dalam Alkitab, tetapi tetap saja saya sulit memahami maksud yang terkandung mengenai isi Alkitab. Misalnya, tertulis pada Markus 15:34, ?Dan pada jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eloi, Eloi, lama sabakhtani?", yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku??
Lalu, siapakah Yesus Kristus sesungguhnya? Bukankah ia adalah paribadi (zat) Allah yang menjelma sebagai manusia? Lalu, mengapa ia (Yesus) berseru dengan suara nyaring dan mengatakan, ?Eli, Eli,..lama sabakhtani? ? (Tuhanku,..Tuhanku,.. mengapa Engkau tinggalkan aku?)
Akhirnya saya yakin bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan. Walaupun sebelumnya iman kepada Yesus Kristus sangat berarti dalam kehidupan saya. Apalagi, ketika itu didukung dengan ayat-ayat dalam Alkitab, seperti tertulis,?Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia (Yesus Kristus). Sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan.? Kisah Para Rasul 4:12
Kemudian dilanjutkan lagi dengan Yohanes 14:6, ?Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui Aku (Yesus).?
Setelah membaca ayat ini, kemudian saya mencoba membanding-bandingkan dengan satu ayat yang tertulis dalam QS. 3:19, ?Sesungguhnya agama (yang diridhai) pada sisi Allah ialah Islam.?
Entah mengapa, saya merasakan pikiran saya beru-bah, mungkin ini suatu keajaiban yang luar biasa terjadi dalam diri saya, karena selesai membaca ayat al-Qur?an tersebut, saya mulai merasa yakin bahwa ayat yang tertulis dalam QS. 3:19 itu bukanlah ?ayat rekayasa? dari Nabi Muhammad, tetapi ayat tersebut sesungguhnya adalah firman Allah yang hidup dan kehadiran agama Islam langsung mendapat ridha dari Allah SWT.
Betapa sulitnya seorang Kristen seperti saya bisa memeluk agama Islam, tetapi saya yakin dengan keputusan untuk masuk agama Islam, karena saya berkesimpulan apabila seorang beragama Kristen kemudian memilih agama Islam, selain karena mendapat hidayah, ia juga termasuk umat pilihan Allah SWT. Alhamdulillah, singkat cerita pada tanggal 22 Desember 1973, disebuah pulau terpencil bernama Pulau Moti di wilayah Makian, Maluku Utara dengan disaksikan warga muslim setempat, saya mengucapkan ikrar dua kalimat syahadat. Tanpa terasa air mata kemenangan berlinang, sehingga suasana menjadi hening sejenak, keharuan amat terasa saat peristiwa bersejarah dalam hidup saya itu berlangsung. Usai mengucap dua kalimat syahadat, nama saya segera saya ganti menjadi Chadidjah Mitaart Zachawerus.
Keputusan saya untuk memilih Islam harus saya bayar dengan terusirnya saya dari lingkungan rumah, pengusiran ini tidak menggoyahkan iman dan Islam saya, karena saya yakin akan kasih sayang Allah SWT, senantiasa tetap memelihara saya dalam lindungan-Nya.
?Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah tidak menolong kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin berserah diri.? QS. 3:160
Alhamdulillah, pada bulan Juni 1996, saya bersama suami, Sulaiman Zachawerus, menunaikan rukun Islam kelima, pergi haji ke Baitullah.
5 KOMENTAR TERAKHIR
gabriel omar-- tanggal : 2009-02-09
To : Willy
Sebaiknya anda membaca sejarah turunnya alquran baru berkomentar !!!!! mana mungkin kitab alquran diturunkan dari langit secara utuhh? anda saja yang bodoh mau menerima pemikiran seperti itu,heheh ehehe.
Alquran = firman allah
Alkitab = kitab saksi sejarah
Silahkan anda semua pilih mau percaya kitab yang dari allah atau kitab sejarah !!!!
wassalam
yanuar-- tanggal : 2009-02-09
to :willy
lihatlah kedalam alkitab memangnya itu wahyu Tuhan?, kalau dari Tuhan emangnya Yesus Tuhan?, kalau Yesus Tuhan emangnya Tuhan bisa mati? kalau bisa mati kenapa Yesus di sebut Tuhan dan jika Yesus bukan Tuhan berarti alkitab bukan Wahyu dari Tuhan donk???
yang dimaksud Turun langsung dari langit itu begini: Tuhan memgirimksn langsung Tulisan dan kalimat-Nya ke nabi Muhammad terus dari Nabi Muhammad di bacakan lagi Kalimatullah tersebut jadilah Al-Quran, masa begitu saja bingung???
makanya jadi orang yang di anugrahi iman dan akal pakailah keduanya, jangan mengimani alkitab yang sudah jelas2 secara akal salah masih di imani kan aneh jadinya!
willy-- tanggal : 2009-02-07
Salah satu bukti Ke Allahan Kristus adalah dengan begitu banyaknya orang yang terus menerus mencari tahu segala sesuatu tentang Dia,namun sialnya mereka tak pernah puas dan tak pernah mengerti.
Anda boleh mengakui bahwa Al Qur an adalh kitab suci yang langsung dari Allah.
Tapi saya meragukan hal tersebut. Dalam sejarah tidak pernah ada tulisan yang langsung jatuh dari Langit.
Alkitab merupakan suatu saksi sejarah karena didalamnya tertuliskan segala sesuatu yang terjadi pada zaman dulu, zaman Para Nabi-nabi dan bukan diturunkan dari langit. Kebohongan terbesar bila mengatakan tulisan diturunkan dari Langit, itu tidak masuk akal.
Yudas_Eskareot-- tanggal : 18/01/2009
YESUS....?BAGAIMANA MURID YESUS MEMAHAMI PERKATAAN DAN FIRMAN?PAHAMKAH MEREKA MANA PERKATAAN MANA BUKAN MANA FIRMAN MANA BUKAN?
JANGAN-JANGAN PARA MURID JESUS INI MENYAMPAIKAN FIRMAN TUHAN ASAL-ASALAN YANG FIRMAN DICAMPUR ADUKAN DENGAN PERKATAAN CKCKCKCKC BISA BAHAYA ITU!!!
Admin :Om Yudas, tolong gunakan huruf normal aja ya.. jangan kapital semua... Syukron...
gabriel omar-- tanggal : 06/01/2009
TO : rocky -- asal : bogor
Ya, nabi Isa akan menjadi hakim yang adil (menurut versi islam)
Maksudnya, ketika turun ke dunia pada Hari Kiamat nanti, Isa akan memberikan kesaksian kepada manusia tentang apa yang mereka perselisihkan di antara mereka sepeninggalnya. Pada saat itu beliau akan memberikan kesaksian bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam (Qs. Aali 'Imraan 19).
Sedangkan menurut alkitab matius 19 : 28 dia akan menjadi hakim hanya untuk kedua belas suku israel.,,,,,,,,(karena memang dia di utus untuk umat israel, tidak kepada seluruh umat manusia)
Jadi hakim bagi seluruh umat manusia hanya allah !!!!!
Siapa bilang ajaran yesus sudah lengkap coba anda baca baca lagi alkitab ? saya melihat bahwa ajaran yesus itu tidak lengkap, dan injil itu banyak bertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya ( yang menunjukan ajaran tersebut sebagian palsu /terdistorsi ) dan nabi Muhamad meluruskannya (melengkapinya) coba anda baca alquran semua tuntunan hidup di dunia ini tertulis secara lengkap,,??..dan untuk mengantisipasi ajaran kristen yang tidak bisa di terapkan, maka orang orang membuat hukum ekonomi, hukum perdata , hukum pidana untuk melengkapi injil yang tidak bisa di terapkan di dalam dunia ini yang memiliki permasalahan kompleks
wassalam
Langganan:
Komentar (Atom)