BAB I
PENDAHULUAN
Luas Wilayah Dati I Sulawesi Tengah, 63.689.25 km2 atau 6.368,925 Ha.
Sulawesi Tengah pada umumnya di pengaruhi oleh due musim secara tetap yaitu musim Barat yang keying dan musim Timur yang membawa banyak uap air. Musirn .Barat yang keying itu berlaku dari bulan Oktober sampai dengan April yang di tandai dengan kurangnya turun hujan, sedangkan musim Timur yang banyak membawa uap air, yakni pada bulan April sampai dengan Oktober yang ditandai dengan banyaknya turun hujan. Curah hujan di Sulawesi Tengah setahunnya bervariasi antara 800-3000 mm. Kecuali Lembah Palu yang amat kurang mendapat curah hujan, maka variasinya bergerak antara 400-1000 mm saja setahun.
Penduduk yang baru berjumlah satu setengah juta jiwa yang mendiami wilayah ah propinsi yang amat luas itu, dapat dikatakan tidak mudah dapat dengan cepat mengembangkan diri mengelola potensi alam yang besar itu. Namun demikian, keadaan yang dapat dicapai oleh masyarakat Sulawesi Tengah dalam kehidupan kebudayaannya sejak berabad yang lalu, dapat di katakan tidak' terlampau terisolasi dari perkembangan unum kebudayaan yang terdapat di daerah lain di kepulauan Nusantara ini. Tentu terdapat berbagai faktor yang turut mengambil bahagian dalam perpbentukan kebudayaan penduduk Sulawesi Tengah seperti yang dijumpai sekarang.
Faktor-faktor tersebut antara lain :
1.Gerak perpindahan (migrasi) penduduk pada masa prasejarah yang masuk secara bertahap ke Sulawesi Tengah.
2.Persebaran agama Islam dan Kristen di kalangan penduduk Sulawesi Tengah .
3.Pengaruh dan peranan pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat
Beberapa sarjana dalam laporan penelitian mereka telah mencoba melakukan rekonstruksi asal mula persebaran penduduk, serta pertumbuhan kebudayaan yang mereka miliki. Para penulis masa lampau yang amat terkenal seperti Albert C. Kruijt, N. Adriani dan R. W. Kaudren 1).
Rekonstruksi itu didasarkan pada hasil penelitian dan perbandingan dari benda-benda peninggalan praSejarah, bahasa dan mite, serta lagenda penduduk.yang tersebar diberbagai tempat pemukiman yang luas tersebar di wilayah ah ini. Menurut Albert C. Kruijt, daerah yang didiami penduduk Toraja-Sulawesi Tengah itu pada mulanya, lebih dahulu didiami oleh suatu kelompok penduduk yang belum jelas diketahui indan titasnya. Akan tetapi Kleiweg de Zwaan, masih dapat menemukan sisa-sisa dari penduduk Loinang yang berlokasi di Jazirah Timur Sulawesi Tengah.
Dari sini penduduk pembuat tembikar itu menuju ke arah .Utara, ke Daerah Poso Sulawesi Tengah, terus ke daerah Barat, yakni ke daerah Pegunungan Lore, hingga ke daerah aliran Sungai Koro. Dari sana arahnya, kemudian membelok kembali ke Selatan dan berhenti di suatu tempat yang bernama Waebunta, suatu tempat di daerah Galumpang yang kini termasuk wilayah ah Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan.
Migran Pottenbekkers ini menurut Kruyt ada juga yang datangnya dari arah laut (Selatan Makassar ), memasuki daerah Palu dan menyebar ke Lembah Palu. Penduduk pendatang baru itu, membawa anasir kebudayaan baru ke dalam kehidupan penduduk pribumi Lembah Palu, dalam lapangan sosial ekonomi dan relegi, antara lain sebagai berikut :
1.Dalam lapangan ekonomi diperkenalkan teknik pertanian berpengairan.
2.Dalam lapangan relegi disumbangkan satu sistem yang mengenal struktur dewa-dewa yang bertingkattingkat. Disamping itu juga diperkenalkan upacaraupacara keagarnaan yang rumit.
3.Dalam lapangan kehidupan sosial diperkenalkan jumlah peraturan baru, termasuk innovasi dari suatu lapisan sosial baru, yakni lapisan bangsawan, yang berada di atas lapisan sosial yang telah ada lebih dahulu berlaku dalam masyarakat, yaitu lapisan budak dan merdeka.
Eksistensi lapisan sosial bangsawan, sebagai lapisan baru ini terikat pada mite/legenda Sacaerigading dan Manuru Lasaeo. Unsur-unsur kebudayaan baru yang datang bersama orangorang pendatang baru itu, menurut Kruyt diperkirakan berasal dari unsur-unsur kebudayaan Hindu 'Jawa, yang berasal dari Pulau Jawa. Tentang mite/legenda Sawerigading yang terdapat dalam epos Galigo sebagai tokoh orang Bugis di Sulawesi Selatan, diduga persebarannya sebagai tokoh legendaris di Sulawesi Tengah meliputi daerah yang amat luas dari pantai Barat di Selat Makassar, sampai ke Luwuk Banggai di Teluk Tolo.
Selain terjadi migrasi yang berasal dari luar Sulawesi, sepanjang kehidupan penduduk Sulawesi Tengah, terjadi pula beberapa migrasi lokal. Kaudern membahas mengenai migrasi yang berlangsung di Sulawesi Tengah dalam bukunya menyatakan bahwa perpindahan penduduk di daerah ini terjadi karena berbagai sebab, seperti bencana alam, epidemi penyakit dan adat berperang di antara desa-desa. 2) Perang-perang yang amat sering terjadi itu, bertalian erat dengan adat pen,gayauan mereka. Suasana peperangan itu mengakibatkan penduduk desa acapkali mengungsi lebih jauh ke daerah pedalaman yang sukar dijangkau oleh musuhnya. Sebagai akibat lebih jauh dari adat peperangan ini, timbullah lembaga yang berasal dari tawanan perang, pada beberapa kolompok kaum yang besar di Sulawesi Tengah. Juga punahnya sesuatu kaum tertentu, adalah sebagai, akibat adat peperangan itu, seperti yang diambil oleh kepunahan kelompok kaum To Pajapi.
Pemukiman penduduk sebagian besar terpusat disepanjang pantai (71,21%); tersebar dipedalaman (17,15%), termasuk penduduk yang hidup terpencil dipegunungan, berjumlah kurang lebih 30.000 jiwa, dan selebihnya di daerah kepulauan, (11,64%).
Menurut biasanya, seperti umumnya yang dikemukakan dalam laporan penelitian mutahir 4) SulawesiTengah itu didiami oleh banyak jenis kelompok Etnik (Suku Bangsa), dan terbesar di empat buah Kabupaten, dalam gambar kasarnya sebagai berikut.
Kelompok Etnik (1). Kaili (2). Tomini, (3). Kulawi, umumnya berdian di Kabupaten Donggala. Kelompok-kelompok Etnik (4). Pamona, (5). Lore, (6). Mori, (7). Bungku, umumnya berdiam di Kabupaten Poso. Kelompok-kelompok Etnik (8). Saluan, (9). Balantak, (10). Banggai,umumnya bermukim di Kabupaten Luwuk Banggai. Kelompok-kelompok Etnik (11). Toli-Toli, dan (12). Buol, umumnya bermukim di Kabupaten Buol ToliToli. Dua belas buah kelompok Etnik inilah yang umumnya menjadi pedoman pembagian kelompok Etnik (suku-bangsa) di Sulawesi Tengah.
Cara pengelompokan Etnik tersebut biasanya menurut pengolompokan "bahasa", atau nama tempat pemukiman", mengikuti apa yang sudah dipublikasikan para penelitian sebelumnya.
Di antara kedua belas kelompok Etnik yang manjadi penduduk (asli) Sulawesi Tengah, maka kelompok Etnik Kaili-lah yang terbesar jumlahnya,yaitu kira-kira 45 % dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tengah.
Kelompok kaum atau etnik yang diidentifikasi k rnenurut bahasa yang dipakainya, biasanya digolongk ke dalam narna rumpun bahasa, seperti orang Mela karena berbahasa Melayu, Orang Bugis karena berbaha Bugis; orang Sunda karena berbahasa Sunda dan sebaga nya. Karena pemakaian bahasa itu amat luas terset oleh penutur yang berbeda beda asal tempat tinggalny maka disebutlah misalnya : Orang Melayu Riau; ora Bugis Rappang; orang Sunda Bogor, dan sebagainya. Juga biasa digunakan simbol atau kata tertentu dal suatu bahasa umum yang luas tempat tinggal penuturn tak dapat dibatasi oleh nama tempat saja, maka dipil simbol atau kata khusus dalam dialek bahasa (serumpu itu seperti digunakan oleh Adriani dan Kruijt men identifikasi kan dialek-dialek dalam kalangan apa ya disebutnya Toraja, dengan menggunakan kata sangka seperti Tae, Rai, Ledo, Da'a dan lain-lain yang semu nya berarti "Tidak". Dengan kaitan itu, dibedakann Toraja Tae dari Toraja Data dan'sebagainya.
Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut ci kebudayaan tertentu, seperti To-Panambe, orang ya bermata pencaharian hidup dengan menggunakan al penangkap ikan yang disebut "Panambe": To-Ri-je'n orang (kaum) yang seluruh kehidupannya terletak air. Kelompok kaum yang diidentifikasi menurut temp kediamannya seperti To-Palu, To (ri) Palu, ialah ora atau kaum yang bermukim di Palu, atau yang beras dari negeri Palu.
BAB II
TO-KAILI (ORANG KAILI)
Wilayah ah propinsi/Dati I Sulawesi Tengah, seperti yang disebut pada permulaan tulisan ini, terdiri atas empat buah daerah Kabupaten/Dati II, didiami oleh kelompok-kelompok etnik, secara umum, menurut daerahdaerah Kabupaten itu di kelompokkan sebagai berikut:
1.To-Kaili, dengan sejumlah sub-etnik antara lain, To-Palu, To-Sigi, To-Dolo To-Biromaru, To-Kulawi, To-Parigi dan lain-lain.
2.To-Pamona dengan sejumlah sub-etnik seperti ToMori, To-Bungku dan lain-lain.
3.To-Banggai dengan sekelompok sub etnik yang berdekatan seperti To-Saluan, To-Balantak dan lain-lain.
4. To-Buol Toli-Toli, dengan sejumlah kelompok kaum yang kecil-kecil.
Diantara kelompok -Kelompok etnik itu yang akat menjadi pokok bahasan tulisan ini ialah kelompok etnil To-Kaili. Kelompok etnik To-Kaili inilah yang terbesai jumlahnya, dan persebarannya dalam seluruh wilayah al propinsi yang amat luas. To-Kaili pada dewasa inmenempati jumlah terbesar yang mendiami daerah kabupaten/ Dati II Donggala, dan sebahagian lainnya bermukir di beberapa wilayah ah kecamatan dalam daerah kabupatei lainnya. Orang Kaili mengidentifikasi diri sebagai ToKai, karena adanya persamaan dalam bahasa dan ada; istiadat leluhur yang satu, dipandang menjadi sumbei asal mereka, bahasa Kaili dalam arti Lingua. Fra dalam kalangan semua To-Kaili, digunakan secara umum, Disamping itu terdapat banyak dialek bahasa Kaili van,, juga menjadi identifikasi (sering kali tajam) dari. sut kultur atau sub etnik To-Kaili yang berdiam pada wilayah ah-wilayah ah yang sering kali masih amat terisolasi.
1.To-Palu (To-ri-Palu)
2.To-Biromaru
3.To-Dolo (To-ri-Dolo)
4.To-Sigi (To-ri-Sigi)
5.To-Pakuli, To-Banggai, To-Baluase,To-Sibalaya, To Sidondo
6.To-Lindu
7.To-Banggakoro
8.To-Tamunglcolowi dan To-Baku.
9. To-Kulawi
10.To-Tawaeli (to-payapi)
11..To-Susu, To-Balinggi, To-Dolago
12.To-Petimbe
13.T0-Rarang gonau
14.To-Parigii
Dalam kalangan sub etnik tersebut acap kali terjadi penggolongan yang lebih kecil lagi, dengan ciriciri kliusus, yang kelihatnnya lebih dekat kepada kelompok kekerabatan, yang menunjukkan sifat satuan geneologisnya.
Untuk menemukan pengikat solidaritas dalam kelompok etnik To-Kaili, dicoba diternulcan segala sesuatu yang berbau mitologi, atau cerita-cerita tokoh legendaris atau cerita-cerita rakyat (folk-tale) dalam kalangan To-Kaili dan sub etnik yang terhisap di dalamnya.
To-Kaili yang mendiami Lembah Palu memilki cerita rakyat (folk-tale) yang menjadi pengikat rasa kesatuan To-Kaili tentang asal-usul mereka 4). Tana Kaili yang te-rletak di Lembah Palu (sekarang), menurut ceritera rakyat itu, pada •zaman dahulu kala Lembah Palu ini, masih lautan, di sebut Laut Kai1i atau Teluk Kaili. Nenek moyang To-Kaili pada zainan dahulu itu mendiami lereng-lereng gunung sekeliling Laut Kaili. Konon, di sebelah Timur Laut Kaili itu, terdapat sebatang pohon besar, turnbuh kokoh, tegak dengan kemegahan menjulang tinggi, sebagai tanda pengenal daratan bagi pelaut yang memasuki teluk Kaili. Pohon itu dinamakan Pohon Kaili. Pohon itu tumbuh dipantai dan terletak antara negeri Kalinjo dengan negeri Sigipulu.
Pada suatu hari Laut Kaili mendapat kunjungan sebuah perahu layar yang amat besar, dibawah pimpinan seorang pelaut luar negeri yang namanya sudah arnat tersohor dikawasan ini. Pelaut itu bernama SAGJExIGADING 5). Dikatakan Sawerigading itu, singgah di Teluk Kaili dalam perjalannya kembali dari Tana Cina, menemui dan mengawini tunangannya yang bernama We Cudai. Tempat yang disinggahi pertama oleh perahu Sawerigading, ialah negeri Ganti, ibu negeri Kerajaan Banawa (sekarang Donggala). Antara raja Banawa dengan Sawerigading terjalinlah tali persahabatan yang dilcolcohkan dengan perjanjian ikatan persatuan dQngan kerajan Bugis-Bone, di Sulawesi-Selatan 6). Dalam menyusuri teluk lebih dalam ke arah Selatam sampailah Sawerigading dengan perahunya ke pantai negeri Sigipulu, dalam wilayah ah kerajaan Sigi. Perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan Uwe Mebere, yang sekarang berna~-na Ranoromba. Kerajaan Sigi dipimpin oleh seorang Raja Wanita yang bernama Ngginayo atau Ngili Nayo 7). Raja perempuan ini, belum kawin dan berparas amat cantik. Setibanya di Sigi Sawerigading bertemu langsung dengan raja Ngilinayo yang amat cantik itu. Pada pandengan pertama Sawerigading jatuh cinta. lapun mengajukan pinangan untuk menjadikannya pei-maisuri. Raja Ngilinayo bersedia rnenerirna pinangan Sawerigading dengan syarat ayarn aduannya yang bergelar Calabai 3). dapat dikalahkan oleh ayam aduan Sawerigading yang bergelar Bakka Cimpolon,g (Bg), yaitu ayam berbulu kelabu ke hijauan, dan kepalanya berjambul. Syarat itupun disetujui oleh Sawerigading, dan disepakati, upacara adu ayam itu akan dilangsungkan sekembal Sawerigading dari perjalanan ke pantai Barat, sambi di persi.apkan arena (Wala-wala) adu ayam.
Di pantai Barat perahu Sawerigading berlabuh di pelabuhan negeri Bangga 9). Raja Bangga seorang pe rempuan bernama Wumbulangi di gelar Magau Bangga, yan diceritralcan sebagai To-Manuru 10) Sawerigadingpu menemui baginda dan mengikat perjanjian persahabatan dalam daftar silsilah raja-raja Bangga, Wumbulang adalah Ma~au pertama kerajaan Bangga.
Setibanya di Sigi, Arena untuk penyabungan ayan di atas sebuah gelanggang (wala-wala) sudah dipersiapkan. Ayarn sabungan Sawerigading Bakka Cimpolonp yang akan bertarung melawan Calabai ayam Ngilinayo, semuanya siap di pertarunglean. Pada malam harinya telah diumumkan kepada segenap Iapisan masyarakat, tentank pertarungan yang akan berlangsung ke-esokan paginya. Akan tetapi sesuat.u yang luar biasa telah terjadi pada malarn sebelum pertarungan itu berlangsung, yang menjadi sabab dibatalkannya pertarungan itu.
Anjing Sawerigading yang digelar La-Bolong (SiHitam) turun dari perahu, berjalan jalan di darat Sigi. La-Bolong berjalan ke arah Selatan. Tanpa disadarinya, ia terperangkap kedalam satu Iobang besar, ternpat kediaman seekor belut (Lindu), yang amat besar. Karena merasa terganggu oleh kedatangan anjing labolong yang tiba-tiba itu, maka belut/lindu itupun menjadi marah, dan menyerang La Bolong, maka terjadilah pertarungan yang amat sengit antara keduanya. Pertarungan itu demikian dahsyatnya, sehingga seolah-olah terjadi gempa yang menggetarkan bumi. Penduduk pun menjadi, ketakutan. La-Bolong berhasil menyergap belut/lindu itu, keluar lobangnya. Lobang besar bekas tempat tinggal belut/lindu itu, setelah kosong dan runtuh, lalu menjadi danau, yang hinga kini disebut Danau Lindu.
Anjing Sawerigading La-Bolong melarikan belut itu kearah Utara dalam keadaan meronta-ronta, dan menjadikan lubang berupa saluran yang dialiri oleh air laut yang deras, air yang mengalir dengan deras itu, bagaikan air bah yang tumpah, menyebabkan keringnya air Kaili. Maka terbentuklah Lembah Palu dan terjelmalah Tana--Kaili.
Peristiwa alam yang amat dahsyat ini, membatalkan pertarungan kedua ayam yang telah dipersiapkan dengan cerrnat. Raja Ngilinayo dan Sawerigading sama-sama berikrar untuk hidup sebagai saudara kandung yang saling menghormati i untuk bekerja sama membimbing orang Kaili yang mendiarni Lembah Palu, bekas Teluk Kaili, yang telah menjadi daratan.
Air yang mengalir deras ke laut lepas Selat Makassar menghanyutkan perahu Sawerigading, yang akhirnya terdampar di Sombe. Ceritera rakyat rnenyebut, bahwa gunung yang menyerupai perahu di Sombe itu, adalah bekas perahu Sawerigading yang sekarang di Bulusakaya, yang berarti gunung yang berbentuk perahu. Alat-alat perlengkapan perahu lainnya, antara lain layar, terdampar di pantai sebelah Timur. Tempat itu kini bernama Bulumasomba, artinya gunung yang menyerupai layar.
Sebuah versi lain, mengenai ceritera persaudaraan antara Raja Ngilinayo dengan Sawerigading, menyebutkan bahwa pada menjelang akan diadakannya pertarungan ayam, di adakanlah pesta atau keramaian yang dikunjungi oleh sebahagian besar penduduk kerajaan Sigi. Ferangkat alat kesenian, bunyi-bunyian berupa gong, tambur dan seruling, didaratkan dari perahu Sawerigading, untuk meramaikan pesta kerajaan itu. Gong, tambur, dan genderang dipalu bertalu-talu, memeriahkan pesta itu, mengundang kera:iaian yang gegap gempita. Urang sakitpun yang tadinya terbaring lemah di pembaringan masing-masing, setelah mendan gar bunyi-bunyian itu. Merekapun menghadiri pesta keramaian itu. Penyembuhan dari penyakit, berkat mendan garkan bunyi-bunyian yang mengiringi nyanyian (t'embang), yang diperagakan dengan tari-tarian, dipercaya sebagai obat mujarab. Pengobatan dengan cara itu, disebut Balia, dari dua kata bali + ia artinya lawan ia. Maksudnya setan atau roh jahat yang membawa penyakit harus dilawan.
Puncak acara keramaian malarn itu, ialah peresmian atau pengukuhan sumpah setia persaudaraan antara raja Sigi Ngilinayo dengan Sawerigading. Segenap perangkat alat bunyi-bunyian, diserahkan oleh Sawerigading kepada saudaranya, yaitu Raja Sigi Ngilinayo. Seusai pesta Kerajaan itu, kembalilah Sawerigading dengan anak buahnya ke perahu. Setelah mereka tiba di perahu, mereka dikejutkan oleh adanya getaran bumi yang dahsyat disertai deru air yang bagaikan tautan keras. Dikatan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah kareria pergelutan antara Labolong dengan belut/lindu, seperti diceriterakan didepari. Perahu Sawerigadirlg terlepas dari tambatannya, dan hanyut mengikuti arus air ke laut.lepas, Selat Makassar. Berkat lcetangkasar: awak perahu Sawerigading, menyelematkan perahun,da dari malapetaka. Mereka melepaskan diri dari Teluk Kaili yang sudah menjadi daratan, dan selamatlah Saweriading meneruskan perjalanannya kembali ke Tana-Bone Sulawesi-Selatan).
Sawerigading adalah tokoh legendaris dalam ceritera rakyat Tana Kaili. Tokoh itu dihubungkan dengan kedudukan Kerajaan Bone, sebagai kerajaan Bugis di Sulawesi-Selatan yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kai1i. Dapat diperkirakan bahwa hubungan-hubungan yang akrab dengan kerajaan Bone dengan kerajaan-kerajaan di Tana Kaili, berlangsung dalam abad ke-17. Adapun tokoh lagendaris Sawerigading di Sulawesi Selatan tersebut dalaiu Epos La-Galigo, dipandang sebagai peletak dasar dan cikal bakal raja-raja Bugis, khususnya di Kerajaan Lucau, yang terletalc pada bahagiaii Utara Selat Bone. Zaman Sawerigading dalam Epos La-Galigo, diperkirakan berlaiigsung dalam abad IX dan X (M). Kedua keadaan itu dalam cerita rakyat Tana Kaili, yaitu tokoh iegendaris Sawerigading dan hubungan persahabatan dengan kerajaan Bone, dipadukan saja sebagai pe-ristiwa istimewa dalam suatu cerita rakyat. Hal seperti itu, adalah biasa dan menjadi karastrestik umum dari suatu cerita rakyat (Folk-Tale), untuk memperoleh semacam pengukuhan legitimasi bagi tokoh-tokoh yang tersangkut dalam peristiwa luar biasa 12). Mungkin sekalli dapat dibuktikan kebenaran ilmi.aluiya, melalui penelitian (arkeologi atau paleoantropologi), bahwa sekitar abad IX-X (M), Lembah Palu masih merupakan lautam sampai negeri Gangga dekat Danau Lindu. Setelah Laut Kaili menjadi daratan, yang membentuk Tana-Kai di Lembah Palu, maka terjadilah hubungan dangan kerajaan Bone dan Gowa yang menguasai perairan Selat Makassar. Ketika itu Kompeni Belanda (VOC) juga sudah mulai melakukan kegiatan intervensi terhadap kerajaan kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Peristiwa-peristiwa penting itu justeru terjadi dalam abad ke XVII. Sekitar abad itu , kerajaan Bone mengunggu kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan di baw pimpinan Aruppalakka, To-Erung malamppee' Gemme' n Ketika itu Kerajaan Bone melakukan hubungan baik m lalui daratan, maupun lautan ke bahagian Timur d Barat Nusantara, termasuk Sulawesi Tengah dan Utar Tana Kaili dan kerajaan Banawa amat banyak di sebabkan dalam Lontara Bugis-Makassar tentang hubungannya , politik dan persaudaraannya dengan negeri-negeri Bugis yang menguasai pelayaran Selat Makassar.
Pada dewasa ini, persebaran pemukiman To-Kaili propinsi Sulawesi Tengah, meliputi sebahagian terbes Kabupaten/Dati II Donggala, dan beberapa wilayah Kecamatan dalam Kabupaten/ Dati II Poso, Banggai d Buol Toli-Toli. Kelompok etnik Tiriombo, Tomini d Moutong yang mendiami pesisir sebelah Timur di Tel Tomini, tadinya masih dapat dipertajam identifikasinya yang berbeda dari kelompok etnik To-Kaili. Teta kini, dilihat dari perkembangan persebaran penerima unsur-unsur kebudayaan yang sama,: maka perbedaa perbedan itu menjadi sangat tipis. Malahan percampur rnelalui jalan kawin-mawin yang amat banyak, teruta dalam kalangan pemuka adat dan masyarakat Kaili dan g To-Tinombo, To-Tomini dan To-Moutong, perbedaan yang pernah mempertajam identifikasi etnik masing-masi kini sudah mencair.
Cacah jiwa orang Kaili yang tersebar luas dal Propinsi Sulawesi Tengah, diperkirakan 45 % dari seluruh penduduk Sulawesi Tengah, yaitu kira-kira 4 sampai 5 ratus ribu jiwa. To-Kaili pada umumnya atau terbanyak bermukim di sepanjang pantai, baik di pesisir Barat, maupun dipesisir Timur. Oleh karena itu, maka cara hidup clan kebudayaan Kaili yang dominan, kelihatan lebih dekat kesamaannya kepada kebudayaan Bugis-Makassar (Sulawesi-Selatan), dan kebudayaan Melayu (Sumatera dan Malaka ).
Selain dari pada kelompok etnik Kaili, Pamona, Buol Toli-Toli, Banggai dan lain-lain, seperti telah disebut pada bahagiarr depan, masih terdapat lagi keiompok-kelompok etnik dalam jumlah warganya yang tidak , terlalu banyak, tetapi mereka dipandang' sebagai penduduk asli Sulawesi Tengah. Mereka itu kini disebut suku-suku terasirlg, seperti : Lauje, Tajio, Pendau, To-Lare,. Rarang Gonau, Loon , Sea-sea, Daya dan mungkin masih ada lagi lainnya yang belum di kenal. Kelompok-kelompok etnik itu yang jumlah warganya relatif kecil, mendiami lereng gunung secara terpencar-penca-r dalam hutan-hutan. Mereka rnenggunakan bahasa atau dialek tersendiri dalam kehidupan yang terisolasi itu. Secara umum dapat ditandai keadaan fisik mereka yang berbeda dalam dua golongan. Pada umumnya To-Lare (Orang 'gunung) yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Barat Lembah Palu, disebut juga Tolare-bulumpanau, memiliki warna kulit yang agak cerah. Sebaliknya To-Tare yang bermukim di lereng-lereng gunung sebelah Timur Lembah Palu disebut juga To-Lare-Bulungpadake, memillki warna kulit gelap.
Kelompok- Kelompok Sub-etnik Kaili seperti yang disebut pada bahagian depan masing--masing rnemiliki kekhususan baik mengenai ceritera tentang asal usul, maupun dialek serta pernyataan kulturalnya, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :
1.Penduduk asli Lembah Palu. Di Lembah Palu dan sepanjang pantai teluk Palu bermukim To-Kaili, sebagai satu kelompok etnik di kawasan ini 14). Penduduk Lembah Palu, terdiri atas beberapa kelompok sub-etnik atau kelompok kaum, dengan dialekdialek bahasa masing-masing.
Pemukiman awal ke-empat kelompok kaum ini, mehurut petunjuk yang diketemukan sekarang, adalah sebagai berikut:
To-ri Palu, bermukim pada bagian Utara lembah, sepanjang dua sisi muara Sungai Palu.
To-Biromaru dan To-ri Sigi, bermukim di bagian Selatan To-ri Palu, pada sebelah kanan daerah aliran sungai Palu, dengan kekecualian bagian kecil sebelah Utara Wunu, di sana berdiam To-ri Dolo, bermukim di sebelah Selatan To-ri Palu, pada bagian ki-ri daerah aliran Sungai Palu. Di lereng-lereng gunung bagian Utara Lembah Palu juga sudah berdiam sejak dahulu kala penduduk yang disebut To-Lare (Orang gunung). Disamping To-Lare terdapat juga To-Petimpe, yang berdiam di lerenglereng gunung sebelah Utara lembah, terutama dalam wilayah ah Palolo. To-Petimpe secara etnik tidak banyak hubungannya dengan penduduk asli Lembah Palu. Menurut berbagai keterangan To-Petimpe itu, keturunan To-Balinggi dari Tana-Boa di Teluk Tomini, atau mungkin juga dari To-Pebato, satu kaur yang berdiam di muara sungai Puna.
Pada bagian yang agak jauh ke Selatan Lembah Palu, sekitar Gumbasa, Miu, Salcuri pada daerah aliran Sungai Palu, terdapat dua kelompok kaum yaitu To-Pakuli sekitar Gumbasa dan Miu, dan To-Sakuri sekitar Miu. Disana terletak negeri Bangga yang penduduknya berbahasa sama dengan To-Pakuli.
2.To-ri Palu dan To- Biromaru. Penduduk Lembah Palu, berasal dari pegunungan sekitar Lembah Palu itu juga. Ketika bermukim di Lerabah Palu, sejak awalaya-pun, mereka telah berkelompok l:e dalam tiga buah kaum, yaitu : To-ri Sigi, To-ri Dolo dan To--ri Palu.
Berbagai cerita rakyat yang samar-sarna diingat melaiui ceritera atau tutur o-ang tua-tua, bahwa ketiga kaum irri, acapkali saling memerangi antara satu sama lainnya. Karena begitul;ah mereka dalam bermukim di Lernbah Paiu, masing -masing memilih tempat yang secara alamiah terlindung dari upaya serangan-serangan terbuka dari pihak lawarrnya. Malahan ada kecenderungan mempertahanl sosialisasi mereka satu sama lainnya.
To-ri Palu yang rnendiami wilayah Palu, kabarnya berasal dari pegunungan sebelaii Timur. Di Tempat asal mereka, dipegunungan itu, terdapat satu tempat yang bernama Buluwatumpalu, disana bertumbuh banyak tanarnan barnbu yang dipergunakan dalam kehidupan. Untuk mengingat asal nama negeri Buluwaturnpalu yang berarti bambu kecil, maka tempat yang mereka pilih untuk bermukim, yaitu di muara sungai besar yang sekarang bernarna Sungai Palu, disebutnya dari kata itu, yaitu mPalu (kecil). Di mana letak tempat yang disebut Buluwatumpalu itu, diperkirakan di salah satu tempat di atas bukit Paneki sekarang, yang disebut Raranggonau.
Adapun To-Biromaru, diduga keras berasal dari leluhur yang sama dengan To-ri Palu, yang sama-sama menggunakan dialek Kaili-Ledo. Pemelcaran menjadi kaum sendiri itu, terjadi kemudian setelah pemisahan tempat pemukiman.
To-Biromaru mendiarRi tempat yang lebih kedalam di daerah lereng dalam lembah yang subur. Pemisahan menjadi dua kelompok kaum itu terjadi sebelum abad ke-XVII 17).
3.To-ri Sigi, To-ri Dolo.
Menurut catatan Valentijn (1724), To-ri Sigi dan To-ri Dolo diperkirakan sudah bermukim di Lembah Palu sejak ak'nir abad XVII atau pada permulaan abad XVIII. Kedua kelompok kaum ini, menggunakan dialek bahasa Kaili yang sama, yaitu dialek Ija. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berasal da,ri leluhur yang sama. Akan tetapi sejarah kehidupan mereka sejak awal, selalu diwarnai oleh permusuhan dan peperangan antara keduanya.
Dari mana asal kedua kelompok kaum ini pada mulanya sebelum bermuhim di Lembah Palu, terdapat beberapa keterangan. Salah satu cerita yang hampir sarna dengan keterangan Hissink, diterlukan dikalangan penduduk Sigi, sebagai berikut. Sebelum To-ri Sigi bermukini di Lernbah Palu, yaitu di Bora, Watunonju, Oloboju dan Sigi, leluhur merelca berrnukim di sele,lah utara Danau Lindu di lereng-lereng gunung, di terapat-tenlpat pemukiman yang disebut Leu, Silonga, Wowolau, Ue-hialaei dan Sigipulu.
Mengenai To-ri Dolo, menurut beberapa cerita rakyat, dikatakan berasal dari daerah pegunungan yang lebih ke Utara lagi letaknya dalam tempattempat pemukiman yang bernama Dolo, Maru dan Pompewajo. Dimana tempat-tempat itu terletak di lerenglereng gunung sekarang, tidak diperoleh petunjuk yang jelas dari penduduk. Tetapi nama-nama itu, masih ada mengingatnya. Kemungkinan besar, bekasbekas pemukiman To-ri Sigi terletak sekitar negeri Palolo sekarang, tempat-tempat pemukiman awal ToDolo, justru terletak sekitar negeri sekarang.
4.To-Pakuli; To-Pakuli; To-Bangga;To-Baluase; ToSibalaya; To-Sidondo adalah kelompok-lcelompok kaum dalam komunitas yang kecil-kecil. Mereka bermukim di sebelah Selatan wilayah ah pemukiman To-ri Sigi. Mereka menggunakan dialelc bahasa Kaili yang disebut Ado atau Edo. Dialek Ado amat dekat kepada dialek Ija yang dipergunakan oleh To-ri Sigi diperkirakan sebelum mereka bermukim di Lembah Palu, mereka berdiam di lereng-lereng pegunungan sebelah Timur dan Tenggara Lembah Palu.
5.To-Tawaili (To-Yayapi). Dalam iembah sebelah utara Napu hiduplah pada zaman dahulu sekelompok kaum yang menamakan diri To-Tawaeli atau To-Payapi. Karena berbagai gangguan dari kaum di sekitarnya lalu berpindah melewati sebelah Utara Danau Lindu, melintasi nege-ri Sigi dan akhirnya sampai ke Budong-Budong, di sebelah Selatan Donggala di pantai Selat Makassar. Sebagiaii lainnya menetap di Sausu, Dolago dan Parigi.
Pada dewasa ini, To-Tawaeli yang bermukim di wilayah ah Kecamatan Tawaeli yang terletak di sebelah Utara Kota Palu, dalam cerita rakyat yang sudah samar-samar dalam ingatan para penuturnya mengatakan bahwa To-Tawaeli berasal dari bagian Selatan pantai Selat Makassar.
6.To-Lindu, bermukim sekitar Danau Lindu. Mereka percaya dan mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lembah Palu. Para pemimpin adat Lindu atau keturunan mereka yang ada sekarang, selalu menyatakann diri berasal dari Sigi di Lembah Palu. Keterangan seperti juga dijumpai pada umumnya dalam kalangan penduduk lereng-lereng pegunungan sebelah Selatan di lembah Palu, bahwa nenek moyang mereka berasal dari Sigi.
7.To-Banggakoro. yang mendiami daerah pegunungan jauh di sebelah barat Kulawi dapat dikatakan secara kebudayaan lebih banyak bersentuhan dengan kebudayaan Mamuju di pantai Barat dan kebudayaan Lembah Palu di sebelah Utara. Asal mula penduduk terdahulu To-Banggakoro tak dapat ditemukan dalam ceritacerita rakyat. Akan tetapi besar sekali persamaan kelompok kaum ini (To-Banggakoro) dengan penduduk Bangga yang berasal dari bagian Selatan Lembah Palu.
8.To-Tamungkolowi; To-Tabaku, berdiam di atas pegunungan sebelah Barat negeri Kulawi. Tidak ditemukan legenda ataupun ceritera-ceritera rakyat yang memperkatakan tentang asal usul mereka. Akan tetapi berbagai ungkapan dan benda-benda kebudayaan sub-etnik'ini, seperti sebutan Sou-eo, dan pakaian atau alat-alat perhiasan wanita dan tata rambutnya,sama dengan yang pada umumnya terdapat di Lembah Palu. Dari pengamatan-pengamatan yang lebih dekat dan lama dapat dikatakan bahwa To-Tamungkolowi dan To-Tabaku, juga pada awalnya berasal da-ri bahagian Selatan Lembah Palu.
9.To-Kulawi, yang berdiam di sebelah Selatan Danau Lindu, menurut legenda,mereka berasal dari Bora dan Sigi di Lembah Palu. Menurut ceritera rakyat, bahwa pada zaman dahulu kala, ada seorang bangsawan dari Bora bersarna pengikutnya berburu ke hutan-hutan dan gunung Momi di daerah Kulawi yang masih lengang. Para pemburu berteduh dibawah pohon yang amat rimbun.dan lebat daunnya. Mereka namakan pohon itu, pohon Kulawi.Jenis pohon itu sekarang tidak ditemukan lagi.
10.To-Sausu; To-Balinggi; To-Dolago, diantara Sungai Tambarana dengan Parigi di Pantai Timur SulawesiTengah, terdapatlah negeri-negeri Sausu, Tana -Boa dan Dolago. Disitulah kelompok-kelompok kaum yang menyebutkan diri To-Balinggi dan To-Sausu berdiam. Menurut ceritera rakyat, baik To-Sausu maupun ToBalinggi berasal dari keturunan yang sama yang disebut To-Lopontato yang bermukim di lereng-lereng gunung. Kaum ini amat erat hubungan kebudayaanya dengan To-Parigi. Adapun To-Dolago menurut ceritera rakyat itu, juga adalah dari suatu keturunan dengan kedua kaum lainya, yaitu To-Sausu dan To-Dolago. Tetapi kemudian hidup memisahkan diri karena lingkungan alam, tetapi tetap merasa mempunyai hubungan kekeluargaa<< dengan To-Parigi, juga dengan To-Sigi.
11.To-Parigi. Negeri Parigi terletalc di sebelah Utara Sausu di Teluk Tomini. Pada umtlimnya penduduk negeri Parigi yang disebut To-Parigi percaya bahwa nenek rr,oyang rnereka, berasal dari Lembah Palu. Akan tetapi dalam perkembangan masyarakat Parigi selanjutnya, banyak juga terjadi kontak dengan kelompok etnik Panona dari Wilayah ah Poso, sehingga beberapa pengamat menduga, bahwa orang Parigi dapat digolongkan ke dalam kelompok etnik Pamona-Poso.18).
Dapat diduga ballwa oi-ar,g Kaili yang sekarang me diami Lembah Palu, berasal dari arah Tenggara Utara Barat Daya, yaitu dari daerah sebelah Uta Danau Poso. Ada yang bergerak kearah Baiat dan ke a-r pantai Teluk Tomini, dan ke aril Selatan dan Tim Lembah Palu hingga pantai Seiat Makassar.
BAB III
SEKELUMIT SEJARAH KEBUDAYAAN KAILI
Tempat awal pemukiman sesuatu kaum yang pada hakekatnya terpisah-pisah, malahan terisolasi dari tempat pemukiman kaum lainnya, biasa disebut Ngapa. Da-ri Ngapa itulah dimulai peradaban sesuatu kaum, yang lambat laun berturnbuh jumlah warganya dan memekari:an tempat-tempat pemukiman baru itu. Tempat-tempat pemukiman baru disekitar Ngapa itu, selaku perluasan pemukiman kaum perluasan kaum seasal biasanya disebut Boya atau Soki.
Tempat penukiman lain yang terbentuk oleh adanya lapangan pekerjaan tertentu seperti komunitas (persekutuan) tani atau nelayan dinamakan Kinta. apabila pada suatu waktu perkembangan Ngapa menjadi sudah cukup luasnya ole'n dukungan sejumlah Boya, Kinta dan Soki, maka terbentuklah satu wilayah a territorial dengan susunan kekuasaan yang ditaati- oleh penduduk. Terbentuklah apa yang dinamakan secara umum kerajaan lokal, yang dapat disebut "Kagaukang" atau "Kagau".
Menurut berbagai sumber, 1) sebelum terjadinya struktur kerajaan yang disusun dalam perangkat kekuasaan pejabat-pejabat secara hierarchis, sesuatu wilayah ah pemukiman kaum yaitu Ngapa atau sejenisnya dikuasai atau dipimpin oleh orang yang disebut '1'0Malanggai. Ia adalah pemimpin yang dipandang perkasa, seorang jantan yang mengatasi jantan-jantan lainnya. la-pun dapat disebut "penakluk" atas kaum yang bermukim disekitarnya. Dasar kepemimpinannya adalah keberanian, kepeloporan, untuk mengungguli orang-orang atau kaum yang dipimpinnya.
BAB IV
MODAL PERSONALITY ORANG KAILI
Konsep MODAL PERSONALITY, atau kalau hendak diterjemahkan secara sederhana, dapat disebut PERASAAN KKPKIBADIAN. Penguraian tentang modal-personality, pertama-tama akan menghadapi secara serius persoalan metodologis, untuk penerapannya. Kita akan menghadapi suatu masyarakat dengan segala persoalannya yang amat rumit. Wilayah ah masyarakat itu yang seringkali amat luas, aneka ragam pranata dan lembaga sosial; aneka macam lingkungan alam tisik darn kebudayaan; aneka macam iklim yang dibawa oleh aneka macam keadaan lingkungan, seperti gunung, lembah dan dataran yang membentang luas, semua itu secara metodologis harus diperhitungkan dalam penelitian atau pengamatan yang diperlukan, untuk melukis kan PERASAAN KEPRIBADIAN itu. Oleh karena itu, suatu perkiraan umum yang dipandang representatit atau secara wajar mewakili segenap keadaan yang sesungguhnya amat diperlukan. Tentu saja sangat di perlukan adanya sampling secara statistik dari berbagai daerah kesatuan hidup, atau kelompok sosial, jenis-jenis lapangan pekerjaan, tingkat usaha dan lain-lain, untuk mendapatkan gambaran yang sungguh-sungguh dapat memuaskan, sebagai gambaran umum tentang perasaan kepribadian sesuatu kaum, seperti yang akan dilukiskan disini, yaitu YEKASAAN KEPRIBADIAN ORANG KAILI.
Dalam pengertian umum, tulisan ini hendak mencota melukiskan ciri-ciri kepribadian To-Kaili, melalui perasaan kepribadian yang ditampilkan dalam berbagai tata kelakuan dalam kehidupan yang membudaya atau bernilai budaya. la secara aktual dianut atau dihargai sebagai perilaku sosial dan secara umum dilakukan dalam kehidupan. Deilgan kata lain, apa yang dilakukan atau diperbuat oleh orang Kaili, sehingga ia merasa diri sebagai To-Kaili.
Sesuatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan yang bermakna ke-Kaili-an, karena seseorang (Kaili) yang melakukannya merasa diri orang Kaili, ('To-Kaili). To-Kaili lainnya melihat ia melakukari perbuatan itu, segera mengetahui bahwa ia adalah To-Kaili. Maka antara yang melakukan dengan yang mengamati kelakuan itu tumbuh tali perhubungan yang alafniah sebagai hubungan keakraban (familiar). Karena apa yang diamati itu seolah-olah adalah dirinya sendiri. Ia akrab dengan perilaku atau tingkah laku seperti yang dilakukan dalam kebudayaan Kaili.
Patokan-patokan umum yang dapat dipergunakan dalam menjaring perasaan-perasaan kepribadian itu, adalah biasanya perbuatan-perbuatan atau perilaku yang amat lekat pada kehidupan emosional atau yang menyentuh perasaan-perasaan terdalam, seperti pada perasaan hidup :
1.Kekerabatan dan kenasyarakatan,
2.Keagamaan dan kepercayaan,
3.Bahasa, kesusasteraan dan kesenian pada umumnya.
Pertemuan-pertemuan, berupa pesta-pesta dalam keluaga, membuka kesempatan bagi para remaja untuk saling bertemu dan berkenalan, melalui perkenalan di pesta-pesta itu, terjalinlah hubungan-hubungan yang akan mengantarkan ke(-'Iua remaja yang saling mencintai itu, untuk memasuki tingkat hubunban formal menuju perkawinan/pernikahan.
UPACARA PEMINANGAN : Upacara-upacara pernikahan, lebih banyak memperlihatkan segi-segi formal yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Hal-hal yang formal itu dilakukan untuk saling memberikan kesan tentang adanya kesungguhan kedua belah pihak untuk membangun pertalian keluarga besar.
Rangkaian upacara menjelang hari pernikahan, merupakan formalitas yang kelihatannya amat cermat dijalankan. Orang menamakannya upacara adat, untuk menjaga harmoni dalam kehidupan. Menurut ceritera, adapun NOTATE DALA (upacara manbuka jalan) dilakukan, untuk menjaga agar tidak terjadi penolakan pinangan, atau gadis itu telah ada yang meminangnya lebih dahulu. Kalau terjadi yang demikian, dahulu kala dipandang rnembawa aib bagi keluarga laki-laki.
Dalam upacara peminangan, berbagai benda yang bermakna simbolik diantarkan oleh pihak laki-laki yang diberikan oleh pihak pererrrpuan, antara lain sebagai berikut: SP.MPULOIGI (perbiasan emas perak buat perernpuan). SABALE KAMAGI (buah kalung emas).
Berbagai upacara adat dalam pelaksanaan acara perkawinan seperti tersebut di atas dilakukan dengan sedapat mungkin menampilkan idan titas keluarga yang menjadi penyelenggranya. Upacara itu menunjukkan kedudukan keluarga itu dalan masyarakat, sesuai nilai dan norma yang berlaku. Pada upacara itu ditampilkan ke
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
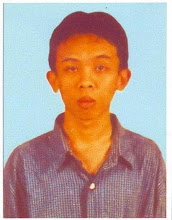
Tidak ada komentar:
Posting Komentar